Series ATLA di Netflix Gak Sebagus yang Orang Bilang
Watching ATLA on Netflix is such of wasting time. NGL. Untuk saya yang sejak awal kemunculannya sudah sangat menyukai Avatar: The Legend of Aang ini, saya cuma berharap ATLA gak akan di live action-in lagi. Saya mau bilang “Sudah, lah. Jangan rusak ATLA lebih jauh.”
Entah kenapa saya selalu merasa upaya-upaya yang dilakukan dalam alih wahana anime ke live action adalah upaya suicide. Usaha Netflix menyajikan efek tentu saja melampaui standar, tapi ya cuma sebatas melampaui saja. Gak ada yang benar-benar wow juga. Semuanya sangat biasa dan sekadar lulus KKM.
Saya rasa dari semua film yang sudah saya tonton sejauh ini dengan zaman yang secanggih sekarang, efek-efek yang ditampilkan Netflix itu wajar dan sebenarnya bisa kita dapatkan di film adaptasi pertamanya itu. Saya rasa, untuk efek-efekan juga Lion King masih lebih bagus, karena bikin saya beneran mikir “Itu hewan beneran atau animasi sih?!”
Sebagai orang yang sedikitnya 2 tahun pernah ada di panggung teater, saya yakin garapan film adaptasi/live action tuh bakal sangat membebani. Misalnya gini. Ambillah Pengabdi Setan sebagai contoh adaptasi. Secara tidak langsung, saya merasa Joko Anwar dan tim sedikit banyaknya pasti punya beban semacam, “Film ini harus lebih bagus dari pada film yang sebelumnya.”
Pun dengan live action One Piece yang dibebani dengan nama besar dan jumlah fans di seluruh dunia itu. FYI, rating live action One Piece ternyata jauh lebih tinggi daripada live action ATLA. Saya bukan penggemar One Piece, ya. Jadi saya memang gak bisa nilai keberhasilan live action One Piece. Yang jelas, sekonyong-konyong series ATLA di Netflix ini malah nyungsruk dan cuma punya satu hal yang bikin dia terlihat bagus yaitu kegagalan film adaptasi sebelumnya.
Karakter
Celakanya, dalam menggarap live action, segenap tim diharuskan buat “memunculkan” tokoh yang semirip mungkin looks-nya dengan tokoh yang sudah ada. Tokoh yang sudah sering kita lihat, tokoh yang akrab di pandangan. Yang membuat kita -atau saya- sebagai penggemar, punya ekspektasi tertentu ketika 2D itu dikonversi ke dimensi manusia.
Saya takut ini akan jadi bias semacam body shaming atau apalah, tapi entah kenapa itu Azula, Ty Lee, dan Mai terlihat sangat cringe di mata saya. Yes, I know it sounds so bad but it happens.
Awalnya saya meragukan pemeran Zuko yang secara fisik memang “kurang tinggi” kalau dibandingkan dengan tokoh di animenya, tapi pemeran Zuko punya ambience yang membawa saya yakin “Oh iya ini Zuko.”
Kadang kan bisa ya, kita lihat satu karakter atau satu tokoh di sebuah film yang meskipun secara fisik orang itu gak mirip sama karakter itu, tapi kita bisa tahu kalau orang itu mirip. Misal Ahmad Farid dan Suneo. Meskipun secara fisik mereka jauh berbeda, tapi kalau kelakuan dan ambiencenya sama, ya saya akan bilang,
“Ih Farid! Kamu teh siga Suneo!”
Nah, kemiripan Farid dan Suneo ini bisa saya temukan di Zuko 2D dan Zuko live action. Saya rasa Zuko live action ini membawa grief yang entah dari mana, tapi saya sebagai penonton bisa ngerasain grief itu muncul dengan intens dan berhasil membuat saya yakin kalau meskipun tidak terlihat persis seperti Zuko, tapi aktor ini sukses memerankan Zuko. Sokka, secara konstruksi wajah, dari semua pemeran utamanya Sokka ini paling mirip loh sama 2Dnya. Tapi actingnya sangat gak natural. Alih-alih terlihat sebagai cowok yang menjengkelkan, Sokka hanya terlihat sebagai cowok canggung di setiap waktu. Bukankah Sokka orang yang super duper percaya diri?
Beda hal sama pemeran Zuko, saya merasa Azula, Mai, dan Ty Lee ini someway too pushy alias terlalu maksa. Realitanya, di kehidupan nyata saya gak masalah ya sama looks, tapi ketika itu sudah jadi live action dari sebuah anime, saya rasa looks itu mengambil porsi banyak dalam memengaruhi cerita.
Ya masa Azula, Ty Lee, dan Mai gak ada lincah-lincahnya? Ty Lee kan pemain sirkus. Dia juga sering banget jalan pakai tangan. Azula kenapa jadi anak kecil yang hobi nge-jagger di kelas, sih?! Please, Azula. Kamu terlalu konyol.
Menurut saya, daripada ditampilkan di awal dan malah merusak, saya lebih suka kalau Azula, Mai, dan Ty Lee tidak ditampilkan sama sekali. Saya gak tahu siapa yang mengarahkan mereka bermain peran sejelek itu, tapi ambience dan perasaan yang saya dapatkan ketika saya melihat karakter itu ya sangat kacau dan gak beraturan.
Come, on! Netflix bisa lebih baik dari ini. Lagian, tolong deh. Paman Iroh tidak segurung-gusuh itu, dan Aang tidak seserius itu. Tapi di atas semua, yang paling menyentuh saya adalah pemeran Bumi. Kekacauan, kekecewaan, depresi, saya bisa lihat itu di Bumi, sih. Pas obrolan Bumi sama Aang ini tuh astaga, saya ngelihatnya kaya Bumi ingin banget mengakhiri hidupnya karena beban, tanggung jawab, dan perang yang selama ini ia lihat gitu.
Alur yang Buruk
Semuanya sangat buru-buru, sampai-sampai tidak ada karakter Haru. Sampai-sampai gak ada Pakku sadar kalau kalung yang dipakai Katara adalah kalung buatannya. Secara feels juga jadi aneh. ATLA di live action berwarna sangat serius, dipaksain konyol tapi garing, dipaksain bijak tapi malah blunder. Saya kecewa saja dengan “maju-mundurin” alur seenaknya. Kenapa pula banyak adegan di Book 2 yang masuk ke Book 1?!
Tuh, kan. Hal kecil aja udah bikin marah, apalagi hal besar. Live action tuh risikonya gede banget, dan karena saya kritikus (kata sendiri), jadi untuk ATLA versi Netflix ini saya kasih 4/10. Coba kalau saya disuruh bikin film? ya gak bisa, lah! Kalau bisa kan gak jadi komentator yang julid doang kayak gini. Heu.
Arini
Menulis puisi, prosa, melukis, dan bermusik. Buku kumpulan puisinya As Blue As You telah diterbitkan di Pustakaki Press. Juni 2023 telah mengadakan Pameran Tunggal bertajuk A Quarter Century untuk mempertunjukkan hasil lukis sekaligus merayakan kelahiran buku keduanya, Jayanti. Aktif membuat konten di Arireza.
- Trending
- Comments
- Latest
A Happy Notes
Transformasi Orsel Cilamaya
Misuh-Misuh Keunikan Tubuh
Kenalan Penulis: Budi (Masih) Hikmah
Memantau Pola Cinta
Dukung Penulis Favoritmu
-
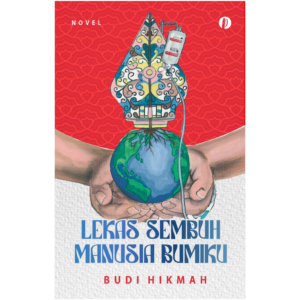 Lekas Sembuh Manusia Bumiku
Rp69.000
Lekas Sembuh Manusia Bumiku
Rp69.000
-
 Unboxing
Rp65.000
Unboxing
Rp65.000
-
 Mendengar Radio Sendirian
Rp69.000
Mendengar Radio Sendirian
Rp69.000
-
 Klothek'an
Rp75.000
Klothek'an
Rp75.000
-
 Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya
Rp75.000
Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya
Rp75.000
-
 Yang Absen dari Pendidikan Kita
Rp75.000
Yang Absen dari Pendidikan Kita
Rp75.000
-
 Menjadi Perempuan Setiap Hari
Rp75.000
Menjadi Perempuan Setiap Hari
Rp75.000
© 2018 Nyimpang Coop - Part of CV Pustakaki Press .














