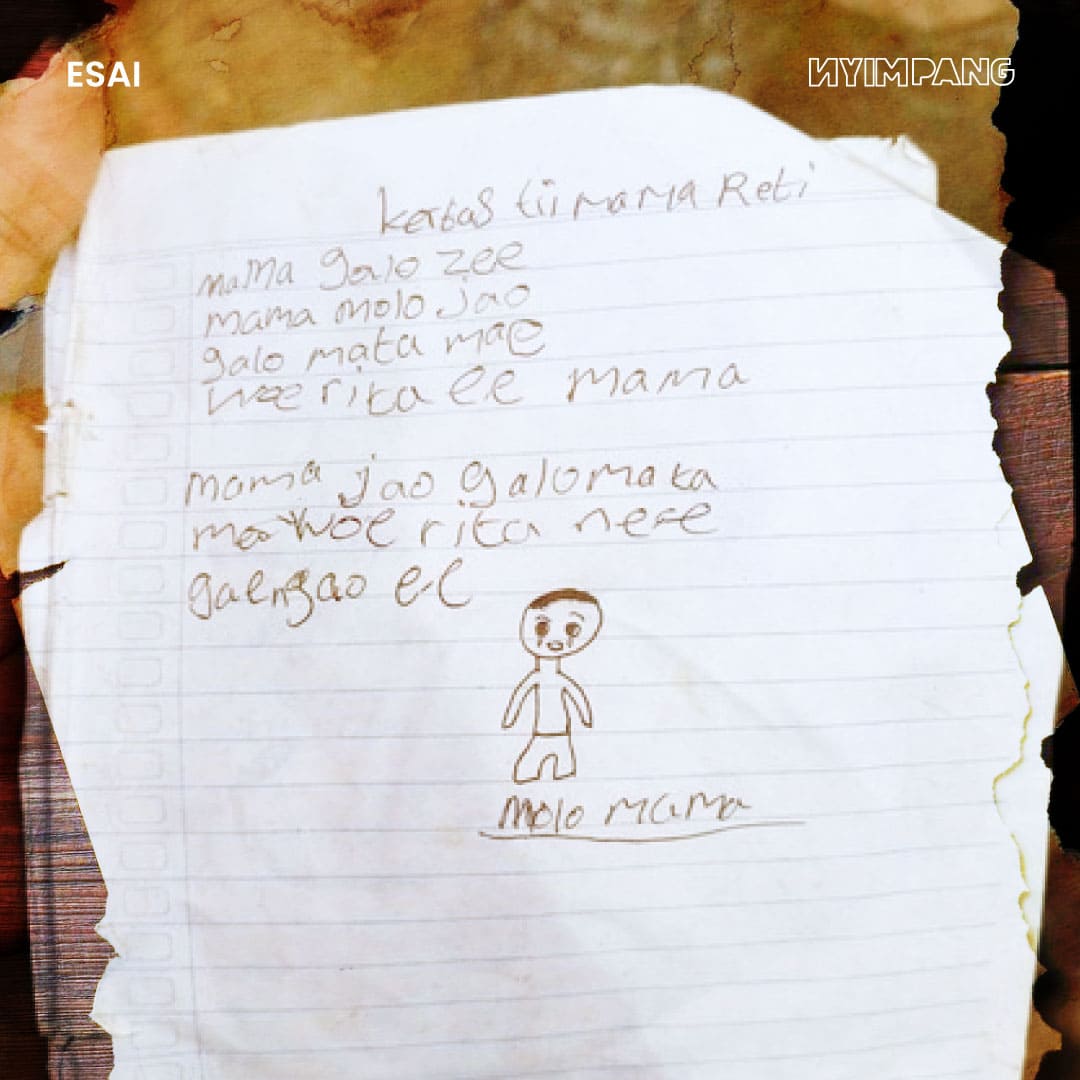
Cinta Sepihak: Tinggalkan atau Lanjutkan Biar Menyala

Di dunia ini, mungkin hanya orang yang kamu cintai dan—entah karena permainan takdir atau kesalahan semesta—kebetulan mencintaimu balik, yang mampu memberi sedikit jeda dari beban hidup yang terus menghimpit. Tapi, bahkan itu pun bukan jaminan. Cinta, seperti langit bulan Januari di atas kota Karawang, seringkali hanya mendung tanpa hujan—memberi harapan, tanpa kepastian. Ia mungkin saja datang membawa kebahagiaan, tetapi lebih sering hadir seperti layangan putus yang tersangkut di dahan pohon angsana tua di pinggir jalan, robek, kusut, dan tak lagi bisa diterbangkan. Angzay.
Para psikolog dan ilmuwan, dalam segala kegigihannya yang patut dihormati, mencoba memahami apa itu cinta. Mereka menganalisis, menghitung, bahkan merenung seperti filsuf yang kehabisan rokok. Namun cinta, seperti angin dari arah yang salah, menolak untuk dirumuskan. Carl Gustav Jung, misalnya, mengatakan bahwa cinta lebih cocok dipahami melalui seni, musik, atau puisi. Dalam pandangannya, sebuah melodi sederhana bisa terasa lebih jujur daripada seribu lembar skripsi. Musik, katanya lagi, adalah bahasa universal yang berbicara langsung kepada hati tanpa perlu diterjemahkan, kata Jung melalui The Archetypes and the Collective Unconscious. Dari sini, bahkan Jung tampaknya memilih bersembunyi di balik metafor, seperti seseorang yang tak berani mengakui bahwa ia pun tidak paham.
Dalam universe yang lain, Erich Fromm mencoba lebih filosofis. Dalam The Art of Loving, ia menggambarkan cinta sebagai seni, sesuatu yang harus dipelajari, dipahami, dan dikuasai. Tapi ironisnya, seni cinta ini sering kali terasa seperti lukisan Jack Haris Bonandar—ekspresionis, kacau, penuh garis-garis yang saling berbenturan.
Coba aja kamu berdiri di depan kanvas besar itu, melihat setiap goresan dengan harapan menemukan makna, tetapi yang ada justru kebingungan. Apakah cinta benar-benar memiliki arah, atau hanya serangkaian coretan yang tak sengaja tumpah?
Namun, cinta tidak selalu tentang keindahan. Baron (1986), dengan nada sarkastis, menyebut cinta sebagai kombinasi emosi, pikiran, dan perilaku yang tak pernah benar-benar sinkron. Lebih jauh, ia dengan berani mengatakan bahwa cinta adalah penipu ulung. Ia membungkus diri dalam ilusi kebahagiaan, hanya untuk kemudian menariknya kembali dengan tangan dingin. Kita semua, pada akhirnya, hanya aktor dalam drama cinta yang sudah ditulis oleh sutradara yang bahkan tidak kita kenal, dan lebih sering daripada tidak, kita bahkan gak pernah dikasih skripnya.
Sementara itu, Sternberg, dalam teorinya yang disebut Triangular Theory of Love (1986), mencoba merasionalisasi cinta dengan merumuskannya ke dalam tiga komponen: keintiman, gairah, dan komitmen. Ketiganya, jika digabungkan secara sempurna, menciptakan apa yang disebut consummate love. Sebuah cinta utopis yang hanya ada dalam dongeng Disney atau drama Korea. Sisanya? Sisanya adalah fragmen-fragmen yang tak sempurna. Ada fatous love—cinta yang penuh gairah dan komitmen, tapi tanpa keintiman, seperti sebuah janji yang berteriak nyaring tapi tidak pernah menyentuh. Ada companionate love, cinta yang nyaman tapi hambar, seperti teh tawar yang kamu minum hanya karena tak ada pilihan lain. Atau romantic love, cinta yang meluap-luap tetapi sebatas ilusi remaja yang akan pudar begitu angin logika bertiup.
Lalu, ada empty love—cinta yang bertahan hanya karena kewajiban, tanpa gairah atau keintiman. Ia seperti lampu neon yang berkedip di tengah malam: terang, tapi dingin, tanpa nyawa. Dan jangan lupa infatuated love, cinta penuh gairah tanpa keintiman atau komitmen, seperti hubungan semalam di kamar kosan yang murah, meninggalkan kehangatan palsu yang cepat menguap.
Namun, di atas semua itu, cinta sepihak adalah tragedi paling kejam. Bayangkan kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi cinta itu tidak pernah sampai. Ia seperti surat yang dikirim ke alamat yang salah, hilang di antara tumpukan sampah di kantor pos. Penelitian Baumeister dan Leary (The Need to Belong, 1995) bahkan menunjukkan bahwa 98% orang pernah merasakan sakitnya penolakan cinta. Dan dari semua bentuk rasa sakit, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan orang yang kamu cintai memilih orang lain. Rasanya seperti tertusuk, tetapi kamu gak bisa narik pisaunya.
Apa yang harus dilakukan ketika cinta ditolak? Berhenti, ceuk anu heeh mah ceunah. Tapi berhenti mencintai seseorang sama sulitnya dengan melupakan lagu yang pernah nemenin kamu menangys malam-malam. Kamu tahu kamu harus berhenti, tetapi hati kamu terus melangkah, seperti pengembara yang tersesat di jalan setapak tanpa ujung. Dan setiap langkah itu hanya memperbesar harapan, yang sebenarnya adalah kebohongan terbesar cinta. Harapan itu, seperti lubang kecil yang terus digali, perlahan menjadi kuburan buat jiwamu.
Seperti kata Rumi,
“… dan dari hari kehari, kegilaanku kian bertumbuh. Kegilaan yang tak kuinginkan kesembuhannya. Dan dari hari kehari aku dirundung ketidaktahuan tentang bagaimana kerinduan harus dialamatkan. Kerinduan yang terus menjalar seperti akar-akar pohon tua yang berkeras menembus dinding-dinding mesjid. Kerinduan yang tak berujung seperti jari-jemari yang mengitari tasbih. Oh, cinta dan kerinduan. Tercerabut sudah jantung hatiku.” (1207-1273)
Pada akhirnya, cinta adalah kekuasaan yang kamu kasih ke orang lain buat ngancurin dirimu sendiri. Njay. Cinta, seperti langit mendung di atas Karawang, tidak pernah benar-benar menjanjikan hujan. Kamu cinta, tapi terluka. Kamu mau lupa, tetapi cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantuimu. Srrr ah!
Kepustakaan
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.
Baron, R. A. (1986). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. Boston: Allyn & Bacon.
Fromm, E. (1956). The Art of Loving. New York: Harper & Row.
Jung, C. G. (1968). The Archetypes and the Collective Unconscious (R. F. C. Hull, Trans.). Princeton: Princeton University Press.
Sternberg, R. J. (1986). A Triangular Theory of Love. Psychological Review, 93(2), 119–135.





