Saat kecil dulu, saya cenderung menghindari film-film yang, menurut beberapa sumber, dapat menggoyahkan iman. Sebut
Siksa Kubur (2024) dan Proses Spiritual Manusia

Saat kecil dulu, saya cenderung menghindari film-film yang, menurut beberapa sumber, dapat menggoyahkan iman. Sebut saja The Da Vinci Code (2006), PK (2014), dan Noah (2014). Jika diingat lagi, saya cemen sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, saya perlahan menyadari bahwa tanpa menonton film-film tersebut pun, keimanan manusia kadang naik-turun. Melalui observasi kita dari orok hingga tumbuh bulu halus di bokong, wajar bila pertanyaan-pertanyaan yang menantang logika kita dalam beragama muncul. Saya meyakini hal tersebut sebagai proses spiritual yang setiap orang lalui.
Sama seperti karakter utama film ini, yaitu Sita (Faradina Mufti). Ia terobsesi mencari tahu bahwa siksa kubur itu benar adanya. Motifnya jelas: orang tuanya meninggal karena bom bunuh diri oleh orang yang takut akan siksa kubur. Sejak saat itu, Sita, dibantu oleh Adil (Reza Rahadian), mencari orang paling berdosa untuk ikut masuk ke dalam liang lahatnya dan merekam proses siksa kubur.
Melabeli dirinya sebagai horor religi, Siksa Kubur tak memenuhi durasinya untuk menceramahi penontonnya. Siksa Kubur justru memantik pembahasan mendalam dengan melemparkan pernyataan dan berbagai pertanyaan yang cukup mengganggu benak penontonnya.
“Orang yang membunuh orang tua kita bukanlah orang yang percaya setan, tapi orang yang percaya agama.”
“Apa itu siksa kubur? Apakah yang disiksa jiwanya atau fisiknya?”
“Bagaimana kalau orang yang disiksa itu seorang masokis, dan dia menikmati rasa sakit?”
“Jika seseorang akan mendapat siksa di neraka, kenapa harus disiksa juga di alam kubur?”
Pertanyaan-pertanyaan provokatif semacam ini mengingatkan saya pada film asal Negeri Jiran berjudul Munafik (2016). Saya ingat betul ketika karakter di film itu kesurupan dan melontarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya tak saya pahami, namun sukses membuat saya bergidik ngeri.
Kumpulan pertanyaan provokatif itu juga membawa saya ke masa kecil, di mana cara pandang saya masih polos. Saat itu muncul beragam pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh orang tua kita. Kalaupun bisa, orang tua kita akan menjawab dengan normatif dan sangat berhati-hati. Pertanyaan seperti “kenapa teroris justru mengatasnamakan agama?” atau “kenapa di pesantren banyak kasus kekerasan seksual?” Pasti pernah terbersit sesekali di benak kita. Hingga seiring berjalannya waktu, kita menemukan sendiri jawaban-jawabannya.
Dalam perjalanannya, Sita justru “menjauh” dari agama. Jika pelaku bom bunuh diri tersebut adalah orang yang percaya agama, maka Sita mencoba menjadi antitesisnya. Nantinya, Sita akan diberi pelajaran atas skeptisismenya terhadap agama. Adegan Sita memohon-mohon untuk bertobat kala menyaksikan siksa kubur merupakan adegan yang sangat menyiksa batin dan bikin bulu kuduk merinding.
Sayangnya, film ini tak punya karakter atau adegan yang ditujukan menjadi kompas moral. Ketika alasan teroris melakukan bom bunuh diri adalah takut akan siksa kubur, dan siksa kubur itu benar adanya, harusnya ada karakter atau adegan yang mencoba melogiskan bahwa, meskipun siksa kubur nyata, melakukan terorisme dengan dalih takut akan siksa kubur tetap salah. Nah, Siksa Kubur tak punya momen itu. Mungkin Joko Anwar memang maunya seperti itu, sebagai bentuk satir.
Siksa Kubur berani mendobrak pakem film-film bertema “religi”. Ia tidak menyederhanakan orang baik dan orang jahat, pahala dan dosa, surga dan neraka. Ia tak seperti penceramah yang berdiri di atas mimbar. Ia justru berdiri lebih dekat lagi, atau mungkin ia menjadi diri kita sendiri: manusia biasa, yang penuh pergulatan batin, pertentangan logika, serta keimanan yang naik-turun ketika menjalani proses spiritual.
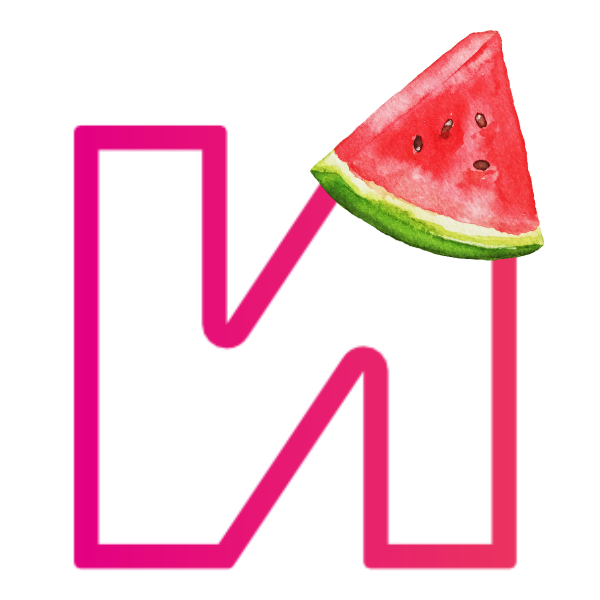



Leave a Comment