Saat kamu salah memilih jalan di sebuah persimpangan, kamu bisa saja punya opsi putar balik
Quarter-Life Crisis dan Filosofi Rute Google Maps

Saat kamu salah memilih jalan di sebuah persimpangan, kamu bisa saja punya opsi putar balik untuk kemudian memilih jalan yang tepat untuk sampai ke tujuanmu. Tapi brengseknya, fase kehidupan tidak bekerja dengan cara seperti itu.
Beberapa hari yang lalu, saya dan keluarga baru saja mengadakan perjalanan panjang lintas provinsi. Selain dipenuhi debaran menyenangkan sekaligus mengharukan karena melewati Kota Istimewa yang pernah saya diami selama beberapa tahun lamanya, perjalanan kemarin punya makna mendalam lain untuk saya.
Tapi sebelum menjelaskan makna yang saya maksud, izinkan saya menyatakan satu hal: saya adalah orang yang pernah percaya kalau Quarter Life Crisis itu adalah salah satu kebohongan paling murah yang diciptakan dan dipercaya oleh orang-orang payah.
Ya, saya pernah tidak percaya ada satu periode dalam kehidupan manusia yang dipenuhi ketidakpastian dan pencarian jati diri. Bagi saya, sebutan ini hanyalah sebuah alibi dari mereka yang berusia pertengahan 20 hingga awal 30-an tahun untuk mengelak saat disalahkan oleh orang lain ketika mengambil sebuah keputusan hidup yang tidak tepat menurut kesepakatan banyak pihak.
Bagi saya, menyebut diri tengah berada di fase Quarter Life Crisis adalah bentuk pelarian paling tidak hormat dari mereka yang enggan mencari solusi saat permasalahan hidup datang menghampiri. Anggapan ini bahkan masih saya pelihara ketika salah seorang teman datang untuk mengutarakan keluh kesah dan kebimbangan hati yang tengah dia hadapi.
Teman ini, yang tak perlu saya sebutkan namanya, membuka ceritanya dengan menanyakan apakah saya sudah bisa menerima sepenuhnya takdir saya yang sekarang sebelum mengutarakan keinginannya untuk pindah agama. Sejujurnya saya tidak mengerti kenapa teman saya ini memunculkan pindah agama sebagai salah satu opsi yang bisa dipilih untuk menjadi solusi atas berbagai dilema yang tengah dihadapi.
Dan sejujurnya juga saya tidak tahu persis dilema macam apa yang sedang dia hadapi. Tapi saya percaya, dia tengah menghadapi kebingungan tak berujung meskipun masih menolak menyebut teman saya yang satu ini tengah menjajagi fase Quarter Life Crisis.
Teman ini terus bercerita bagaimana hidupnya tengah berada di persimpangan; menuruti bujukan hati kecilnya untuk pindah agama atau mengubur dalam-dalam keinginan itu demi menjaga nama baik keluarganya yang dikenal sebagai salah satu pemuka agama penting di daerahnya. Ritual curhat itu pun diwarnai dengan pertanyaan,
“Kamu pernah ada di fase yang sama kaya aku gak sih, Din? Jujur!” yang menuntut saya mau tak mau memutar kepingan-kepingan fase kehidupan yang terekam dalam memori otak.
Setelah mencoba mengingat beberapa saat, saya akhirnya menemukan fakta bahwa saya juga pernah berada di fase hidup yang cukup dilematis, sama seperti dia meskipun tidak serumit dilemanya. Dilema saya hanya soal melanjutkan kuliah atau tidak dengan pertimbangan takut tidak sanggup menyelesaikan sampai akhir dan kekhawatiran takut dicap sebagai orang gagal karena menjadi satu-satunya orang yang tidak punya gelar sarjana di lingkungan pergaulan. Teman saya ini lalu menutup ritual curhatnya dengan,
“Ternyata Quarter Life Crisis semenyiksa itu dan kita sama-sama sedang menghadapinya ya, Din?”
Eh, benarkah begitu?
Saya belum sepenuhnya mengamini bahwa kami sedang sama-sama menghadapi Quarter Life Crisis. Tapi yang jelas saya menyadari kami berdua memang punya banyak kesamaan, mulai dari yang sepele seperti sama-sama menyukai lagu Kelangan yang dicover NDX a.k.a familia hingga yang lumayan serius seperti sama-sama pernah punya keinginan untuk mengakhiri hidup.
Harus saya akui, keinginan untuk mengakhiri hidup pernah muncul berkali-kali dalam diri saya bahkan sampai saya ikut dalam perjalanan lintas provinsi bersama keluarga. Keinginan ini bahkan seringkali datang tanpa permisi saat saya menjalani aktivitas sehari-hari seperti menjadi pembaca rute Google Maps saat perjalanan lintas provinsi beberapa waktu yang lalu.
Keinginan ini juga yang akhirnya memaksa saya beberapa kali menyuruh kakak laki-laki saya untuk lanjut menginjak pedal gas saat kami memilih ruas jalan yang salah di sebuah persimpangan. Tapi kemudian keinginan ini juga yang justru pada akhirnya membuat saya mengamini bahwa Quarter Life Crisis itu mungkin saja benar adanya dan terjebak di dalamnya bukanlah suatu dosa.
Ya, mungkin benar Quarter Life Crisis itu ada. Tapi sama seperti melakoni perjalanan yang berpatokan pada rute Google Maps, berhenti sejenak untuk menekan tombol Pusatkan Lagi bisa jadi opsi terbijak yang bisa dipilih dibanding menyerahkan diri dengan cara melompat ke jurang untuk menyelesaikan perjalanan yang tak diharapkan dan tak kunjung sampai ke tujuan.
Bahkan, salah memilih jalan di persimpangan nyatanya juga tidak seburuk itu. Meskipun di beberapa ruas jalan kamu tak punya opsi putar balik, melanjutkan di jalan yang tidak seharusnya bukan selalu berarti akan membuatmu gagal mencapai tempat yang kamu tuju. Kamu hanya akan mencapai tempat itu beberapa waktu lebih lambat dari rute yang seharusnya. Dan menggapai sesuatu lebih lambat dari yang lain tentunya bukanlah suatu dosa.
Cilacap, Menjelang Seperempat Abad.
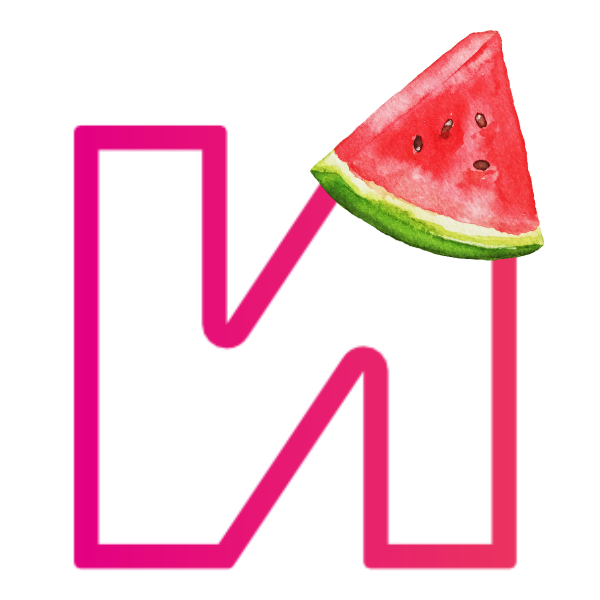



Leave a Comment