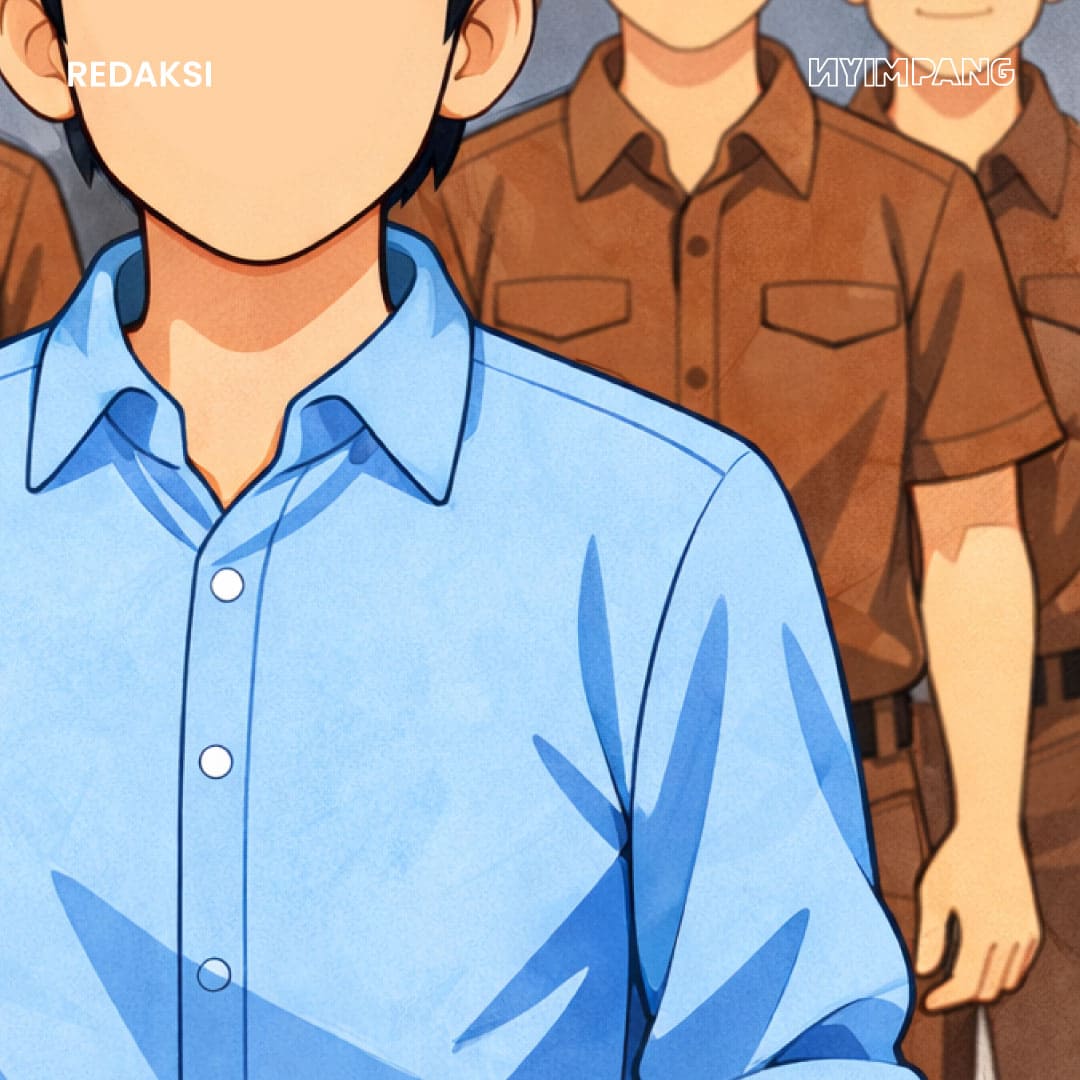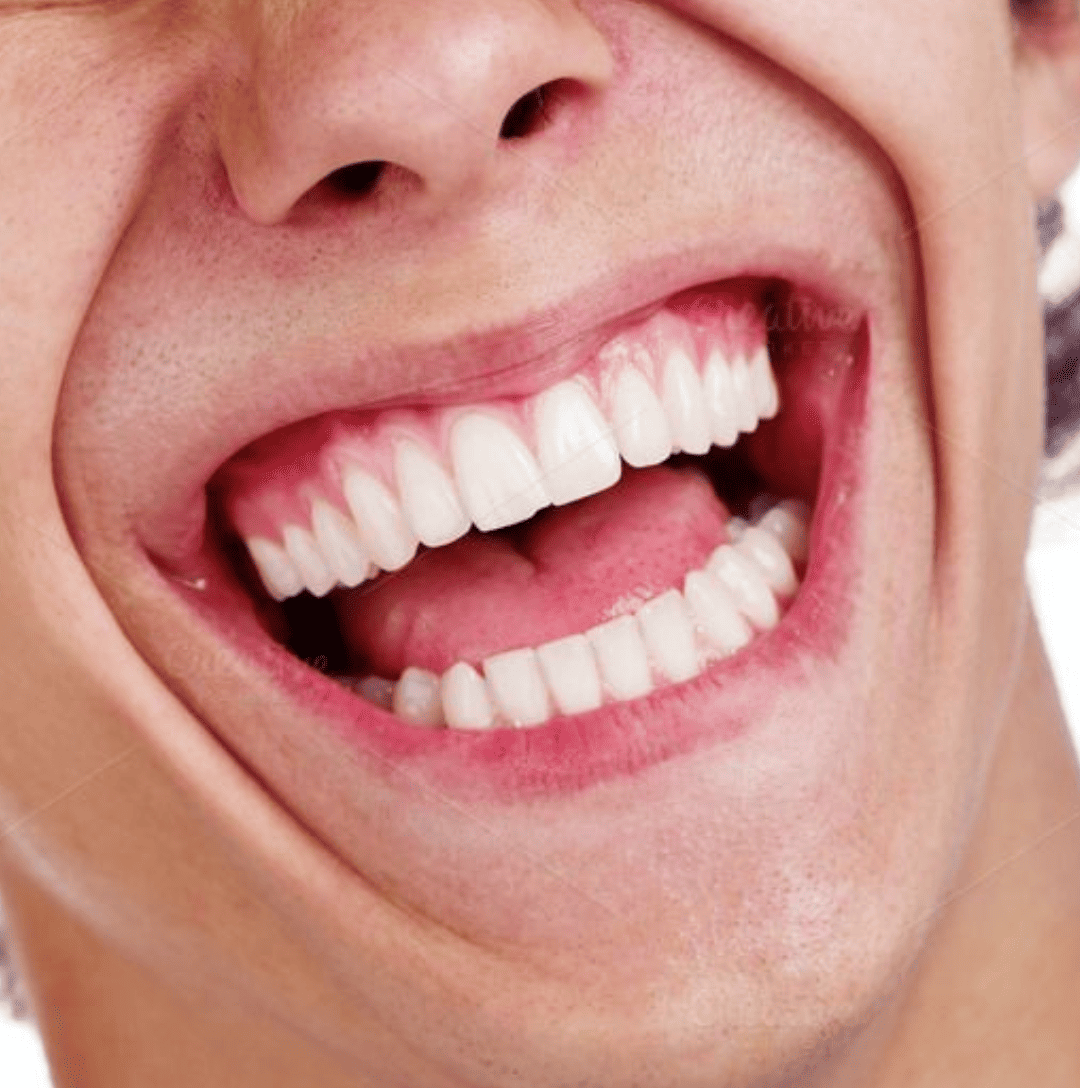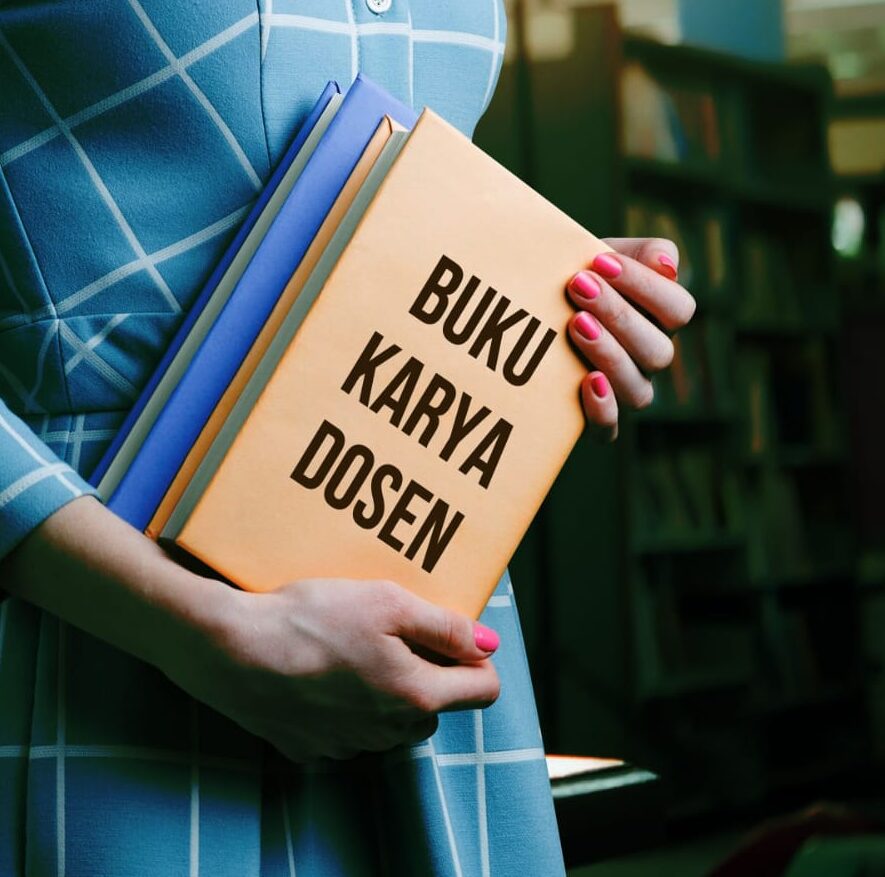
Dari #PeringatanDarurat sampai #IndonesiaGelap: Apa yang Perlu Kita Lakukan?

Di awal pemerintahan second account—istilah untuk rezim yang dianggap sebagai periode ketiga kekuasaan lama—ruang publik diguncang oleh dua gelombang aksi massa bertema “darurat” dan “gelap.” Kedua diksi ini menggambarkan kondisi bangsa yang pernah disebut oleh seorang elit bak “macan Asia” yang bisa “bubar” pada tahun 2030.
Gelombang pertama muncul akibat putusan MK yang berdampak pada elektoral, sementara yang kedua dipicu oleh penghematan anggaran program “isi perut” yang justru mengorbankan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, dalam acara resmi, dua sektor yang menunjang hajat hidup orang banyak ini justru disebut sebagai “pendukung,” bukan prioritas.
Idealnya, demokrasi yang sehat membutuhkan rakyat yang kritis, bukan hanya patuh buta. Chantal Mouffe dalam The Return of the Political (1993) menegaskan bahwa suara-suara antagonis itu penting dan sangat baik agar demokrasi tidak mandek. Hal ini sejalan dengan pandangan Howard Zinn yang menyatakan bahwa masalah utama bukan ketidakpatuhan terhadap penguasa, melainkan justru kepatuhan itu sendiri. Sudah banyak rakyat yang sengsara akibat kepatuhan buta terhadap penguasa. Jadi, dalam konteks demokrasi, bukan hanya right to vote (hak memilih) yang penting, tetapi juga right to speak (hak bersuara). Aksi massa adalah bentuk paling nyata dari hak bersuara tersebut.
Darurat dan Gelap, terus Apa?
Saat ini, gelombang “darurat” dan “gelap” sedang mengalami pendinginan mungkin akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Apalagi, penguasa saat ini semakin memperlihatkan egoismenya melalui rancangan undang-undang angkatan bersenjata yang disinyalir banyak pihak akan menggiring kita kembali pada dwifungsi ABRI, yakni masuknya tentara ke ranah sipil yang dapat mengancam demokrasi.
Coba aja sedikit lebih rajin membaca sejarah, kita bakal tahu kalau dwifungsi ABRI lebih banyak membawa dampak negatif ketimbang positif. Tapi buzzer sering kali mencoba membangun opini bahwa dominasi militer di ranah sipil adalah hal biasa, dengan bawa-bawa Vietnam dan China. Mereka lupa bahwa ideologi dan sikap politik kedua negara itu bertolak belakang dengan Indonesia. Di satu sisi, mereka membangun opini seakan-akan dominasi militer akan membuat Indonesia lebih disiplin dan aman. Padahal, klaim tersebut omong kosong. Banyak negara dengan dominasi militer dalam kekuasaan sipil justru masuk dalam kategori negara gagal, sebut saja Myanmar, Korea Utara, atau Nigeria.
Kembali pada persoalan dua aksi massa tadi, pertanyaannya: apakah gerakan ini hanya akan menjadi cerita romantis perjuangan rakyat, atau justru menjadi penyuluh bagi gerakan rakyat selanjutnya? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita bertindak setelahnya.
Jangan Dulu Ngomongin Revolusi
Berbicara revolusi saat ini terasa terlalu jauh. Revolusi membutuhkan setidaknya empat elemen utama: pemimpin, ajaran, massa aksi, dan suasana. Sementara saat ini, kita hanya memiliki suasana dan massa aksi yang masih mengambang.
Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan?
Anggaplah Politik itu Penting
Buang jauh-jauh anggapan bahwa politik tidak memengaruhi hidup kita. Njoto pernah ngomong, “Politik adalah panglima,” yang berarti politik mengatur segalanya dan tentu berdampak pada kehidupan kita.
Jika kita cermati, kondisi yang diciptakan oleh para aktor politik saat ini justru semakin menjauh dari esensi kebenaran. Mereka lebih sibuk memperkuat citra, sehingga menciptakan iklim politik yang jauh dari ide, makna, kehendak, apalagi ideologi—yang sejak dulu memang hanya menjadi pemanis belaka.
Kekuatan politis kemudian fetisisme komoditas dan kesadaran palsu seperti kata Karl Marx: kesadaran umum diarahkan untuk lebih mementingkan pencitraan, euforia sesaat, dan massa yang mengambang. Hal ini membuat mereka teralihkan dari kebutuhan manusiawi (needs) ke hasrat (desire).
Politik yang penuh pencitraan ini mendorong demokrasi ke dalam keadaan yang Yasraf Amir Piliang sebut sebagai desubstansialisasi demokrasi. Masalah-masalah nyata justru diselesaikan dengan pencitraan semata. Contoh sederhana dari gejala ini terlihat dalam kasus Sritex. Para elit menjanjikan penyelesaian, tetapi dalam waktu yang sama, mereka malah meminta rakyat berteriak “hidup” untuk seorang penguasa—bukan untuk kehidupan mereka sendiri.
Tidak heran jika kita merasa kehadiran pemerintah justru tidak memberikan pengaruh penting terhadap kemaslahatan bersama.
Maka, menganggap politik itu penting adalah upaya yang bisa kita lakukan pasca-gelombang aksi “darurat” dan “gelap.” Politik yang dimaksud tuh harus melampaui sekadar urusan elektoral tapi. Pemilu hanya momentum lima tahunan yang penuh kekotoran dan kebisingan, yang justru memecah kita ke dalam pola pikir kamu vs aku.
Anggaplah politik itu penting dalam konteks makna dan urgensinya yang sebaik-baiknya—bukan pada ketokohan, apalagi kefanatikan terhadap kelompok—tetapi pada kondisi yang kita idealkan.
Terus Merawat Kepekaan, Kemuakan, dan Kewaspadaan terhadap Otoritarianisme
Reformasi 1998 meruntuhkan Orde Baru, tetapi warisannya masih hidup. Politisi berjubel, tetapi negarawan langka. Kita malah terjebak memilih pemimpin karena faktor fisik tertentu seperti “imut” dan “gemoy,” padahal mereka justru berpotensi memunculkan otoritarianisme.
Saat ini, para “mutan” di media sosial tengah membangun opini bahwa “Indonesia mustahil otoriter!”
Padahal, kenyataannya mengkhawatirkan. Kita semakin terbiasa menormalisasi kekerasan untuk mencapai tujuan politik, menggunakan retorika ancaman (contoh: isu makar, separatis), membangun budaya takut dan anti-perbedaan, mengkriminalisasi lawan politik, serta menolak dialog.
Hidupkan Terus Agitasi dan Propaganda
Dalam setiap gerakan ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud), agitasi dan propaganda selalu menjadi alat untuk menjaga nyala perjuangan. Agitasi berfokus pada jangka pendek, sedangkan propaganda berfokus pada jangka panjang.
Menghidupkan agitasi dan propaganda melalui seni visual, tulisan, bahkan musik menjadi langkah yang perlu dilakukan. Agitasi dan propaganda yang efektif harus memahami perbedaan kepentingan, ketegangan sosial, keyakinan terhadap aksi, serta potensi gerakan massa itu sendiri. Para pelaku agitasi dan propaganda juga harus membaur, menyadari realitas, serta berkontribusi di tengah-tengah rakyat.
Suburkan Kolektif yang Melawan Kepandiran Intelektual
Menjadi intelektual bukan hanya soal IPK tinggi, karya ilmiah yang terindeks, atau lulusan universitas ternama. Ali Syariati mendefinisikan intelektual sebagai mereka yang memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat dan mengambil peran untuk melawan serta memperbaiki keadaan.
Menjadi intelektual dengan IPK tinggi, produktif berkarya, dan lulusan universitas ternama hanyalah bonus. Yang lebih penting adalah peran intelektual sebagai aktivis yang menyatukan akademisi dan gerakan sosial.
Untuk merawat dampak gerakan “darurat” dan “gelap,” kita harus memperkuat kolektif yang tidak hanya mengkaji dan melawan suatu isu, tetapi juga melawan kepandiran intelektual.
Kepandiran intelektual, menurut Syed Husin Ali, dicirikan dengan ketidakmampuan menganalisis masalah, ketidaksanggupan menyelesaikan masalah, bahkan ketidakmauan untuk belajar memahami masalah.
Kepandiran ini tidak hanya menjangkiti mereka yang kurang akses terhadap literasi, tetapi juga mereka yang sebenarnya memiliki keistimewaan untuk mengaksesnya. Sadar akan tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual adalah langkah awal untuk keluar dari lingkaran kebodohan yang bebal ini.