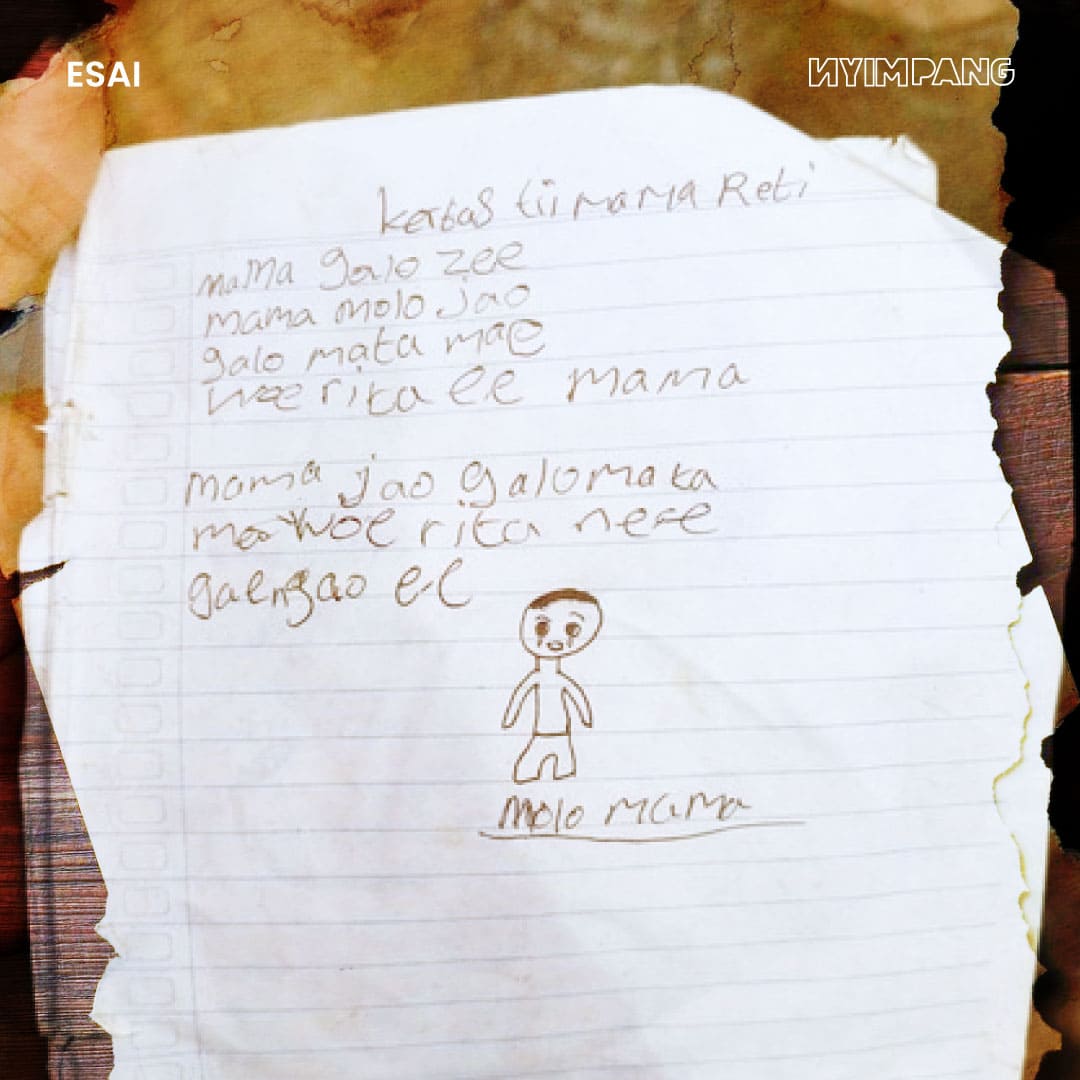Seribu Lilin di Tengah Gelap Kota Industri, Seribu Komentar di Lini Masa

Sabtu malam, 31 Agustus 2025, aku berdiri di Taman Sehati bersama puluhan orang berpakaian hitam. Di tangan kami ada lilin, di kepala kami ada payung hitam, di dada kami ada duka. Kami datang bukan untuk hura-hura, bukan untuk keributan, apalagi demi uang, kami datang karena kami ingin ambil bagian dari gejolak situasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Kami menyalakan lilin untuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang hidupnya direnggut begitu brutal. Kamis, 28 Agustus lalu, kendaraan rantis Brimob melindas tubuhnya. Bersama Affan, puluhan orang juga terluka, bahkan terus bertambah sampai hari ini.
Affan bukan aktivis besar, bukan pejabat, bukan siapa-siapa selain seorang ojol yang sedang mengantar makanan pesanan pelanggan. Kematian Affan menambah daftar panjang kematian warga sipil oleh aparat kepolisian.
Tapi rupanya, aksi damai tidak selalu dipahami sebagaimana adanya. Seorang ibu merekam kami menggunakan ponselnya di dekat Stadion Wibawa Mukti, lalu mengunggahnya ke TikTok. Videonya lumayan viral, tembus 124 ribu tayangan, dengan caption penuh was-was,
“Astagfirullah, udah sampai stadion aja nih demonya. Bener-bener serem. Semoga Cibitung dan arah Jababeka aman, soalnya jalur utama misua kerja lewat situ.”
Dari situ, komentar netizen bermunculan macam kacang goreng. Ada yang bilang kami maling, ada yang menyebut provokator, ada yang yakin kami dibayar Rp50 ribu per kepala, ada juga yang menuduh video itu hoaks lama dari tragedi Kanjuruhan. Ada rasa nyesek yang meninju ulu hati saat membaca komentar-komentar tersebut.
Padahal kenyataannya jauh dari tuduhan itu. Aku datang dengan uangku sendiri: bayar parkir Rp5.000, beli jambu kristal Rp5.000, beli roti Rp5.000, beli lilin dan korek Rp5.000, lalu beli payung hitam Rp30.000. Kalau ditotal, sudah keluar hampir Rp50 ribu itu belum bensin. Jadi kalau ada yang bilang kami “pendemo bayaran”, rasanya pengen ketawa miris. Kami sama sekali tidak dibayar, kami melakukan ini tulus semata. Teman-teman yang datang pun sama, bawa uang masing-masing sesuai kebutuhan, tidak menggunakan uang dari partai politik, bukan dari senior-senior pergerakan, bukan dari kanda-kanda, bukan dari perusahaan, atau bukan dari pejabat publik. Ini murni dari kami yang ingin berdoa bersama untuk Affan dan korban lainnya.
Masih jamak kita temui di tengah masyarakat kita orang-orang yang seenaknya saja menempelkan stigma: melawan dianggap negatif. Bawa payung hitam dicap anarko. Pakai baju hitam dikira mau rusuh. Membaca puisi di ruang publik dianggap pembangkangan.
Sementara “ketertiban” dijunjung tinggi, walaupun di balik ketertiban itu bersemayam ketidakadilan. Masyarakat kita perlu diperlihatkan kenyataan pahit di balik ketertiban sebenarnya. Bahwa di balik ketertiban itu ada gaji pejabat yang terus naik sementara hasil kerjanya gak jelas, ada korupsi yang terus merajalela di tengah hidup masyarakat yang makin sulit, ada anggaran TNI dan Polisi yang luar biasa besar saat anggran Pendidikan Dasar dan Menengah cuma seuprit.
Pengalaman negatif ini bukan baru sekali kualami. Aku teringat ketika masih ikut salah satu komunitas di Karawang, tempat asalku. Di sana pernah ada giveaway buku. Aku senang sekali saat berhasil masuk daftar penerima, bahkan sudah membayangkan akan kuambil pas kebetulan pulang kampung. Tapi tiba-tiba ada komentar menyakitkan, “Ngapain dia dikasih buku, dia kan jarang di Karawang,” padahal KTP-ku masih Karawang dan aku menang giveaway dengan cara yang jujur. Soal buku bisa kubeli sendiri karena memang aku mampu. Aku hanya merasa senang berpartisipasi dan menjadi bagian dari komunitas yang memang aku minati.
Komentar itu menyayat luka dalam pada sanubariku. Aku merasa keberadaanku dipinggirkan hanya karena aku merantau di kota industri. Padahal semakin beragam domisili dan latar belakang anggota komunitas semakin baik juga bagi komunitas tersebut. Jejaring, perkawanan dan kesempatanpun makin luas. Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir aku betah sekali bergabung dengan komunitas literasi Nyimpang. Selain aku bisa menulis rutin, anggotanya pun baik dan asyik sekali.
Pengalaman pahit atas komentar itu membawa ingatanku terbang pada sebuah tulisan di sebuah zine: “Berkolektiflah tapi jangan terikat. Jika kau merasa lelah pada satu kolektif, pergi. Tak perlu permisi.”
Kalimat itu terus bergema di kepalaku. Setelah menimbang untung-ruginya, aku memutuskan keluar dari grup WhatsApp komunitas itu. Bukan dilandasi perasaan benci, tapi karena aku ingin tetap merawat semangatku.
Malam di Taman Sehati itu, perasaan de javu menghampiri. Kami dituduh macam-macam, dicurigai, dianggap aneh karena menyalakan lilin dan membaca puisi.
Tapi seperti pengalaman di komunitas dulu, aku belajar bahwa perjuangan itu kadang bukan soal seberapa sering kita hadir di tempat, melainkan seberapa tulus kita menjaga api kecil di hati.
Rundown acara malam itu pun jelas: doa lintas agama, pembacaan pernyataan sikap, pembacaan puisi, lalu penyalaan lilin. Semua tenang, damai, dan khidmat. Bahkan suasananya lebih mirip acara tahlilan akbar ketimbang demonstrasi. Jadi kalau dibilang serem, mungkin memang karena begitulah aura yang menguar dari rasa duka. Tapi kalau dibilang mau rusuh, itu hanya fantasi netizen yang sudah kebanyakan nonton berita kriminal.
Aku sendiri merasa, perlawanan tidak harus dengan amarah. Justru lilin kecil yang kutaruh di tangan itu mengajarkanku sesuatu: cahaya sekecil apa pun bisa menembus gelap. Begitu juga harapan, sekecil apa pun bisa menembus tembok tebal kekuasaan.
Malam itu, aku mendapat pelajaran berharga: lebih baik dianggap aneh karena memperjuangkan kemanusiaan, daripada dianggap normal tapi membiarkan ketidakadilan berlangsung terus.
Affan memang sudah tiada. Tapi cahaya lilin yang kami nyalakan malam itu tetap menyala, di hati kami, di jalanan kota industri ini, dan semoga sampai ke telinga mereka yang berkuasa.
Aku lahir di Karawang, kini merantau di Cikarang. Dua-duanya kota industri, penuh pabrik, penuh peluh. Di Karawang aku belajar arti kolektif, di Cikarang aku belajar arti berdiri di jalanan. Dan di mana pun aku berada, satu hal yang tidak berubah: aku memilih berpihak pada kemanusiaan. Karena pada akhirnya, lilin yang menyala bukan soal kota mana yang jadi alamat KTP-ku, melainkan tentang nyawa siapa yang tidak boleh padam sia-sia.
Kami menolak diam. Kami menolak lupa. Dan kami menolak tunduk pada budaya impunitas.
Hidup kemanusiaan!