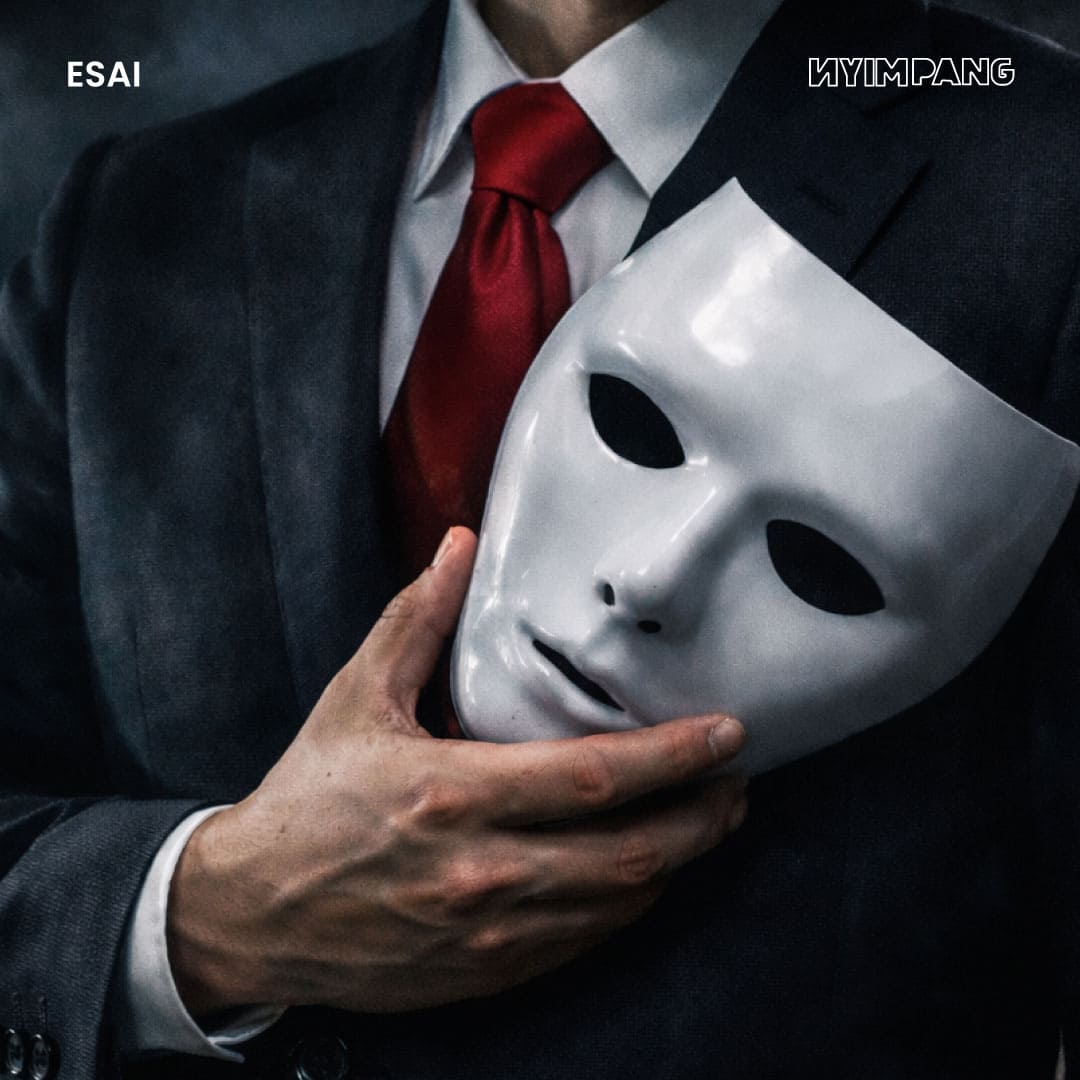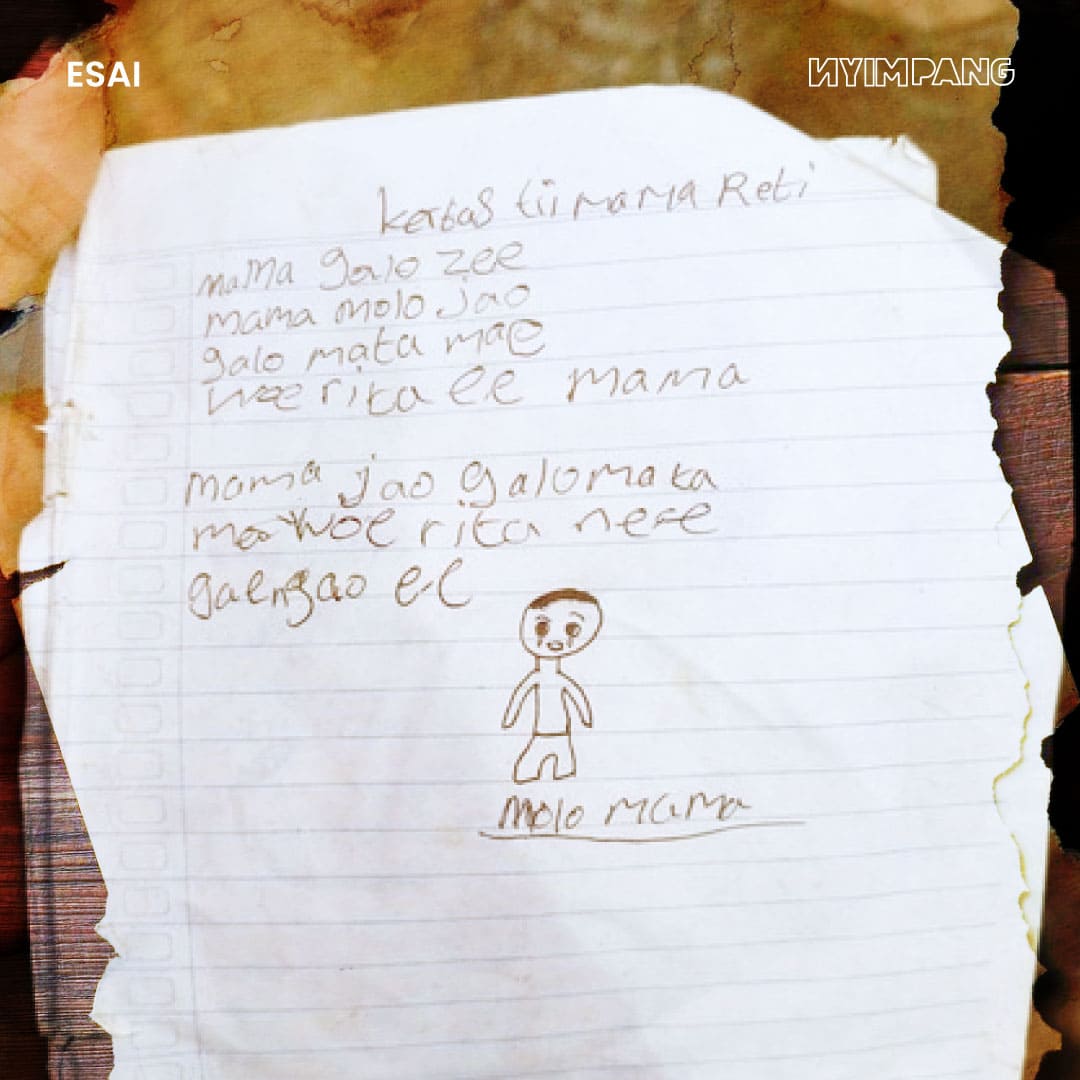Kenapa Premanisme di Indonesia Tidak Pernah Mati?
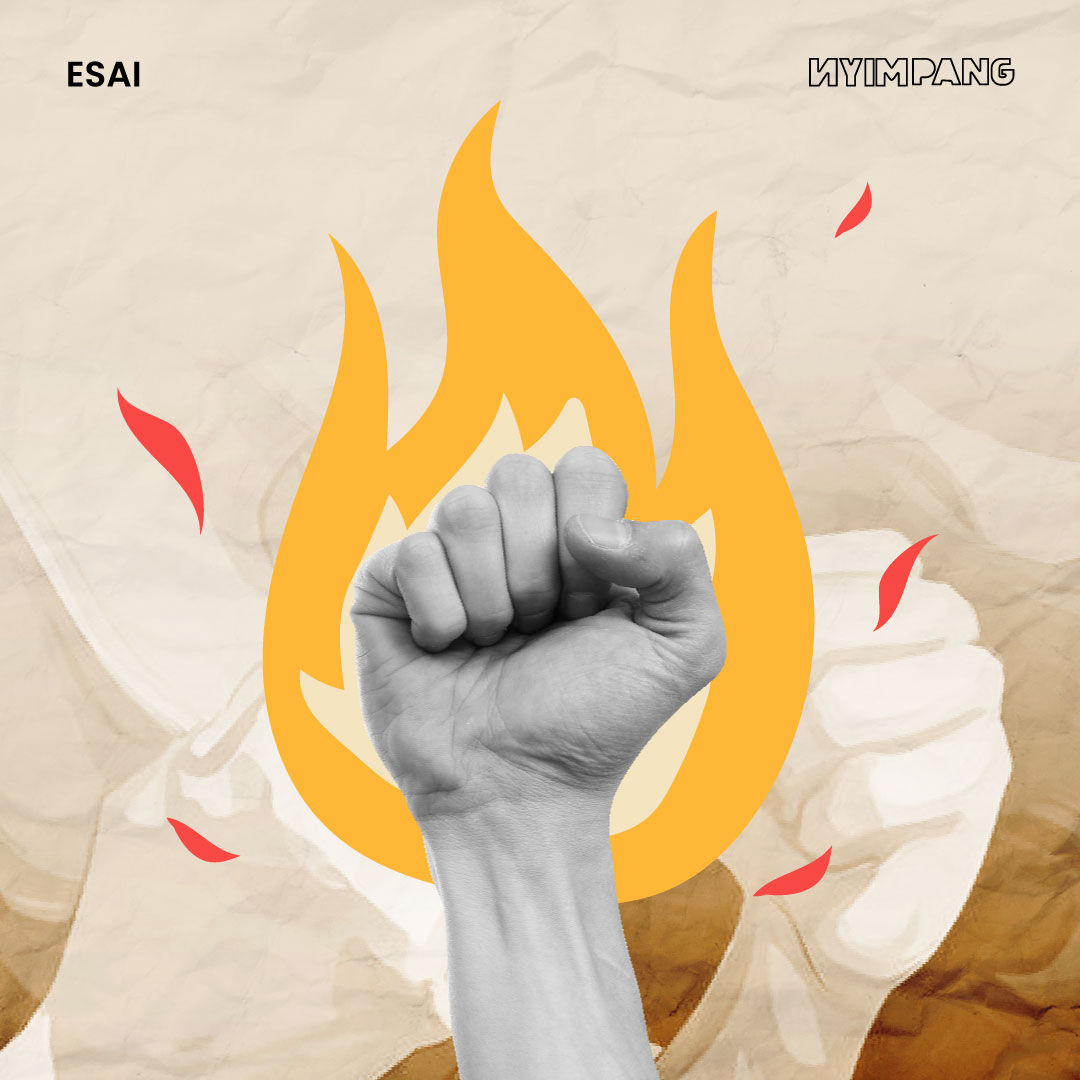
Proklamasi Kemerdekaan 1945 sebenarnya hanya membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
Namun, ironisnya, bayang-bayang kekerasan yang terlembagakan tak serta-merta sirna.
Apalagi yang melibatkan aktor non negara atau semi negara seperti pada fenomena premanisme dengan palakisme yang dipandang sebagai kegagalan aparat keamanan. Bahkan dalam banyak kasus, mereka ikut pula menikmati setoran.
Sungguh ironi, di usianya yang bakal ke-80 tahun sebentar lagi, Republik yang kita banggakan ternyata masih bergumul dengan warisan kelam dari tradisi kekerasan yang dijalankan oleh aktor-aktor non negara itu.
Praktik ini bukan hanya mengancam ketenteraman masyarakat, tetapi secara serius menggerogoti kedaulatan negara di berbagai lini.
Yang lebih memprihatinkan lagi, semakin banyak terjadi aliansi berbahaya antara penguasa dan preman yang justru semakin memperburuk lanskap keamanan, politik, dan ekonomi nasional.
Permasalahan Preman di Tengah Budaya Pertikaian dan Subkontrak Kekerasan
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menelusuri jauh ke belakang, sebelum era kolonial. Sejarawan seperti Henk Schulte Nordholt menggambarkan lanskap sosial Nusantara kala itu sebagai medan yang “hidup bersama saling bermusuhan”. Wilayah ini dihuni oleh beragam aktor, dari penyamun, pendekar, tentara bayaran, ahli suluk, panglima perang, pangeran, dan kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan sebagai alat.
Realitas politik ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai “Negara Pertikaian” (contest state).
Dalam “Negara Pertikaian”, kontrol efektif atas penduduk dan sumber daya alam bukanlah sesuatu yang mutlak karena diperoleh melalui negosiasi yang tiada henti, pembentukan dan pembubaran aliansi, serta ritual pameran kekerasan yang pragmatis dan sering kali brutal.
Dari kancah inilah muncul sosok kunci, yaitu mereka yang disebut para “jago”, yang terdiri dari orang lokal paling kuat (akamsi), yang menjadi ujung tombak kekuasaan.
Schulte Nordholt menegaskan bahwa kondisi ini kemudian memfasilitasi tumbuhnya bentuk-bentuk campuran antara kekerasan publik dan privat. Oleh karena itu, praktik kekerasan sering kali “disubkontrakkan” kepada pihak-pihak di luar struktur resmi, dengan jago sebagai pelaku utamanya.
Kolonialisme sebagai Lahan Subur Subkontrak Kekerasan
Meski bisa menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial, pola “subkontrak kekerasan” tidak dihapus oleh kolonialisme Belanda, melainkan dimanfaatkan dan dilembagakan.
Apalagi pemerintah kolonial menghadapi luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya dalam mempertahankan kekuasaan. Maka, dipakailah para jago lokal atau kelompok bersenjata setempat sebagai perpanjangan tangan untuk menjaga ketertiban, memungut pajak, atau menekan perlawanan.
Praktik ini memperdalam akar kekerasan non negara sebagai alat yang “diterima” untuk mencapai tujuan, baik oleh penguasa maupun komunitas tertentu, yang kemudian menjadi warisan dan terus bermetamorfosis hingga era modern.
Reformasi dan Kebangkitan “Politik Jatah Preman”
Transisi dari rezim otoriter Soeharto pada 1998, yang membuka ruang demokrasi, juga melepaskan kekuatan-kekuatan lama yang terkekang.
Ian Douglas Wilson, peneliti dari Murdoch University, Australia, mengkaji fenomena ini dengan cemerlang dalam bukunya The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia, atau yang kita kenal sebagai Politik Jatah Preman.
Wilson menggambarkan bagaimana aktor-aktor kekerasan non negara, yang sering kali merupakan keturunan para “jago” kolonial, menemukan ruang baru pasca-Orde Baru.
Mereka berevolusi, tak lagi sekadar preman kampung, namun menjadi “pengusaha kekerasan” (violent entrepreneurs) yang menawarkan “jasa” proteksi, penguasaan sumber daya (seperti tanah atau tambang), mobilisasi massa, hingga intimidasi politik.
Wilson menunjukkan bagaimana jaringan-jaringan ini menjalin hubungan simbiotik dengan aktor politik dan birokrat lokal yang membutuhkan “tenaga kasar” untuk memenangkan pemilu, mengamankan proyek, atau menekan lawan.
Meneropong Fenomena Para Jago dengan Teori Mafia
Dalam teori mafia dijelaskan bahwa perilaku para jago bukan sekadar tindakan kriminal, namun menawarkan “perlindungan” privat dari ancaman yang mereka ciptakan sendiri.
Menurut teori mafia pula, para jago ini membangun kekuasaan melalui:
1. Kekerasan yang terorganisir sebagai alat utama untuk menegakkan aturan, menghukum, dan mengintimidasi;
2. Kontrol teritorial/ekonomi seperti pasar, proyek, transportasi, dan lain-lain;
3. Penggunaan hubungan patron-klien yang membangun jaringan loyalitas dan ketergantungan luas, mencakup masyarakat biasa, pengusaha, hingga aparat negara;
4. Penyediaan “jasa perlindungan” ilegal;
5. Penjualan keamanan di luar kerangka hukum negara, sering kali kepada mereka yang tidak percaya atau ditinggalkan oleh negara; dan
6. Infiltrasi negara (state capture) yang berusaha menyusup ke atau mengendalikan bagian-bagian aparatus negara (polisi, pengadilan, birokrasi) untuk melindungi operasi mereka dan mendapatkan kekebalan hukum.
Struktur jaringan preman lokal dan “jago” modern di Indonesia menunjukkan karakteristik mafioso ini. Mereka menguasai terminal, pasar, atau kawasan proyek (kontrol teritorial/ekonomi). Mereka menawarkan “perlindungan” (atau memaksa menerimanya) kepada pedagang atau pengusaha. Mereka membangun hubungan patron-klien yang luas dan kompleks. Yang paling berbahaya, mereka sering menjalin aliansi gelap dengan aktor negara (polisi, tentara, politisi, birokrat), menciptakan simbiosis yang korup dan memperlemah kedaulatan negara.
Memutus Rantai Warisan Kelam
Warisan kekerasan non negara di Indonesia bukanlah takdir atau semata dianggap sebagai budaya yang telah mengakar.
Namun, karena warisan kekerasan itu sendiri telah sedemikian rupa dipoles oleh kolonialisme dan dimodernkan dalam demokrasi pasca-Soeharto.
Oleh karena itu, untuk mengatasinya harus dimulai dari keterikatan, ketegasan, kejujuran, dan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama terhadap aktor negara yang berkolusi. Selain itu, perlu terus disuarakan agar setiap institusi penegak hukum tetap profesional dan berintegritas dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keamanan di ruang publik.