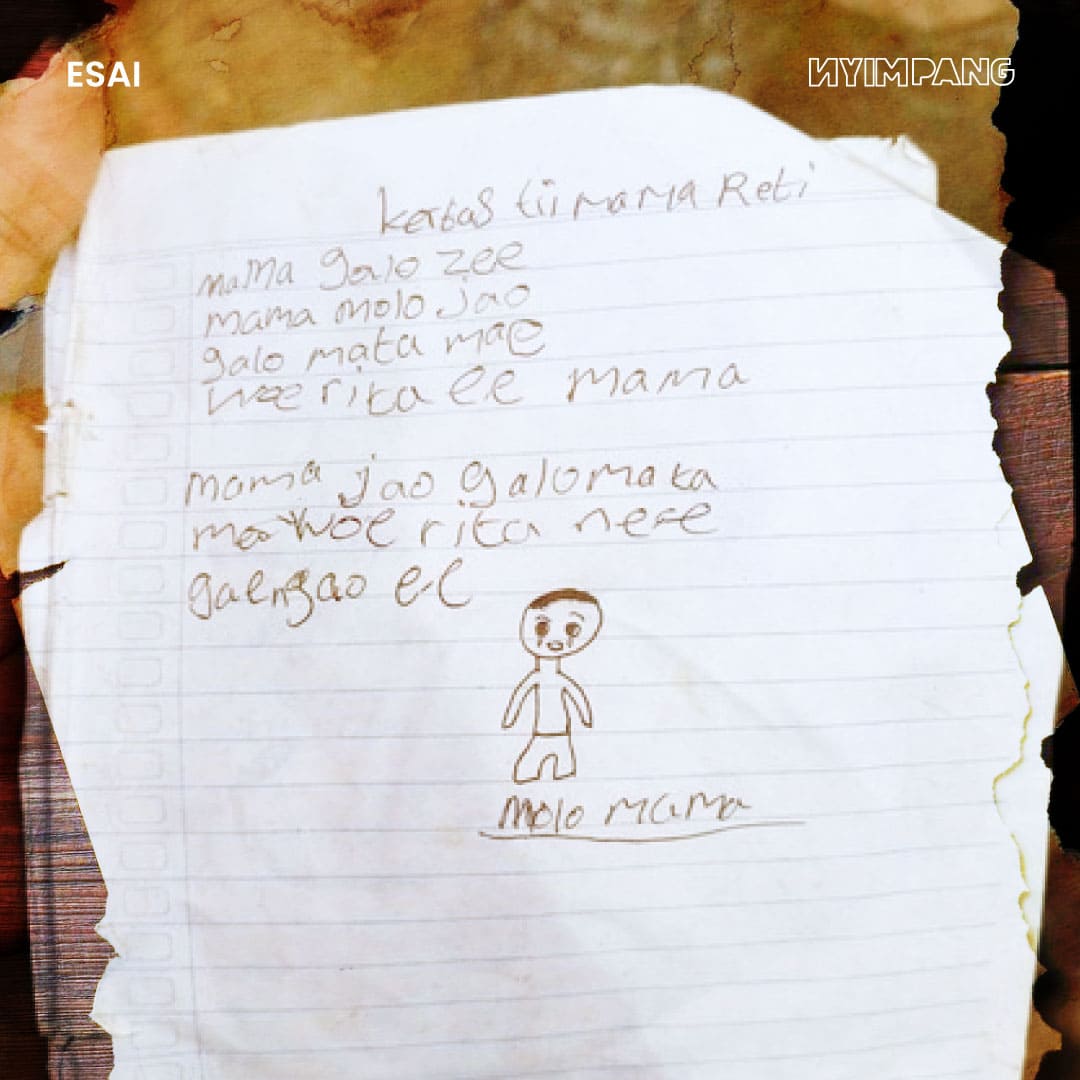Pergeseran Peran Organisasi Mahasiswa yang Kehilangan Daya Gugat

Tulisan ini lahir dari kegelisahan kecil yang pelan-pelan berubah jadi keresahan besar: bagaimana organisasi mahasiswa yang dulu menjadi benteng kesadaran kini justru tampak jinak dan patuh. Di banyak kampus, termasuk di tempatku belajar, Ormawa (Organisasi Mahasiswa) lebih sibuk mengurusi proposal, LPJ, dan acara seremonial ketimbang mengurusi mahasiswa itu sendiri. Aneh memang, tapi begitulah adanya. Ormawa makin rajin menyusun laporan kegiatan, namun makin jarang melahirkan gagasan kritis.
Dulu, mahasiswa dikenal sebagai kekuatan bangsa, motor perubahan, dan suara bagi yang terpinggirkan/termarjinalkan. Mahasiswa pada zaman dulu mencatat sejarah lewat keberanian: dari Boedi Oetomo sampai Reformasi 1998, semua memberi jejak langkah mahasiswa.
Tapi entah sejak kapan, gelar itu berubah jadi slogan kosong yang hanya diucapkan saat pelantikan. Kini, yang sering terdengar di ruang-ruang rapat kampus bukan lagi suara kegelisahan sosial, melainkan pembahasan teknis acara, siapa pembawa acara, dan bagaimana laporan pertanggungjawaban disusun supaya “aman”.
Aku tidak sedang merasa paling benar. Aku cuma sedang jujur pada apa yang aku lihat dan aku alami. Sebagai mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang, aku pernah terlibat dalam beberapa rapat Ormawa. Anehnya, yang lebih sering dijadikan topik tak jauh menyoal pengesahan program kerja atau tanda tangan pejabat pembina, bukan ketidakadilan yang menimpa mahasiswa.
Tidak ada ruang untuk bicara tentang fasilitas kampus yang timpang, kurikulum yang ketinggalan zaman, atau mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Semua seperti sibuk dengan “prosedur” tapi lupa pada “perjuangan”. Ormawa rasanya bukan lagi cermin keresahan mahasiswa, tapi justru perpanjangan tangan birokrasi kampus.
Kalau aku tarik ke belakang, akar masalahnya sudah panjang. Sejak masa Orde Baru dengan kebijakan NKK/BKK, mahasiswa dipaksa menjauh dari politik dan dibiasakan untuk patuh. Kampus dijadikan ruang steril dari gejolak sosial atau singkatnya, tempat aman yang tak boleh disusupi dan diguncang.
Lalu lahirlah generasi mahasiswa yang lebih paham cara bikin surat resmi daripada cara menggugat ketidakadilan. Hingga kini, pola itu masih diwariskan: Ormawa dijadikan lembaga administratif di kalangan mahasiswa saja,bukan tempat menyemai perlawanan intelektual.
Kita belajar lebih banyak tentang cara mengatur acara, tapi lupa cara mengatur pikiran.
Padahal, kalau menengok ke asalnya, universitas sejatinya adalah ruang pembebasan. Di Eropa abad pertengahan, universitas lahir dari keberanian untuk berpikir di luar batas kekuasaan gereja dan negara. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang memerdekakan manusia, bukan yang menundukkannya, tapi yang terjadi sekarang jauh berbeda. Banyak universitas justru berubah jadi pabrik pencetak tenaga kerja, “Kebebasan akademik” hanya jadi jargon basi di spanduk-spanduk yang terpampang di gerbang dan linimasa media sosial kampus
Aku melihat sendiri bagaimana banyak teman di kampus lebih takut pada surat peringatan rektorat ketimbang ketidak adilan. Ada organisasi yang rela menggadaikan idealisme demi bantuan dana kegiatan,ada yang sibuk membuat lomba debat tapi tak pernah berani memperdebatkan arah pendidikan itu sendiri. Lucunya, semua hal itu disebut “demi kemajuan kampus”. Aku sering berpikir, kalau kemajuan diukur dari jumlah acara seremonial, maka mungkin universitas kita sudah paling maju di dunia.
Saya rasa sistem pendidikan tinggi saat ini memang dirancang untuk menormalisasi kepatuhan. Kampus mencetak mahasiswa yang jinak, dan manut-manut saja. Mahasiswa kritis dianggap pembuat onar, padahal mereka cuma menjalankan peran sejarahnya.
Paulo Freire menyebut ini sebagai pendidikan gaya bank. Mahasiswa dianggap wadah kosong yang hanya perlu diisi pengetahuan, tanpa hak mempertanyakan isi itu sendiri. Lalu perlahan-lahan, kemampuan berpikir digantikan oleh kebiasaan ikut arus.
Krisis ideologi ini juga membuat Ormawa kehilangan semangat kolektif. Dulu mahasiswa bergerak bersama karena punya rasa yang sama: lapar, marah, dan ingin diperlakukan adil dan setara. Sekarang banyak yang bergerak karena jadwal saja,.
Mereka datang ke perhelatan rapat karena diwajibkan, bukan karena dipanggil nurani. Semua jadi formal, prosedural, dan kehilangan ruh perjuangan. Kita sibuk menulis laporan kegiatan tapi lupa menulis bab baru dalam sejarah gerakan mahasiswa.
Tapi aku percaya, semuanya belum sepenuhnya mati. Masih ada bara kecil yang bisa tumbuh kalau dirawat. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan melahirkan robot birokrasi. Ormawa bisa kembali hidup kalau berani menolak tunduk dan kembali berpihak pada kebenaran. Mahasiswa harus menjadi intelektual organik yang berpikir, bergerak, dan berjuang bersama rakyat. Tan Malaka pernah bilang, tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Tanpa itu, kampus hanya jadi tempat menggandakan ijazah dan melahirkan sarjana tanpa kesadaran.
Refleksiku sederhana: kampus seharusnya ruang pembebasan, bukan ruang penjinakan. Ormawa harus berani menolak peran administratif yang membelenggu dan kembali menjadi ruang perlawanan intelektual. Tidak perlu heroik, cukup jujur dan berpihak. Karena saat mahasiswa berhenti melawan, universitas kehilangan jiwanya. Dan saat universitas kehilangan jiwanya, bangsa kehilangan nuraninya.
Kini, aku merasa mahasiswa perlahan kehilangan maknanya sendiri. Dari kata “maha” yang berarti agung, dan “siswa” yang berarti pelajar, semestinya mahasiswa menjadi manusia agung yang belajar demi kebenaran. Tapi hari ini, banyak yang berubah menjadi “maha-eksiswa” makhluk yang eksis di acara, di foto, di media sosial, tapi absen dalam perjuangan. Kita hidup di zaman di mana pose lebih penting dari posisi, dan dokumentasi lebih diutamakan dari kesadaran.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti jadi “maha eksiswa”, dan kembali menjadi mahasiswa yang berpikir, menggugat, dan berani memihak. Karena tanpa itu, kita bukan lagi manusia pembelajar, melainkan manusia yang sedang dilupakan.
Namun, aku tidak ingin tulisan ini berhenti di nada muram. Aku tahu masih banyak mahasiswa yang gelisah, yang hatinya bergetar melihat ketimpangan, yang pikirannya resah melihat ketidakadilan. Untuk mereka, aku ingin bilang: jangan baper, mari sadar. Ini bukan serangan, tapi ajakan. Mari kita perbaiki dan bangun ulang kesadaran kita bersama. Jadikan kampus kembali hidup sebagai ruang berpikir dan berjuang. Jadikan organisasi mahasiswa bukan tempat menunggu arahan, tapi tempat melahirkan arah. Karena selama semangat itu belum padam, masih ada harapan untuk mahasiswa kembali menjadi “maha” dalam arti yang sesungguhnya.