
Nyatanya, Tidak Semua Orang Layak menjadi Orang Tua: Ulasan The Book You Wish Your Parents Had Read karya Philippa Perry
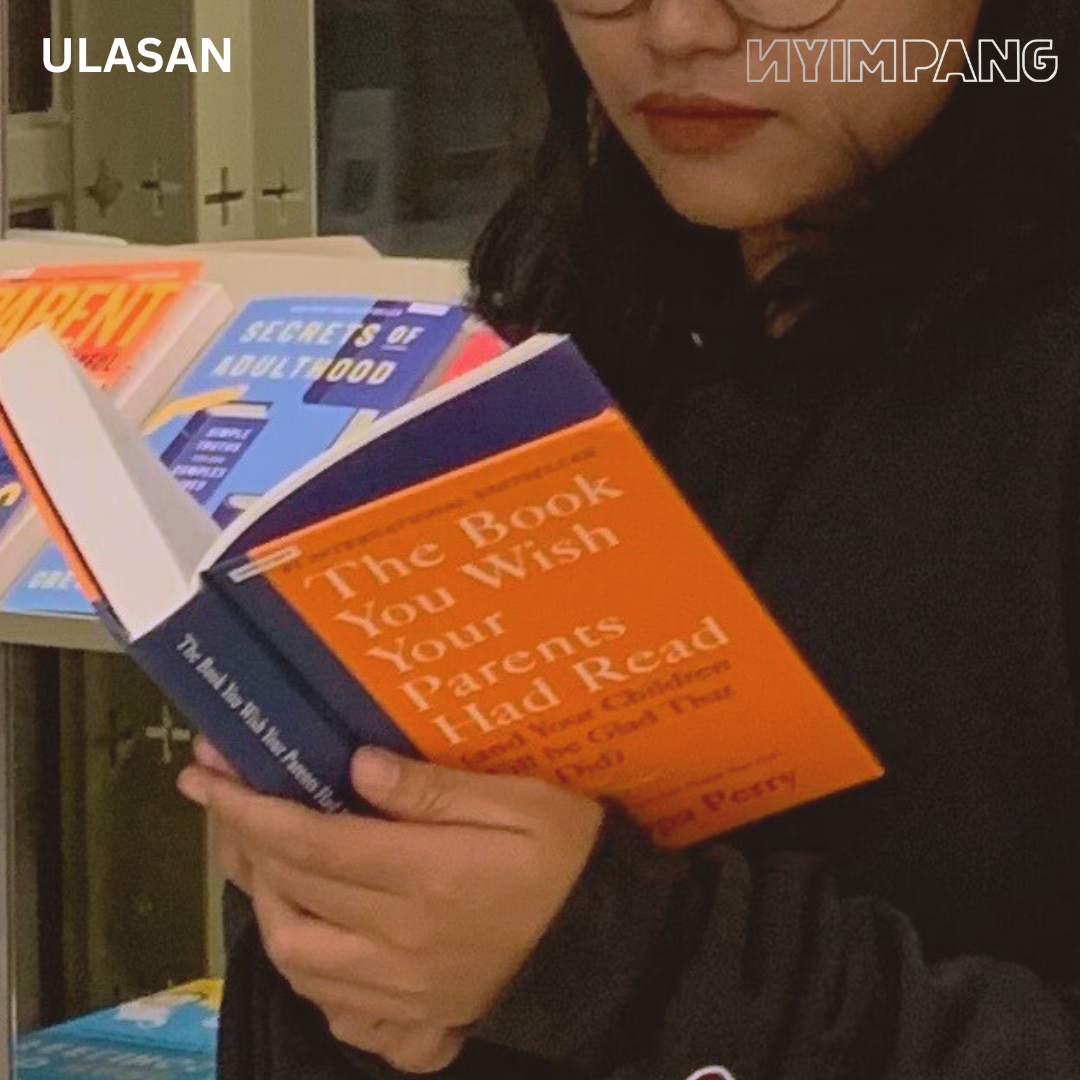
“The cliché is true: children do not do what we say, they do what we do. Before we even consider the behavior of our children, it’s useful – essential even – to look at their first role models. And one of them is you.” Philippa Perry dalam The Book You Wish Your Parents Had Read.
Berbicara soal anak sepertinya akan selalu jadi pembahasan yang panjang, dan bakal terus-terusan “nabrak sana, nabrak sini” tapi sebelum ke anak, saya mau mundur ke orang tua-nya dulu.
Sebagai orang tua atau orang yang “lebih” tua, kita sering dihadapkan pada tantangan untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak-anak kita, terutama dalam hal yang sensitif di negara enih seperti pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.
Meskipun saya amat sangat gak setuju sama Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang terjadi pada remaja-dewasa muda ini hari, tapi setidaknya saat ini saya bersyukur, sebab belakangan orang-orang mulai lebih terbuka ketika bicara soal hal-hal yang dulu dianggap tabu termasuk penananganan KTD. Oh iya, saya bicara dalam konteks persetubuhan yang disetujui dua pihak, ya. Bukan pelecehan atau kekerasan seksual.
Saya tahu gak semua orang sepakat bahwa aborsi adalah pilihan baik, tapi sebagai Arini, saya mendukung hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Aborsi atau tidak, setiap orang berhak menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri.
Dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan (konteks persetubuhan yang disetujui kedua pihak) terutama pada remaja-dewasa muda, jujur saja saya agak bersungut-sungut membahasnya.
Saya tumbuh di masa sinetron menjadikan KTD sebagai tema utama layar kaca televisi zaman itu. Sinetron Suci, atau sinetron-sinetron Mirdad bersaudara deh kalau gak salah. Sinetron-sinetron yang menggambarkan penebusan dosa lewat melahirkan dan membesarkan anaknya. Padahal, melahirkan anak tanpa kesiapan mental dan finansial justru sering berakhir dengan anak yang tumbuh dalam amarah, kelelahan, dan kekacauan emosional orang tuanya.
Celakanya, realita seperti itu benar (dan banyak) terjadi di dunia nyata. Terutama di lapisan masyarakat kelas bawah-menengah, yang beban moralnya lebih berat ketimbang dukungan sosialnya.
Kalau kamu percaya konsep dosa-pahala dalam Islam, mungkin pemerintah yang paling banyak dosanya. Sekarang kutanya, sekolah formal mana yang benar-benar berani memberikan edukasi seks dengan lantang? Kelas enam masuk Bab Reproduksi aja disuruh tutup telinga.
Nying, lah.
Tapi kembali lagi, dalam konteks persetubuhan yang disetujui kedua pihak, melahirkan anak tentu gak se-simple bapil, terus bersin, dan brojol deh. Atau tiba-tiba muncul dari akar pohon. Kan gak gitu, ya?
Pada titik inilah, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa banyak orang tua sebenarnya belum benar-benar siap menjadi orang tua, dan hei! Beranak-pinak itu tidak hanya urusan membuat dan membiayainya saja!
Jangankan dalam kasus KTD yang tadi saya sebutkan, bahkan dalam pernikahan saja banyak kok yang ternyata belum siap. Alasannya sesederhana belum selesai dengan diri sendiri saja.
Banyak orang tua yang belajar mengasuh sambil mengasah masa kecilnya sendiri. Semacam menebak-nebak apa yang seharusnya dilakukan kalau anaknya begini atau begitu. Semacam dijadikan proyek trial and error atau mainan The Sims IRL.
Maka tak heran jika pola asuh yang sama (buruknya) terus berulang dan diwariskan sehingga anak-anak tumbuh bukan dari asuhan kesadaran, tapi dari asuhan yang “salah” atau yang kadung jadi “kebiasaan” saja.
Kenapa Buku ini Penting?
Di sinilah The Book You Wish Your Parents Had Read karya Philippa Perry saya rasa harus dibaca semua orang. Meskipun balik lagi, ya. Gak semua orang punya akses beli buku, dan akses buku bahasa Inggris, anjir! Keur dahar ge hese!
Tapi saya rasa ini penting, sebab buku ini bukan cuma buat orang tua. Semua orang yang tentu sempat merasakan jadi anak-anak, atau pun orang yang akhirnya memilih childfree. Pokoknya selama kamu pernah jadi anak-anak, buku ini harus kamu baca, karena buku ini akan membedah trauma-trauma terdalam pembacanya, dan membuat kita sadar bahwa tidak ada satu pun orang yang layak menjadi korban perpanjangan tangan trauma kita.
Selain itu, buku ini juga membuat saya secara pribadi berpikir dan mulai bergumam begini “Oh … iya iya iya iya,” kepada orang tua saya yang galak itu, karena kadang saya juga lupa, mereka pernah jadi anak-anak.
Buku ini menelanjangi kita untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali pola asuh yang kita terima, dan ya semacam panduan healing kembak-biak generasi, lah.
Perry menampar pembacanya dengan studi kasus dan pengalamannya sebagai psikiater, dan ya resek ketika dibaca karena saya merasa disindir, tapi saya rasa si Perry ini sekaligus mengajak kita melihat diri sendiri. Mengenali luka, kemarahan, dan kebiasaan kita untuk menanggulangi luka dan marah-marah itu. Untuk saya pribadi, membaca buku ini rasanya seperti bertelanjang di depan cermin dan melihat bekas-bekas borok di tubuh kita, yang bahkan kita lupa kita pernah punya borok itu.
Kita dibawa ke masa-masa yang gak gitu menyenangkan di masa kecil, seperti dijeburin ke bak mandi gara-gara gak mau mandi, dipukul karena gak mau salat, atau dibiarin tidur di luar gerbang karena pulang kemalaman. Lalu muncullah perenungan semacam: apakah semua itu sedang kita wariskan ke anak-anak di sekitar kita?
Buku ini menggambarkan bahwa dalam satu waktu, sering kali orang tua melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Entah sadar atau tidak, disengaja atau tidak.
Sebuah pengalaman dari kawannya si Perry digambarkan begini:
Satu hari, ada si Mama dan si Anak. Ceritanya mereka lagi di taman bermain gitu, lah. Terus si Anak ini bergelantungan di jungle gym (yang bulat bulat itu loh, yang buat bergelantungan, dari besi), kemudian si anaknya ini nyungseb kakinya, dan gak bisa keluar pokoknya.
Si Anak teriak minta tolong, “Mama! Mama! Mama tolongin aku!”
Si Mama yang entah asyik atau pusing main HP malah teriak “Get down this minute!”
Yang dengan ilmu penerjemahan saya yang aduhai ini menjadi,
“Turun teu?! Mama bilang turun! Tah, kan! Ceuk Mama oge naon?! Meuni hese dibejaan! Geus gera ntosan amengna, Mama teh keur lalieur ieu! Geus ah sok kitu da dede mah sok ka dieu gera turun! Turun teu?!”
Lalu dengan berupaya sekeras mungkin, si Anak itu berhasil turun. Meski dengan sakit-sakit sedikit. Setelah berhasil turun, si Anak yang menahan tangis itu mengangkat tangannya supaya digandeng si Mama itu malah kena marah lagi.
“Gak! Moal Mama mah moal nyepengan panangan! Sok weh pikasebeleun tuda. Meuni teu daek dicaram.”
Sepanjang perjalanan, si Mama malah ngedumel “Gusti Nu Agung, kieu amat boga budak, teh!”
Minggu selanjutnya, si Mama dan si Anak pergi ke bonbin. Ada lagi lah tuh mainan gelantungan.
Lalu, si Mama karena rasa bersalahnya itu nawarin si Anak begini, “Kamu mau mainan itu?”
Si Anak dengan ragu bilang, “Iya.”
“Iya sok atuh nam,”
Sekarang, si Mama fokus melihat anak perempuannya (gak main HP lagi).
Kemudian, lagi-lagi anaknya ngejebros dan kembali berteriak.
Kali ini, si Mama langsung memberikan instruksi kepada anaknya, “Yeuh! Dangukeun! Eta sampeanana anu hiji ka ditu, anu hiji kieukeun! Karak ngajleng!”
Dan, yap! Si Anak itu berhasil.
Si Anak dengan senang menghampiri si Mama, lalu bertanya “Mama, Mama kenapa nolongin aku sekarang? Kenapa kemarin enggak?”
Si Mama mikir keras (agak ditampar perkataan juga), lalu si Mama jawab, “Waktu Mama seusiamu, Nenekmu manjain Mama banget, selalu nyuruh Mama untuk hati-hati. Gak boleh ke sana, gak boleh ke sini, selalu dipegangin. Mama jadi gak PD kalau mau main tapi gak sama Nenek. Mama jadi gak bisa ngapa-ngapain kalau sendiri. Nah, Mama gak mau kamu negrasain itu. Kamu itu harus bisa sendiri! Apa-apa, semuanya, harus bisa sendiri. Tapi Mama pikir-pikir lagi, Mama gak boleh gitu harusnya sama kamu, karena itu gak adil buat kamu, Mama harusnya bantuin kamu waktu itu juga. Mama cuma kesal sama Nenek dan Mama ngerasa inget lagi zaman Mama dulu aja.”
“Oh, aku kira Mama emang gak peduli sama aku.”
Dari cerita itu, sudah sangat jelas bahwa anak sama sekali gak punya kemampuan dan kewajiban untuk memahami kamu sebagai orang tua, dan anak itu gak berhak dilimpahi trauma atau ketidakmampuanmu menghadapi semua itu.
Ketika si Mamah dimanjakan dan dianggap lemah oleh si Nenek, si Mamah kemudian gak ingin anaknya tumbuh manja seperti dirinya dulu, tapi dalam proses itu, si Mamah justru menjadi orang tua yang dingin, keras, pemarah, dan gak ngotak.
Meskipun pada akhirnya, si Mamah sadar, kemarahannya waktu anaknya ngejebros itu bukan karena anaknya ngejebros aja, tapi marah karena ingat momentum dirinya dan masa lalunya sendiri.
See? Betapa seringnya, tanpa sadar, kita memarahi “diri kita” di masa lalu melalui anak-anak di sekitar kita.
Saya sangat setuju waktu Perry bilang kalau anak bukan perpanjangan ego kita, bukan ajang pembuktian bahwa kita “lebih hebat” dari orang tua kita dulu, kita “lebih hebat” dari anak kita, atau yang paling buruk menganggap bahwa anak kita “lebih hebat” daripada anak orang lain.
Saya percaya, anak-anak gak seharusnya mewarisi trauma atau kegagalan orang tuanya. Kalau dulu kita seringnya gak didengarkan, ya jangan ulangi dengan menutup telinga ke anak kita sendiri. Kalau dulu kita selalu disalahkan, ya berhenti bikin si anak harus jadi yang paling benar.
Ah, soal ini juga. Penerjemahan tindakan. Mungkin, kelihatannya yang terjadi adalah anak tadi gak ngerti maksud si Mamah itu mengabaikan dia.
Tapi yang sebenarnya terjadi adalah: si Mamah gagal menerjemahkan kebutuhan anak karena sibuk menerjemahkan lukanya sendiri. Anjay~
Begitulah cara Perry menelanjangi realitas kehidupan anak-orang tua. Ya, cukup membuat saya sadar juga untuk mengasuh Ceca dengan lebih baik dan benar. Ehehe.
Sekali lagi, Perry bilang, “Children are not responsible for your triggers!”
Orang Tua yang Menempatkan Diri seperti Senior Skena
Siap senior~
Alih-alih menempatkan diri sebagai pembimbing, tak sedikit orang tua yang menempatkan diri jadi senior-senior skena si paling, atau kating-kating komdis ospek kampus, atau alumni nganggur yang doyan ngerecokin acara adik tingkatnya.
“Halah! Sebelum lu juga gua dulu!”
“Lu mah anak kemaren sore!”
“Lu baru nyemplung, gua udah kering.”
Ya arogansi ngehek awal mula tukang bully, lah.
Yang tanpa disadari, mungkin masih banyak arogansi semacam itu di dalam diri orang tua, dan yang paling bahaya: menularkannya.
BTW, buku ini gak cuma bisa dibaca untuk kita yang berkomunikasi sebagai orang tua, tapi justru buku ini juga bikin kita jadi anak yang insyaalloh lebih mengerti orang tua. Jadi, komunikasi di buku ini gak cuma dari kita ke anak-anak kita, tapi dari kita ke orang tua kita dan trauma mereka masing-masing, karena kadang kita juga lupa kalau orang tua kita juga anak dari nenek-kakek kita.
Mungkin, sebagaimana kita, anak-anak pun tak punya pilihan untuk tidak meniru. Sebab sebagaimana juga para penindas, kita mungkin sering merasa diri kita lebih paham cara menghadapi dunia dari segala zaman, padahal nyatanya kita masih linglung menyikapi takdir Tuhan yang gak kita sukai.
Banyak orang yang sering turut berduka, bersedih, turut marah apabila kasus bullying muncul di pemberitaan seperti kasus Timothy kemarin. Tapi kita, yang katanya “sudah kering” itu masih juga tak mau belajar dan luput mengajarkan anak kita supaya jangan merasa paling jagoan dan jangan jadi penindas.
Cuma karena kita lahir lebih dulu, gak berarti kita menjadi tahu semua hal. Cuma karena kita berlayar lebih dulu, gak berarti kita lebih pandai menaklukkan badai, jirlah~ Nyalain mik wireless aja minta tolong Gen Alpha, kan?!
Jadi, ya … kalau hari ini kamu merasa jadi orang gagal, gak apa-apa, lah. Namanya juga manusia, bukan setan.
Kalau merasa belum selesai sama diri sendiri, ya jangan punya anak. Apalagi di musim in this economy-in this economy kalau kata anak Jaksel mah. Gimana kita mau ngenalin dunia ke anak kita kalau kita aja belum selesai kenalan sama diri sendiri?
Tapi kalau kamu tersindir sama buku ini ya bagus lah, artinya kamu sadar dan masih mau belajar. Sebab kalau dipikir-pikir lagi, yang lebih bahaya dari orang tua yang sering salah tuh kayaknya orang tua yang merasa gak pernah salah, deh.
Toh, Perry juga bilang sebelum kita menilai perilaku anak, sebaiknya kita lihat dulu panutannya. Because children do not do what we say, they do what we do.
Kan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya lihat saja lah kalau bapaknya jadi Presiden, terus anaknya harus jadi Wakil Presiden~





