
Membaca Gerak-gerik Dedi Mulyadi dalam Kritik Sosial Kontemporer
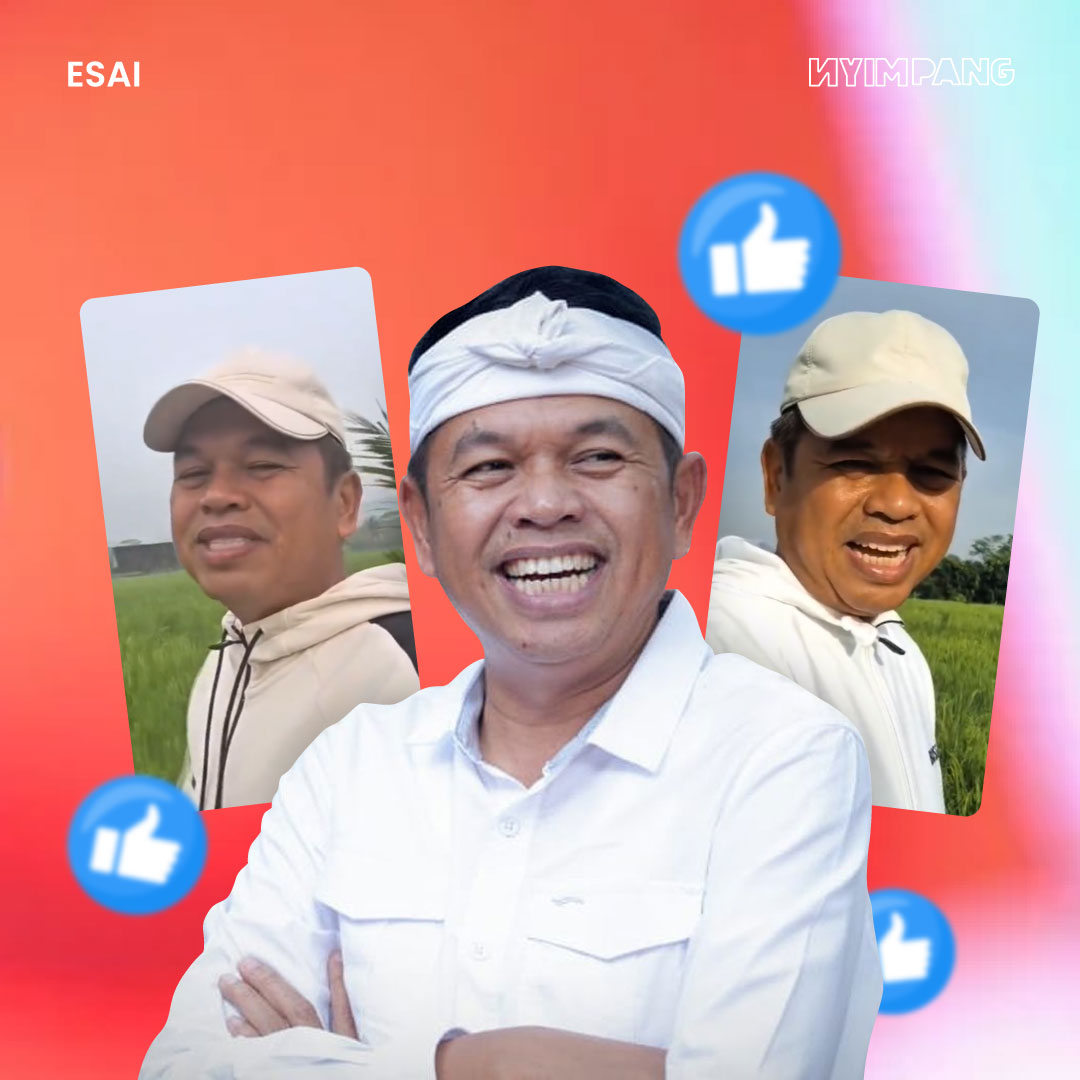
Pada abad ke-21, media sosial gak cuma ngubah cara orang berkomunikasi, tapi juga cara manusia memahami dunia, memaknai politik, bahkan membayangkan keterlibatan sosialnya.
Fenomena Kang Dedi Mulyadi harus dipahami dalam lanskap ini, jadi bukan hanya sebagai seorang politisi tradisional yang turun ke lapangan, tetapi sebagai seorang aktor digital yang sangat memahami logika baru dari produksi kesadaran.
Ia bukan sekadar membangun pencitraan melalui baliho atau koran; ia membangun semesta simbolik yang hidup di platform-platform seperti YouTube, Facebook, dan Instagram—yang setiap like, share, dan komentar bukan hanya tanda keterlibatan, tetapi juga bagian dari logika produksi kapitalistik baru.
Dalam kerangka kritik industri budaya Adorno dan Horkheimer (1944), media modern tidak lagi bertujuan membangkitkan kesadaran kritis, melainkan menciptakan budaya konsumsi untuk setiap produk, termasuk produk politik, dikemas agar mudah dicerna, menghibur, dan mengonfirmasi nilai-nilai yang sudah ada.
Dalam dunia ini, bahkan aktivisme sosial, bahkan kritik terhadap sistem, bisa direduksi menjadi sekadar tontonan cepat konsumsi: sesuatu yang menimbulkan rasa baik di hati penonton, tetapi tidak menuntut perubahan struktural nyata.
Kang Dedi Mulyadi mengerti hal ini, mungkin secara intuitif. Setiap aksinya di lapangan—menegur pembuang sampah, menghibur anak yatim, membantu pedagang kecil—selalu direkam dengan kualitas visual yang apik, disunting dengan musik latar yang menyentuh, dan dikemas dalam narasi storytelling sederhana yang mudah dipahami dan dibagikan.
Tidak ada kerumitan struktural di sana. Tidak ada diskusi panjang tentang sistem ekonomi, hak kepemilikan lahan, atau peran negara dalam menciptakan ketimpangan. Yang ada hanyalah visualisasi aksi individu yang membawa perubahan langsung, cepat, dan penuh emosi.
Dalam bahasa industri budaya, ini adalah produksi afeksi: membangkitkan rasa iba, rasa kagum, rasa haru—semua emosi yang membuat penonton merasa telah melakukan sesuatu hanya dengan menonton, menyukai, atau membagikan video tersebut. Ini membentuk kesadaran palsu baru: bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui perasaan semata, tanpa perlu mengorganisir diri, menggugat struktur, atau mengubah relasi produksi.
Lebih dalam lagi, pola ini menggeser relasi rakyat dengan kekuasaan. Di masa lalu, partisipasi politik berarti turun ke jalan, menghadiri rapat umum, mengorganisir serikat buruh, atau membangun komunitas resistensi. Hari ini, partisipasi bisa berarti sekadar mengetuk tombol like atau mengetik komentar dukungan.
Ini bukan berarti bahwa teknologi sepenuhnya menghapuskan kemungkinan resistensi. Namun dalam logika kapitalisme digital, keterlibatan rakyat justru diproduksi agar tetap pasif: cukup aktif untuk menciptakan data, trafik, dan engagement, tetapi tidak cukup aktif untuk menggugat sistem secara mendasar.
Pada konteks ini, populisme digital KDM beroperasi secara sangat efektif. Ia menawarkan rasa keterlibatan kepada masyarakat—rasa bahwa mereka “bersama” dalam perubahan sosial, bahwa mereka “dekat” dengan pemimpinnya, bahwa mereka “berkontribusi” terhadap perbaikan negeri ini.
Namun, semua itu terjadi dalam ruang yang telah sepenuhnya dikuasai oleh logika platform: algoritma menentukan apa yang viral, apa yang ditonton, dan apa yang terlupakan. Konten yang sederhana, emosional, dan mudah dibagikan lebih diutamakan daripada analisis yang kompleks, kritis, dan membangkitkan pertanyaan.
Maka kita melihat paradoks besar. Di satu sisi, politik terasa lebih dekat dan personal dibandingkan era sebelumnya. Di sisi lain, politik menjadi lebih datar dan terfragmentasi; kehilangan kapasitasnya untuk membangun kesadaran kolektif yang kritis dan proyek perubahan sosial yang berjangka panjang. Hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dibangun melalui media sosial bukanlah hubungan politik dalam arti tradisional, melainkan hubungan afektif yang dimediasi oleh teknologi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah, ketidaksetaraan sosial yang mendalam bisa dengan mudah disamarkan. Ketika seorang pemimpin hadir di media sosial membantu satu pedagang kecil, membersihkan satu sungai, atau menghibur satu anak miskin, narasi yang tercipta adalah narasi perubahan. Padahal sistem ekonomi-politik yang menciptakan kemiskinan massal, pencemaran lingkungan, dan ketimpangan kekuasaan tetap utuh, tak terganggu.
Lewat kacamata Gramsci, ini adalah bentuk hegemoni baru. Rakyat tidak hanya menerima struktur sosial yang ada, tetapi merasa terlibat dalam mempertahankannya, karena mereka diajak merasa menjadi bagian dari perubahan—meski perubahan itu sebagian besar simbolik.
Dalam istilah Adorno, ini adalah industri budaya yang paling sukses: membuat rakyat merasa bebas padahal sesungguhnya mereka tetap terbelenggu dalam relasi produksi yang tidak berubah.
Tentu saja, ini bukan berarti bahwa semua bentuk politik berbasis media sosial adalah manipulatif atau tanpa harapan. Ada potensi emansipasi dalam teknologi digital, jika digunakan untuk membangun solidaritas kritis, mengorganisir gerakan nyata, dan menantang struktur kekuasaan. Namun, fenomena KDM menunjukkan betapa tipis batas antara politik partisipatif dengan politik konsumtif. Di dunia ini, yang menentukan bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi bagaimana pembicaraan itu diproduksi, dikemas, dan dikonsumsi.
Membaca KDM dalam kerangka ini membuat kita lebih waspada terhadap bentuk-bentuk populisme baru yang beroperasi melalui teknologi. Ia memperlihatkan bahwa dalam dunia kapitalisme lanjut, bahkan perubahan sosial pun bisa menjadi sekadar produk visual—disukai, dibagikan, lalu dilupakan—tanpa pernah menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.





