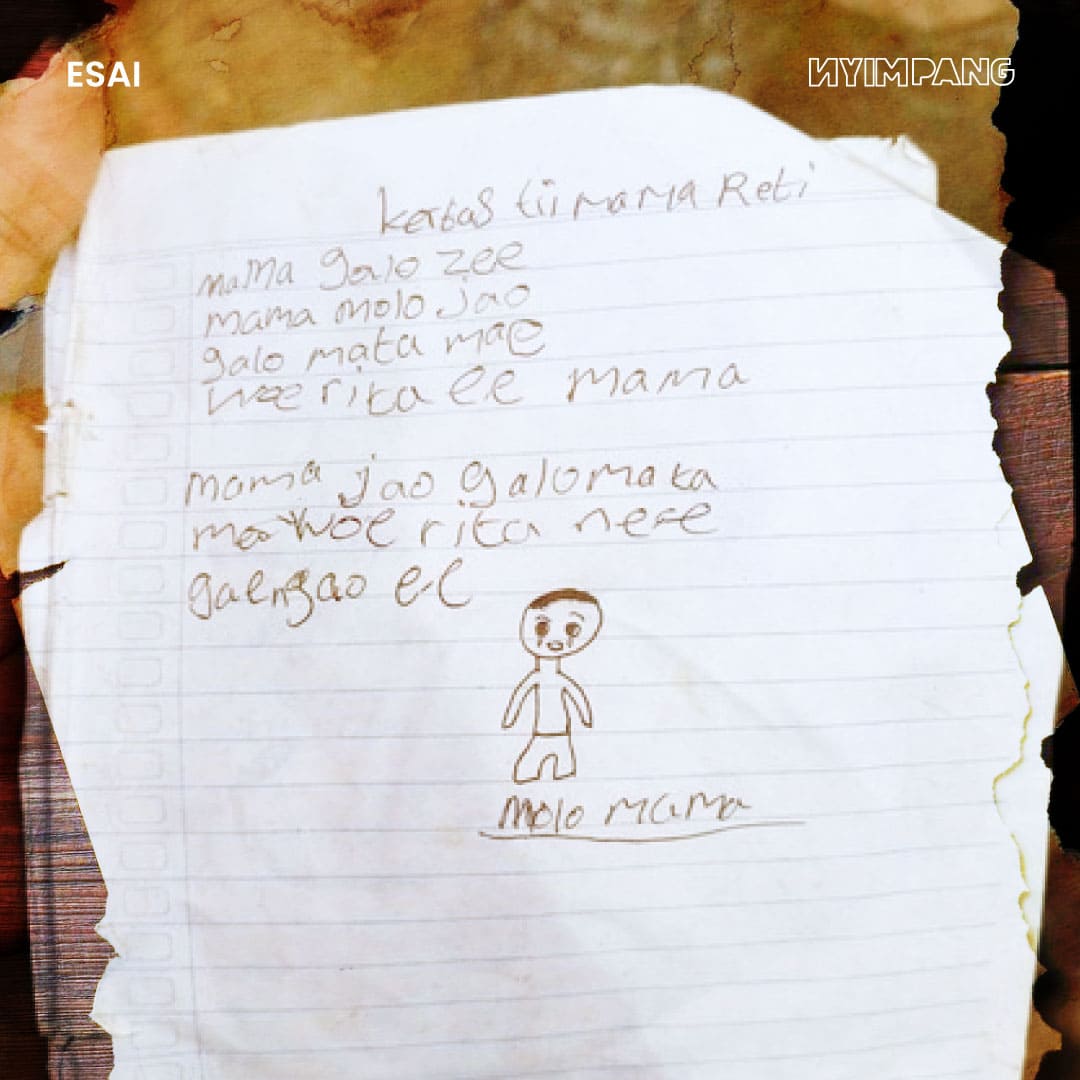Memaknai Hari Tani dan Kembali Menapaki Sawah-Sawah Basah Karawang

Saya meninggalkan Karawang untuk jadi anak sastra di Jatinewyork tepat saat usia saya 17 tahun. Sejak sekolah agama (MDA) sekitar 4 tahun, kaki saya sudah menginjak lumpur sawah di Kosambi, Karawang.
Hobi saya tentulah menghancurkan telur-telur keong yang mirip yupi itu, menangkap belalang lalu dimasukkan ke dalam botol mineral atau dibakar di atas api langsung dan melahapnya, mencabut tanaman urang-aring tak terkecuali lalu menggepreknya untuk kemudian Bunda gosok-gosokkan ke rambut saya yang tipis.
Sisanya, saya senang betul mencolok lubang ular, mengumpulkan tutut, lalu menggoyang-goyang benang yang langsung membunyikan ratusan kaleng pengusir burung. Tidak ada ketakutan apa pun waktu saya main di sawah.
Satu hari, saya kabur dari rumah tapi bukan kabur-kabur drama, sih. Kabur karena ingin main saja. Maklum, dulu saya dan kakak perempuan saya tidak diperbolehkan ke luar melewati gerbang rumah. Entah apa alasannya.

Orang-orang dan keluarga besar kami sering mengatai saya dan kakak perempuan saya dengan sebutan kuda leupas ti gedogan.
Pada hari saya dan kakak saya “kabur” itu, kami pergi ke sawah yang letaknya tak jauh dari rumah kami, malahan tepat di belakang rumah kami.
Hari itu, saya, kakak saya, dan beberapa anak tetangga main di sawah di bawah menara listrik PLN.
Waktu itu musim tandur, sawah Uwa saya baru saja ditanami padi, dan kami bermain lumpur di bawah menara listrik itu. Mencari keong, mengumpulkannya, dan tentu saja bermain benteng-bentengan dengan menginjak-injak padi yang baru ditanami itu.
Saya pergi dari jam 3 sore, dan kami main sampai magrib. Hari sudah gelap dan kami tak takut akan kuntilanak pohon nangka atau kelong wewe.
Badan kami penuh lumpur, hanya ketawa-ketawa, dan berkali-kali jatuh membuat ketawa kami semakin kencang.
Waktu pupujian terdengar, terdengar juga lah Bunda saya berteriak sambil mengacung-acungkan sapu lidi.
Saya memang sering dipukul dan disabet lidi sama Bapak, itu pun karena saya susah bangun salat subuh, tapi kalau sama Bunda saya, itu perkara lain. Ia mengangkat lidi itu, mengacungkannya seperti pedang, dan meneriaki kami menyuruh kami pulang.
Alamak!
Di sepanjang jalan, pantat saya dan si kakak dipukuli dan kami bergantian dijewer.
Oke, begini alasannya:
Pertama, karena kami ke luar rumah.
Kedua, tentu saja karena kami main sampai magrib.
Ketiga, karena kami kotor-kotoran, dan
Keempat, kami merusak padi-padi yang baru ditanami! Betapa dosa saya!
Sebetulnya, dosa saya pada petani bukan cuma itu. Di hari yang lain, Bunda saya sakit. Ia punya kebiasaan merendam beras sebelum dimasak. Dan dengan inisiatif anak kecil secerdas saya, saya diam-diam mencuci beras itu, agar saya tinggal memasaknya di dalam mejikom dan Bunda saya tak usah susah-susah memasak nasi lagi.
Dengan tinggi badan saya yang seuprit itu, saya naik jojodog untuk meraih keran di sink, dan
Brak!!!
Tumpahlah beras-beras yang direndam itu.
Lalu kembali Bunda ngambek dan mendiami saya 2 hari.
Tak berhenti sampai di situ, sampai sekarang, setiap makan, saya masih sering menyisakan nasi di piring. Padahal, untuk bisa jadi sebutir nasi saja, beras itu harus melalui proses yang lebih panjang dari masa PDKT saya dengan si Sayang~
Harus menunggu musim, lahannya harus dibajak, ditanami, diairi, diberi pupuk, dijaga dari burung-burung, ditunggu, dipanen, digebot, dijemur, digiling, ditimbang, dan dimasak! Dan saya dengan sombongnya membuang-buang itu?! Istigfar, Arini!
Setelah bertemu para petani yang ikut menuntut haknya di Hari Tani, saya jadi teringat banyak kenangan masa kecil saya di Kosambi, dan mengingat juga beberapa hal seperti:
Betapa sombong saya
Masih berpikir bahwa menyisakan satu-dua kepal nasi bukanlah dosa besar. Ralat. Jika kamu tidak percaya dosa, maka sebutlah menyisakan nasi adalah perilaku buruk. Perilaku yang arogan dan tidak menghargai petani dan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya. Hal ini berlaku juga untuk semua hasil bumi yang lain, ya!
Kita butuh nasi, tapi seringkali kita abai sama hak-hak petani
Mari kita sebut saja semua penggarap lahan kecuali tuan tanah adalah petani. Berapa banyak petani yang sejahtera? Berapa banyak anak petani yang sulit mengakses pendidikan? Berapa banyak anak petani yang gizinya tak terpenuhi? dan apa yang sudah kita lakukan untuk membantu mereka?
Kela. Jangankan membantu, lah. Mungkin senyum kalau ketemu di jalan aja enggak! Uuuuu shombonk!
Percaya atau tidak, satu kesombongan bisa memunculkan kesombongan lain, lho!
Satu hari, saya melihat teman saya membeli beras seharga Rp200.000,- 1 Kilogram. Kemasannya seperti beras-beras supermarket, lah. Yang bisa ditenteng-tenteng itu.
Awalnya, saya gak tahu itu beras apa, lalu saya tanya,
“Itu beras fukumi namanya. Ini beras bagus! Impor dari Jepang!”
“Oh, bedanya apa?”
“Ini bisa diseduh kaya Popmie, jadi gak usah dimasak.”
Di sini, saya tercengang. Oke. Saya tahu setiap orang bebas habiskan uangnya dengan berbagai cara. Tapi 200rebu untuk beras sekilo? menangys.
Astaga! Saya tahu ada orang yang bisa “membeli waktu” dengan kepraktisan dan nilainya setara dengan jajan saya seminggu. Dan sekali lagi, ini adalah pilihan hidup yang bebas diambil siapa pun, tapi mendengarnya hampir sama seperti melihat orang belanja di supermarket tanpa melihat barcode harga dan menawar habis-habisan waktu beli pisang di pinggir jalan.
Terlebih, saya kurang suka penyematan kata “impor”, terdengar poskol sekali, bukan?!
Saya pun tahu, mental inlander tentu tak hadir begitu saja. Namun, sudah saatnya saya bilang “Habiskan nasi di piringmu!” atau “Ambil nasi secukupnya!” pada diri saya sendiri.
Dengan bertemu para petani kemarin, saya begitu banyak berpikir:
Selama ini, mereka selalu menginjak tanah, selalu menundukkan pandangan untuk melihat tanah. Lalu mereka menanami tanah, menjaganya, sampai bisa menuai yang ditanaminya. Pun, manusia “katanya” berasal dari tanah, dan pepatah selalu nyaring “Semakin berisi padi, maka semakin ia menunduk”. Bukankah indah? petani-petani itulah padi sesungguhnya. Paham menyikapi tanah, menyuburkan tanah, menghasilkan sesuatu dari tanah itu, sampai sesuatu itu bisa muncul dan bermanfaat di piring kita.
Lantas, lihatlah kita. Yang mungkin bekerja di lantai-lantai tinggi di Jakarta, seringkali mendongakkan kepala untuk terus melihat ke atas, suatu tempat yang disebut-sebut dekat dengan Tuhan.
Maka tak heran, apabila dikatakan bahwa orang sombong melihat ke atas atau “… Dan tundukkanlah kepalamu.”
Maka dengan ini, saya akan selalu menundukkan kepala saya di MRT! Tapi saya heran, ketika saya menunduk, bukannya saya makin bersyukur, saya malah makin iri:
“Aduh, orang-orang kok sepatunya bagus-bagus?!”