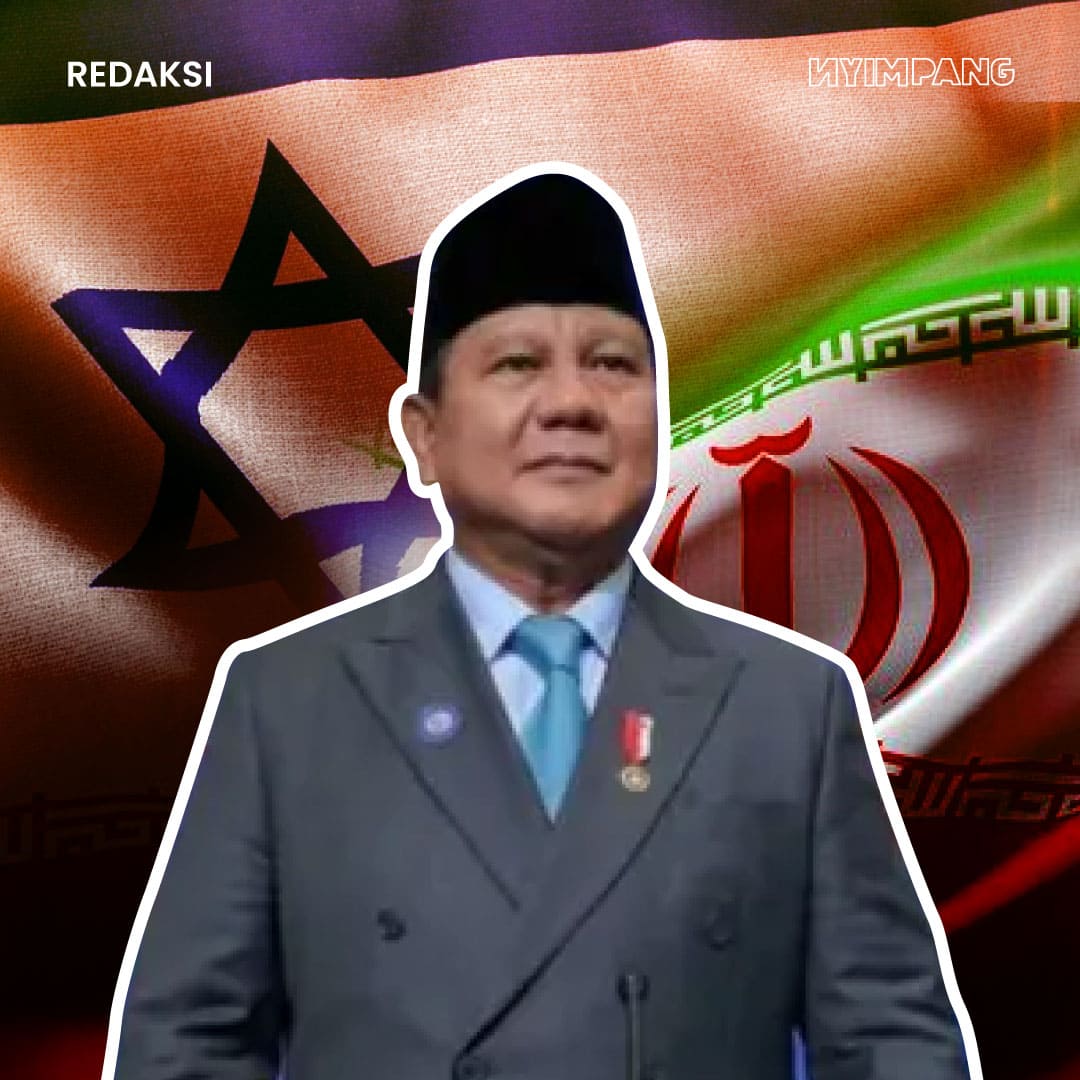
Melawan dan Meledaklah lewat Tulisan

Negara ini sudah lama penuh dengan suara busuk. Dari lidah para pejabat mengalir kata-kata yang lebih kotor dari selokan. Mereka berbicara tentang rakyat, tapi menutup telinga dari jeritan rakyat sendiri. Nyenyenye soal pembangunan, tapi yang dibangun cuma tembok tinggi untuk melindungi istana dari amukan massa.
Mari sejenak kita berpikir: apa gunanya pagar setinggi langit, kalau malingnya bisa keluar masuk dengan bebas, melenggang naik mobil mewah, sementara rakyat kecil di luar pagar terus diawasi, dicurigai, dan ditindas?
Menjadi WNI ini hari seperti domba yang digiring ke penjegalan pajak. Setiap tetes keringat yang jatuh dari punggung orang kecil disedot sampai kering, lalu berubah jadi pesta di meja makan para penguasa. Seperti kata Hok Gie,
”Dua kilometer dari sini, Paduka sedang tertawa dan makan bersama istri-istrinya yang cantik.”
Valid. Valid sekali dengan yang terjadi hari ini, mungkin hanya beda bentuk saja. Waktu rakyat marah, pejabat berjoget angkuh, seolah semua ini bukan hal yang penting untuk dibesar-besarkan. Padahal, yang jelas besarnya adalah penderitaan rakyat.
Faktanya di jalanan: seorang pengemudi ojol terkapar, tubuhnya remuk ditabrak mobil aparat.
Bukan! Bukan kecelakaan dan ketidaksengajaan. Itu adalah simbol bahwa rakyat selalu jadi korban, dan negara selalu jadi yang melindas. Luka di tubuhnya adalah luka kita semua. Darah yang tercecer adalah tinta merah yang menuliskan kebenaran. Sebab negeri ini tidak pernah adil bagi mereka yang hidup dari keringat sendiri.
Mereka boleh kira dengan kebijakan janggal mereka bisa memadamkan kita, tapi justru setiap kebijakan itu adalah bensin yang menyiram api, menjadi bahan bakar untuk terus melawan.
Mereka kira dengan ucapan mereka bisa membungkam kita, tapi setiap kata hina adalah palu yang membangunkan kita dari tidur panjang.
Melawan bukan berarti sekadar menggenggam batu dan melempar ke istana. Melawan adalah berani berkata “tidak” pada kebohongan, merawat sesama yang luka, menulis ketika yang lain dibungkam, berteriak ketika yang lain dipaksa diam. Melawan adalah menyadari bahwa kita tidak sendiri.
Oligarki itu bagaikan menara rapuh yang berdiri di atas pasir, yang tentu saja lebih jelek dari kota-kota di atas pasir Dubai.
Mereka punya uang, punya anjing yang menenteng senjata, punya hukum yang bisa mereka bengkokkan setiap kali moodnya berubah. Tapi mereka gak gak bisa beli kesadaran: satu-satunya hal yang kita punya. Mereka gak bisa memenjarakan harapan. Mereka gak bisa menembak mati solidaritas.
Maka saya berpesan, jangan lagi biarkan kemarahanmu jadi bisikan kecil. Ubah ia jadi nyala api yang membakar gelap. Menulislah! Sampaikan gagasan-gagasanmu! Biar bikin keki penguasa sekalipun. Melawan dan meledaklah lewat tulisan.
Jangan lagi biarkan rasa sakitmu berakhir di kepala dan jadi obat tidur. Ubah ia jadi arus besar yang menggulung tembok kekuasaan. Jangan lagi berpikir ketidakadilan dan semua nasib sial WNI adalah takdir.
Kita adalah rakyat. Kita bukan cuma angka di tabel statistik dan survey bohongan, kita bukan cuma nama di daftar pemilih. Kita adalah daging dan darah yang lama diinjak.
Mereka bisa merampas uang kita, bisa merampas tenaga kita, bahkan bisa merampas nyawa kita. Tapi satu hal yang tak akan pernah bisa mereka ambil: tekad untuk melawan.
Ingat! api kecil emang bisa padam dengan sekali injak. Tapi waktu api kecil itu bersatu, ia menjelma bakal lautan api yang menelan istana. Kita adalah api itu. Kita adalah lautan yang sedang bangkit. Dan kita akan terus menyala, sampai negeri ini benar-benar kembali ke tangan rakyat, bukan oligarki. Tulis! Tulis semua kemarahan dan meledaklah lewat tulisan!
Eh, Nyimpang kebal UU ITE, kan?





