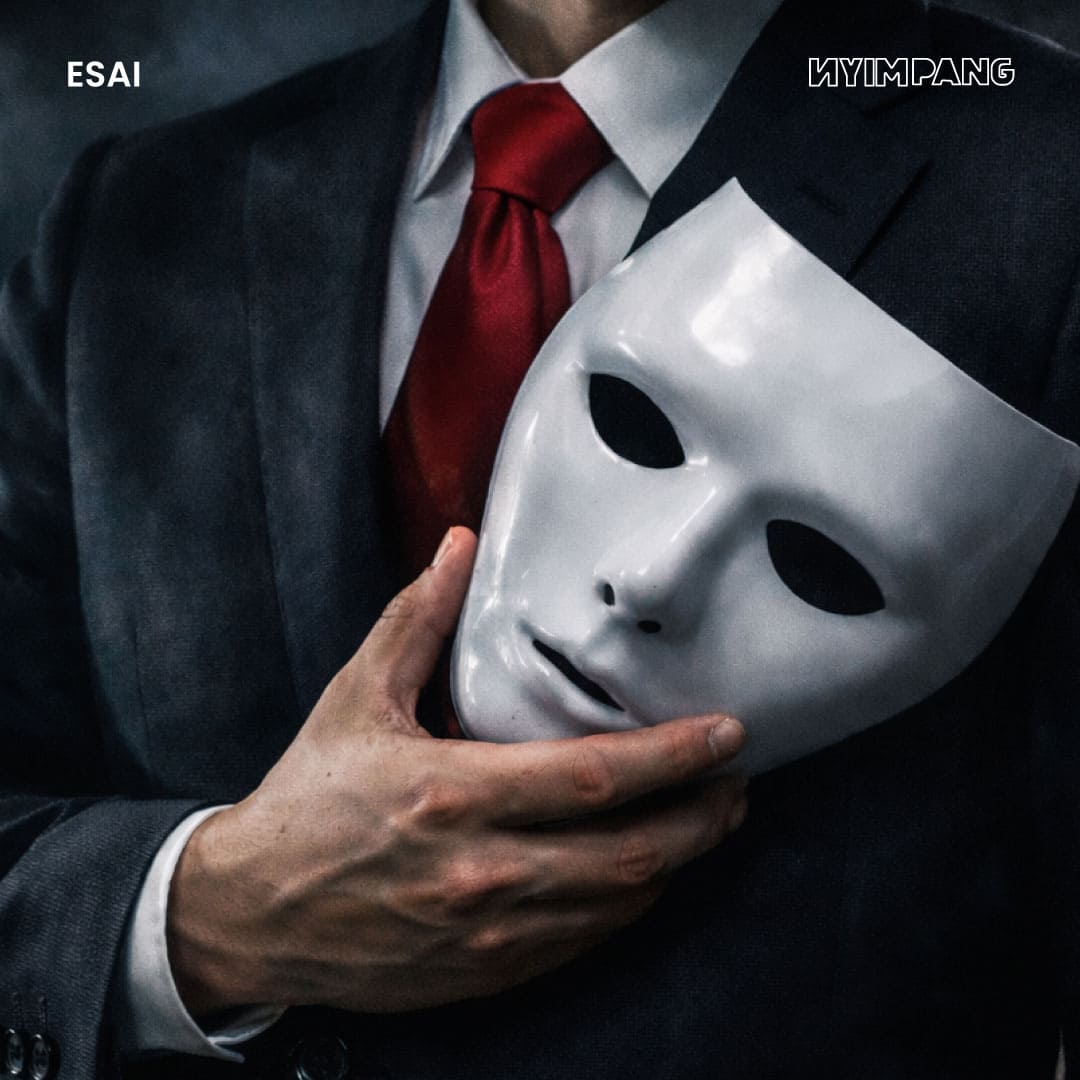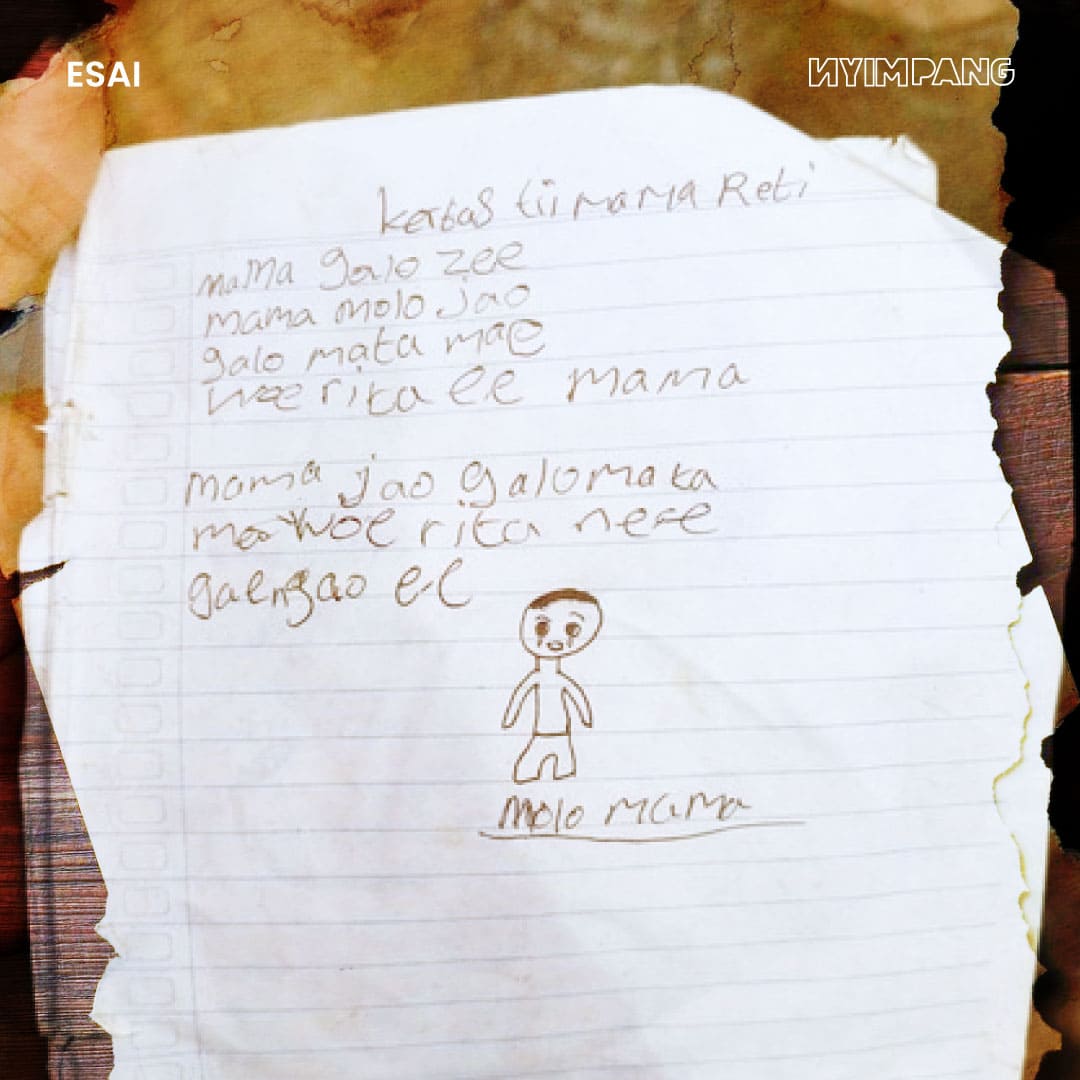Krisis Ruang Aman dalam Pengajaran Fiqih di Lingkungan Pesantren
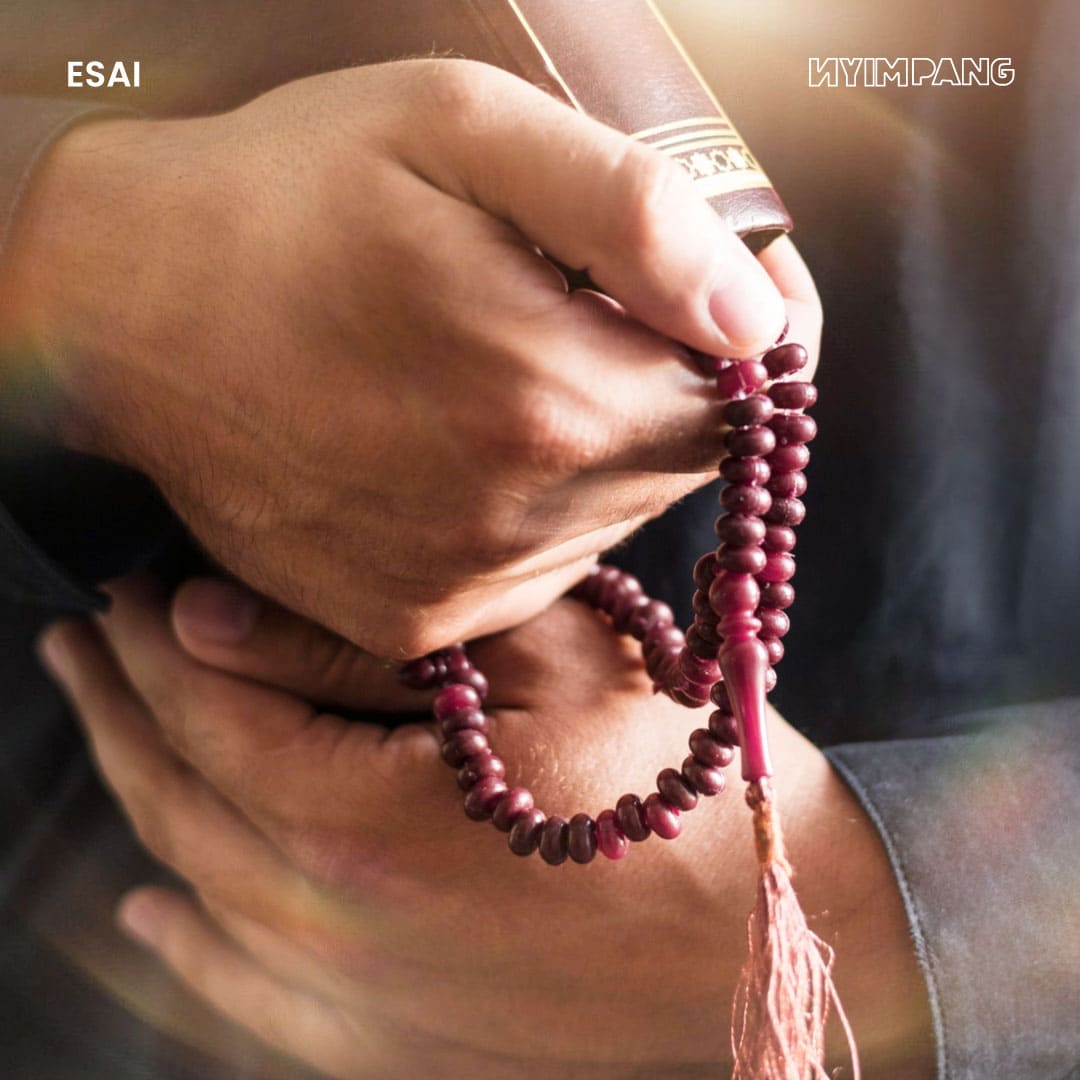
Puluhan kali orang tua membujuk agar saya mondok di pesantren selepas lulus SMA dan meskipun sulit, akhirnya membuahkan hasil juga, seperti kata pepatah:
“Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok,”
Setelah menghadapi berbagai alasan dan penolakan dari saya, akhirnya saya menyetujui mondok dengan syarat hanya bermukim satu tahun saja lalu melanjutkan kuliah. Kebetulan pondok yang dipilih Bapak letaknya tidak jauh dari rumah, kyainya masih kawan satu alumni sehingga Bapak akan lebih mudah “menitipkan” putri semata wayangnya di pondok pesantren beliau.
Sistem pesantren ini masih menganut sistem tradisional, para santri perempuan mengenakan atasan baju padang (baju khas muslim dengan panjang selutut) dan sarung sebagai rok bawahan untuk aktivitas sehari-hari. Aturan lain seperti tidak diperbolehkan memegang gawai, tidak berinteraksi dengan lawan jenis, tidak sembarangan keluar masuk wilayah pesantren dan aturan-aturan lain yang agaknya masih terasa asing dan sulit saya terima sebagai santri baru.
Mungkin karena tidak cocok dengan rutinitas sebelumnya saya saat sekolah yang aktif dan senang bersosialisasi. Semua tampak biasa-biasa saja sampai tiba saatnya rutinitas mengaji kitab yang jadwalnya sibuk sekali, hampir seharian.
Waktu luang hanya bisa diisi dengan menjemur pakaian atau sekadar makan siang saja. Materi kitab yang diikuti pun sangat beragam, mulai dari belajar Alquran dan Tajwid, Adab, Nahwu-Shorof, Sejarah Islam, Praktek Ibadah, dan Fiqih.
Di Pesantren ini, jadwal kitab pengampu Fiqih lebih banyak dari kitab yang lain. Saat pengajian berlangsung para santri berjejer rapi di lantai aula. Ada yang serius menyimak, ada yang tertidur pulas, ada juga yang sibuk menulis diary di buku tulisnya.
Sampai pada suatu malam, kebetulan saat itu saya diminta bergabung dengan kelas “Kabir” atau kelas senior yang berisi para santri yang berusia enam belas tahun ke atas, usia yang dinilai sudah pantas dan sah untuk menikah.
Kebetulan, kitab yang sedang kami kaji adalah kitab Qurotul Uyun, atau kitab yang mengkaji tentang relasi suami-istri termasuk di dalamnya tata cara berhubungan seksual. Malam itu rasanya dingin sekaligus canggung untuk saya yang baru pertama kali mengaji kitab ini. Kami mendengarkan penjelasan ustaz yang setengah serius, setengah menahan tawa. Biasanya suasana semakin ramai saat memasuki pembahasan yang sensitif seperti Fiqih Wanita atau edukasi seksual—yang ternyata tidak terlalu mengedukasi juga.
Di saat-saat seperti itu, ternyata bukan hanya saya yang merasa canggung, tapi santri perempuan lain juga. Sekilas mereka terlihat berpura-pura sibuk membuka kitab, takut jika tiba-tiba ustaz menyebutkan organ kelamin laki-laki dan perempuan dengan istilah jorok alih-alih menyebut penis dan vagina.
Suasana menjadi semakin tidak kondusif saat ustaz menjelaskan posisi bercinta suami istri kepada para santri dengan penggambaran yang erotis. Yang riuh tentu saja santri laki-laki, kami yang perempuan hanya bisa tertunduk malu sambil memejamkan mata.
Masalahnya, Fiqih yang seharusnya menjadi ilmu yang praktis dan rasional, justru sering berubah menjadi topik yang dipenuhi dengan bisik-bisik, candaan, objektifikasi bahkan penilaian moral yang berlebihan. Padahal, justru di bab inilah seharusnya kita belajar tentang otoritas tubuh, kebersihan, dan relasi antar manusia. Terlebih santri perempuan misalnya, kami jadi kesulitan mendapat ruang aman untuk mempelajari hak dan tubuh secara syar’i dan ilmiah hanya karena bahasan ini dianggap lebih “seru” ketimbang lebih “penting”.
Ilmu seperti ini seharusnya dijelaskan secara ilmiah dan terbuka, jika sasarannya adalah para santri yang “mukim” maka bisa memakai pemilihan kata yang sederhana agar mudah dipahami.
Di malam yang lain, saat itu kami sedang menyimak materi “bab haid,” berbeda dengan saat menjelaskan posisi bercinta, ustaz nampak terburu-buru seolah-olah ini bukan bahasan yang penting. Beberapa poin hanya dibacakan saja tanpa dijelaskan dengan detail seperti biasanya.
Hal itu membuat kami (santri perempuan) kebingungan, sebab informasi yang didapat terkesan seadanya dan tidak jelas. Apalagi saat itu, kami kesulitan untuk mendapatkan akses edukasi menstruasi karena tidak diperkenankan membuka internet. Saya berpikir, bagaimana mungkin kami bisa paham hukum fiqih jika hal seperti ini saja terasa tabu dan sulit dibicarakan?
Masalah yang kedua adalah, kekeliruan ini bukan hanya terletak pada penjelasan ustaz saja melainkan budaya pesantren yang menempatkan “topik sensitif” atau bahkan topik-topik lain sebagai sesuatu yang berjarak.
Dalam tradisi keilmuan klasik, beberapa hal memang disampaikan dengan isyarat dan kiasan, agar terkesan sopan dan beradab. Namun sayangnya, dalam praktik “yang beradab” itu sering bergeser jadi “menutup pembahasan”
Akibatnya, santri hanya menerima potongan-potongan hukum tanpa diskusi yang terbuka.
Kita sering lupa bahwa fiqih sejatinya adalah ilmu tentang kemanusiaan. Ia memiliki power yang berpengaruh sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat sosial. Jika pembahasan tubuh, relasi seksual suami istri, menstruasi tidak dibicarakan secara ilmiah, maka yang tersisa hanyalah olok-olok dan stigma belaka. Jelas ini berbahaya, karena membuat ilmu yang seharusnya membebaskan justru malah menumbuhkan rasa takut dan salah paham.
Entah sampai malam Kamis ke-berapa kami, para santri perempuan terus menundukkan kepala karena malu. Yang jelas, malam itu selalu terasa lebih panjang dari biasanya. Saya bergeming, apakah rasa malu itu bagian dari adab, atau sebuah tanda bahwa kita belum terbiasa bicara dengan pendekatan ilmiah?
Saya tidak sedang menuduh atau menganggap salah total sistem pesantren yang seperti ini. Masih banyak nilai luhur yang baik dan tetap relevan seperti adab, keikhlasan menuntut ilmu, dan kedisiplinan. Namun, Ketika sistem itu menolak untuk beradaptasi,yang hilang bukan hanya cara berpikir kritis, melainkan keutuhan ilmu itu sendiri. Sebab terdapat gap yang jauh antar ustaz dan santri untuk berdialog dan bertukar pikiran sehingga proses belajar terkesan hierarkis dan satu arah.
Fiqih seharusnya menjadi jembatan antara teks dan kehidupan, bukan tembok yang membatasi santri untuk berpikir bahkan merampas ruang aman.
Perlunya ruang dialog yang bebas dan terbuka, namun di sisi lain tidak menihilkan nilai-nilai pesantren yang luhur dan beradab agar para santri terlatih untuk berpikir kritis seperti apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu.
Sedangkan adab seharusnya tidak menutup akal, sebaliknya, adab adalah metode untuk menjaga agar akal tetap waras dan rasional saat berpikir. Barangkali, yang mesti kita pikirkan lebih jauh dan perbaiki bukan isi dari kitabnya, melainkan bagaimana cara kita menafsirkan, lalu menyampaikannya kembali dengan pikiran terbuka, bahasa yang sehat dan keberanian untuk memahami.
Seperti apa yang diucapkan Kyai Faqihuddin Abdul Qadir,
“Tafsir tidak boleh berhenti pada teks (lafadz), tapi harus sampai pada misi kemanusiaan dari wahyu.”
Pada akhirnya, tradisi tidak akan kehilangan martabatnya hanya karena membuka ruang dialog atau mengakui ketidakmampuan untuk menjelaskan secara ilmiah. Justru disitulah nilainya tetap hidup dan relevan. Mengaji bukan hanya perihal mengulang teks, tetapi memahami maknanya dengan akal yang sehat dan hati yang jernih.