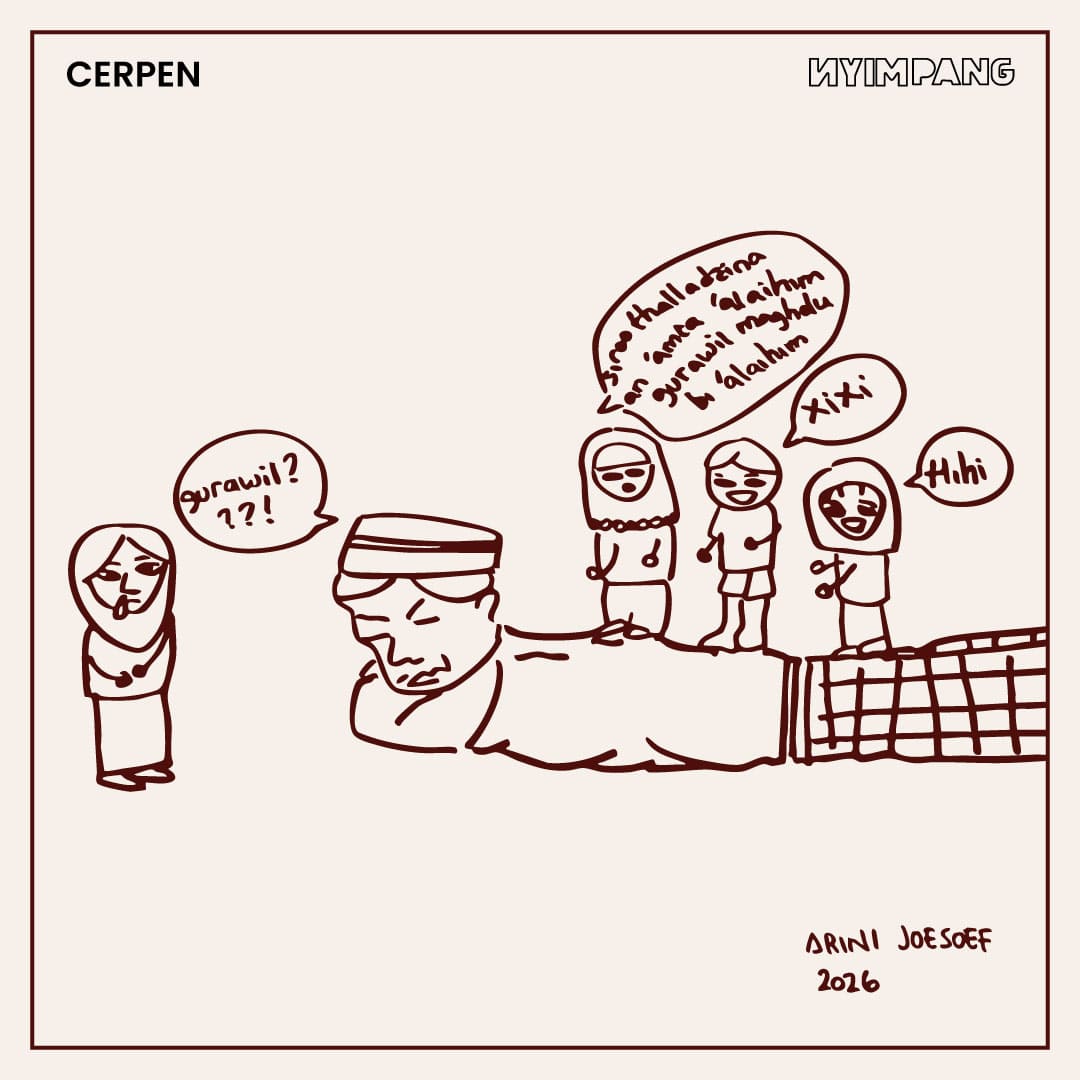Korupsi

Hamzah adalah seorang pemuda berusia dua puluh dua tahun. Ia bekerja di sebuah toko kelontong kecil. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi ramah dan murah senyum. Setiap pagi ia membuka pintu toko, mematikan lampu, lalu menyapu lantai yang penuh debu dari jalan raya. Hidupnya sederhana. Jarang ada keinginan neko-neko.
Pemilik toko kelontong itu, Pak Hasyim, menjadikannya tangan kanannya dan tak ragu memberikan akses ke laci penyimpanan uang. Bertahun bekerja padanya tak pernah Pak Hasyim mendapati suatu yang aneh dari Hamzah.
Hamzah memang tidak digaji besar, tapi cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk memberi ke orang tuanya atau memberi uang jajan keponakan-keponakannya. Meski tak banyak uangnya ia merasakan ketentraman.
Setidaknya begitu, sampai pengaruh buruk Doni masuk ke dalam hidupnya.
Doni adalah teman Hamzah sejak SMA. Orangnya gak mau kalah kalau ngomong, emosian, bicaranya tinggi. Sejak drop out sekolah, hidupnya tak menentu. Kerja serabutan. Kadang ngojek, kadang jualan online, Tapi lebih banyak nganggurnya.
Suatu malam ketika mereka duduk di pos ronda sambil minum es cekek, Doni berkata, “Hamzah, gaji kamu di toko itu berapa sih? Pasti kecil banget, ya?”
“Emang kecil … ” jawab Hamzah jujur, ” … tapi cukup.”
Doni tertawa, “Cukup buat apa? jaman sekarang apa-apa tuh serba mahal. Harga barang-barang udah makin naik sementara gaji kamu segitu-gitu aja. Kerja dari pagi sampai malam, tapi hidup cuma gitu-gitu aja. Kamu kerja apa dikerjain?”
Hamzah terdiam. Ucapan Doni sangat menohok. Padahal Ia tak pernah mempermasalahkan itu sebelumnya.
Doni mendekatkan tubuhnya, dan mengirim bisikan, “toko kelontong itu kan rame terus. Bos kamu kaya. Sesekali malinglah. Kamu berhak menikmati hasil jualan kelontong itu. Bukan Bosmu aja.”
Hamzah tersentak oleh ucapan Doni. Ia menggelengkan kepala.
Doni mengangkat bahu, “Ya udah. Terserah kamu, sih. Padahal kamu yang kerja paling keras, tapi hasilnya bosmu yang nikmatin.”
Kata-kata Doni tenggelam ke dasar hatinya sebagaimana koin jatuh ke kolam permohonan.
Beberapa hari berlalu sejak perjumpaan itu, tapi kata-kata Doni terbalsem awet di kepalanya. Setiap kali membuka laci kasir, ia merasa uang di dalamnya memandang balik padanya. Seolah menggoda, seolah menantang.
Dibarengi kata-kata Doni yang terus bergema di kepalanya. Awalnya lirih, lalu semakin jelas, semakin nyaring, semakin mengganggu. Mengganggu setiap tidurnya, mengganggu setiap lamunannya.
Satu bulan setelah gangguan itu, Pertahanan moralnya runtuh.
Malam itu ketika toko hampir tutup, Hamzah sedang merapikan uang hasil penjualan toko seorang diri. Selembar lima puluh ribu yang tergeletak sendirian, bagai domba yang terpisah dari kawanannya. Ia memandangnya lama. Jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya tegang. Sebuah suara muncul di kepalanya jelas sekali.
Lima puluh ribu aja. Besok bisa diganti, kan cuma sekali.
Tangan Hamzah gemetar ketika mengambil uang lima puluh ribu itu. Memasukannya ke kantong celana jeans nya dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya ia mencuri.
Sayangnya pencurian pertama ini tidak menjadi pencurian terakhir.
Sebelum mengambil uang itu, hidup Hamzah baik-baik saja. Uang gajinya memang pas-pasan, tapi ia bisa menabung, bisa memberi untuk orang tuanya ataupun untuk keponakan-keponaknnya. Tapi setelah pencurian pertama itu, semuanya berubah. Gajinya yang dulu terasa cukup tiba-tiba terasa kecil, sangat kecil. Hatinya selalu merasa kekurangan.
Awal bulan belum lama berlalu, namun uangnya sudah menipis. Ia jadi sering ke luar rumah, nongkrong lebih lama, belanja untuk hal-hal yang tak ia perlukan. Uang gajinya hilang seperti kelinci di topi pesulap.
Dorongan untuk mencuri semakin kuat. Setiap kali bekerja ia selalu menantikan kapan bosnya pergi, kapan ia bisa mendekati laci kasir, kapan ia bisa mencuri lagi.
Sering kali di kepalanya Hamzah beradu argumen dengan diri sendiri. Ia ingin mencuri lagi. Ia tahu tindakannya salah. Ia merasa berdosa karena telah mengkhianati kepercayaan yang Pak Hasyim berikan padanya. Tapi gajinya masih tiga minggu lagi, dan dompetnya kosong. Ia kalah.
Aku berjanji ini yang terakhir.
Ia mencuri lagi. Dua puluh ribu. Lalu besoknya tiga puluh ribu. Lalu suatu hari, seratus ribu. Semakin sering ia mencuri perasaannya makin biasa saja. Tak ada degup jantung kencang seperti sebelumnya. Tak ada perasaan tegang seperti yang lalu. Seakan mencuri tak ada bedanya dengan kentut belaka.
Suatu malam setelah menghitung hasil penjualan, selisih uang di kasir mencapai dua ratus ribu. Hamzah gemetar. Ia tak mengambil sebanyak itu hari ini.
Pak Hasyim yang mencatat pembukuan malam itu memandang tumpukan uang, mengernyit, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, “Ini kenapa selisihnya jadi makin sering gini ya?”
Detik itu seluruh udara di sekitar Hamzah menghilang. Ia mematung, tangannya dingin, tenggorokannya tercekat.
“Mungkin … saya salah hitung Pak.” Suaranya nyaris tidak terdengar.
Pak Hasyim menatapnya lama. Lama sekali. Lalu menghela nafas lelah, dan menggaruk-garuk rambutnya.
“Kamu pulang saja dulu. Besok kita bicarakan.”
Malam itu waktu berjalan lambat sekali. Di kasurnya Hamzah terbaring gelisah. Memandangi langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk dan terus terpikirkan tatapan lama dari Pak Hasyim. Hamzah bisa menangkap arti dari tatapan itu. Sebuah kecurigaan, sebuah isyarat tak percaya. Pada titik itu ia menyesal semenyesal-menyesalnya. Ia bersumpah tidak akan mencuri lagi.
Ia kehilangan ketenangan. Kehilangan rasa syukur. Kehilangan dirinya sendiri. Mencuri tak serta merta membuatnya jadi lebih senang. Uang yang ia ambil tak pernah membuatnya merasa sejahtera. Justru membuatnya semakin miskin. Lahir dan batin.
Keesokan harinya Hamzah datang lebih pagi dari biasanya. Toko belum buka. Ia mengetuk pintu dengan perasaan seperti ada batu besar menindih dadanya.
Pak Hasyim membuka pintu. Wajahnya cerah, namun tatapannya serius melihat Hamzah.
“Pak,” suara Hamzah pecah “Saya mau ngomong jujur.”
Mereka berdua duduk di bangku dekat meja kasir. Pintu geser toko terbuka sedikit, cahaya pagi mendarat di gundukan beras. Hamzah menceritakan semuanya dengan jujur tanpa ditutup-tutupi. Ia mengakui kesalahannya. Suaranya gemetar melawan malu dan takut.
Saat ia selesai bercerita, ia menunduk. Hening lama di antara keduanya menjelma siksa bagi Hamzah. Ia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mungkin bentakan, atau mungkin pemecatan.
Namun Pak Hasyim justru berkata pelan, “Hamzah, jujur saya kecewa sama kamu. Tapi saya akan tetap memberi kamu kesempatan. Kalau kamu melakukannya lagi saya tak akan maafin kamu.”
Hamzah semakin menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan.
“Terima kasih, Pak!” Hamzah berlutut dan memeluk kaki Pak Hasyim. Tangisnya makin tak tertahankan.
Pak Hasyim melepaskan tangan Hamzah dari kakinya, “sudahlah. semuanya sudah terjadi. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jangan mencuri lagi! Jangan Korupsi! Uang hasil begitu tidak berkah. Bikin hidup jadi tak tenang.”
Hamzah bersyukur mendapatkan kesempatan dari Pak Hasyim. Ia berjanji tak akan mencuri lagi.