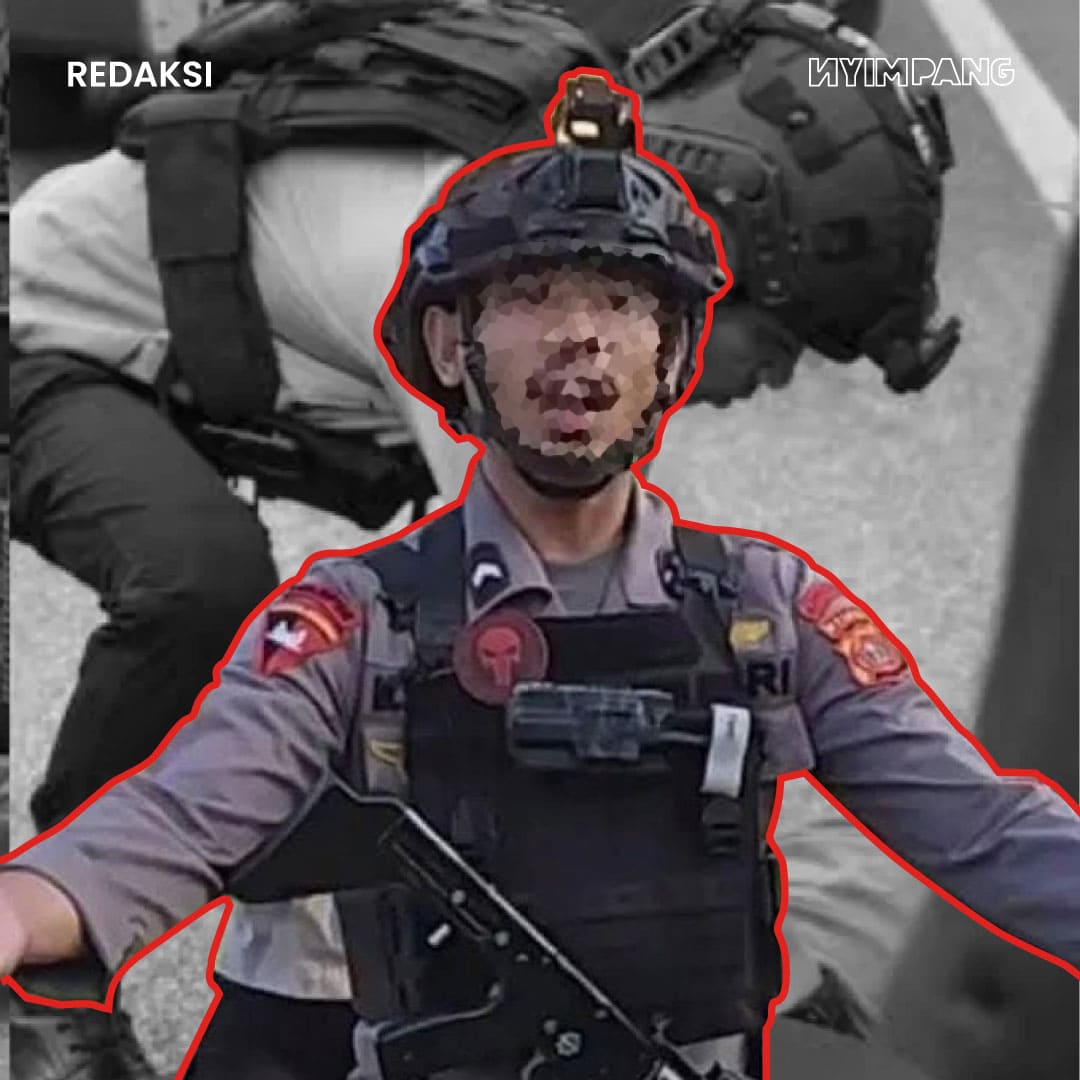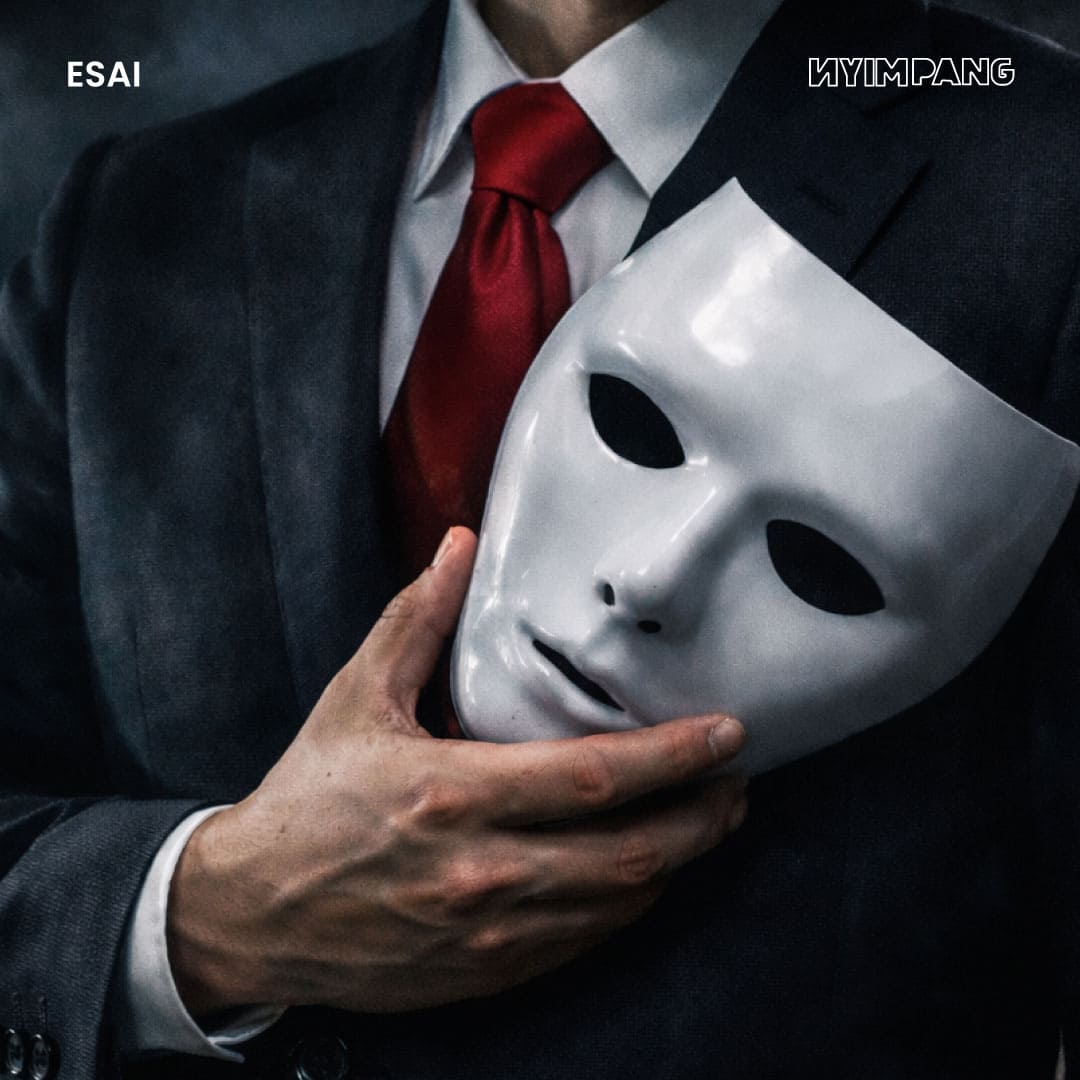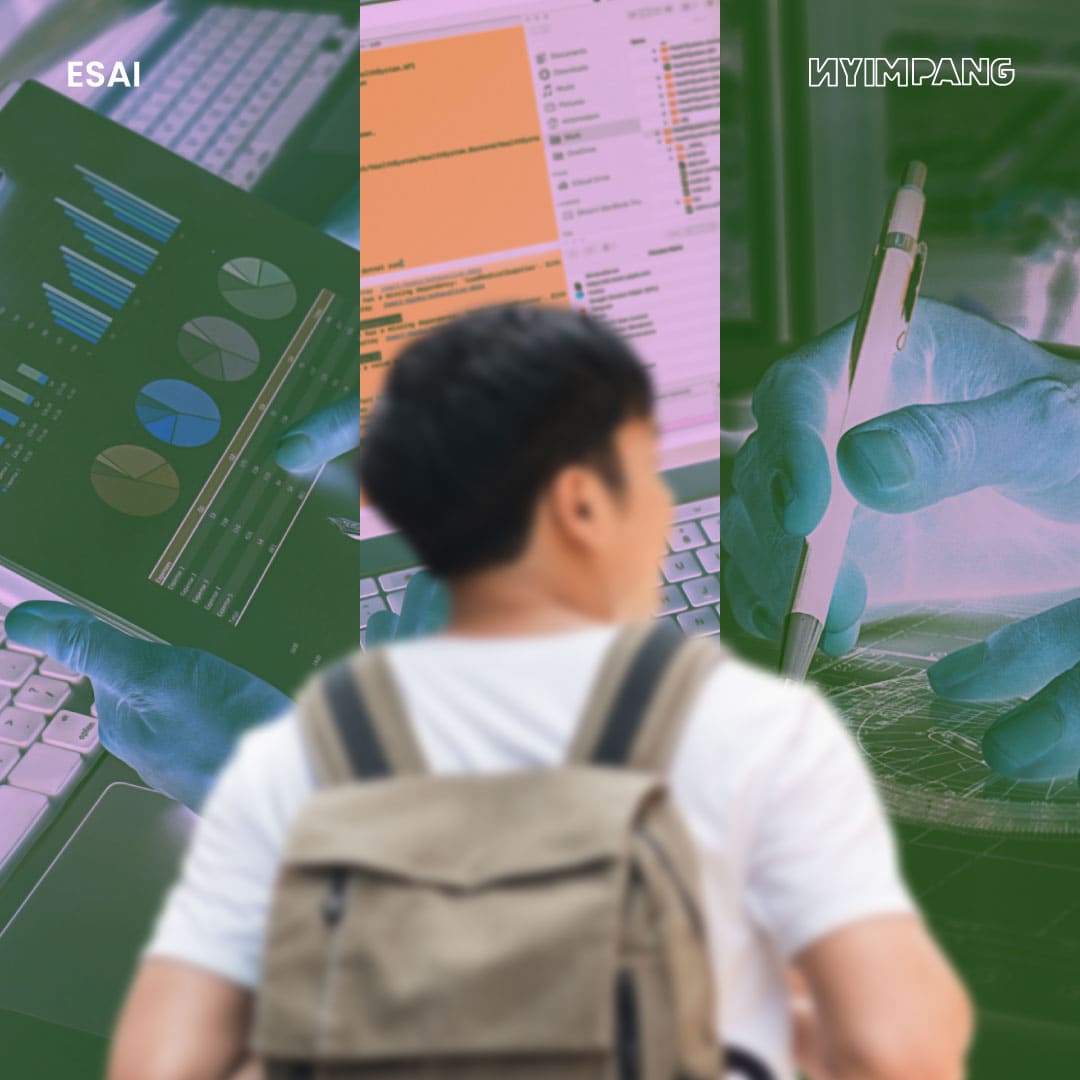
Kata Mereka: Pria (Harus) Punya Selera, Asalkan Jangan Korea!
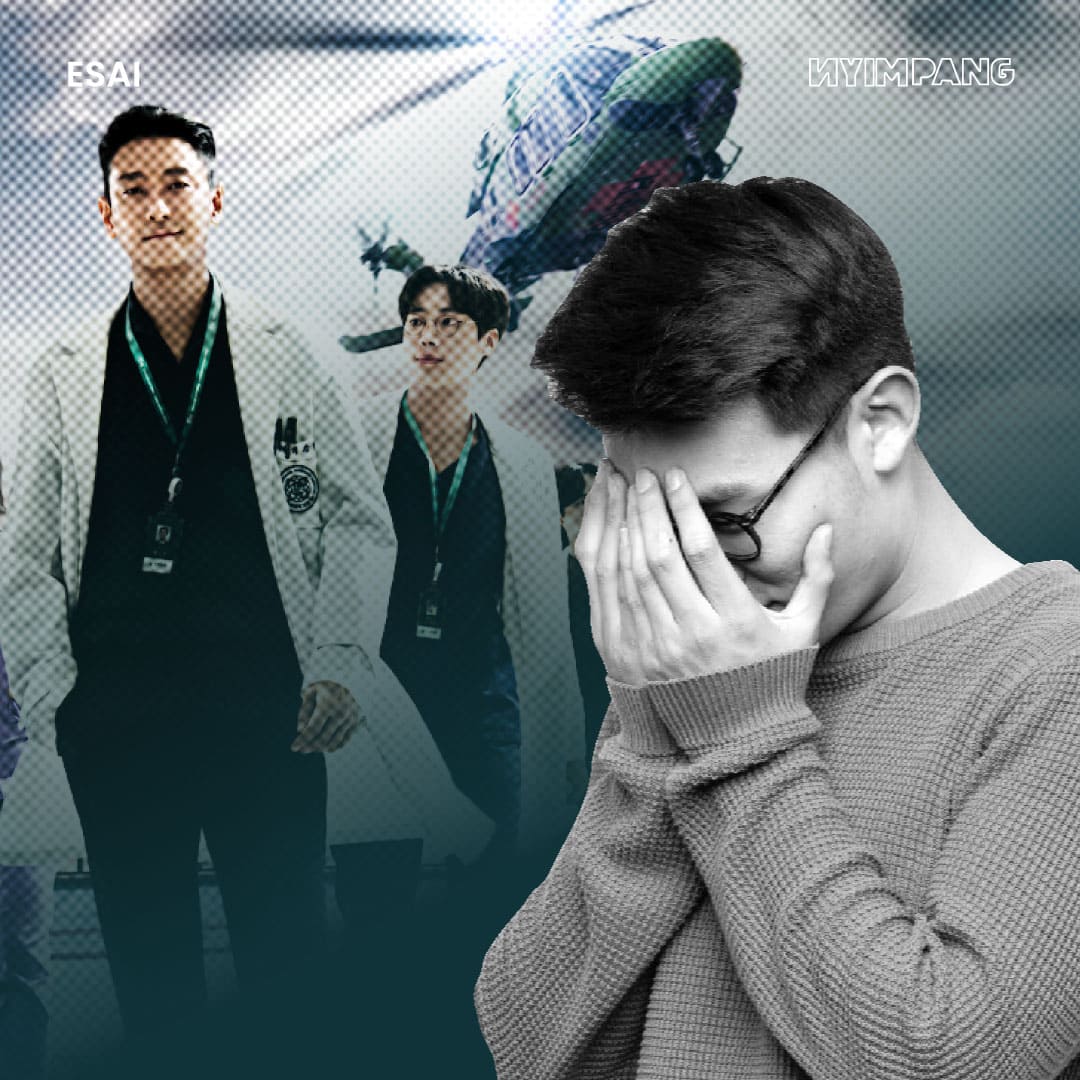
Beberapa tahun lalu, saya nonton film Korea berjudul Ashfall. Filmnya bagus: ada konflik geopolitik, bencana alam, dan sinematografi yang solid. Gak ada adegan romantis yang terlalu manis, ataupun aktor-aktor dengan penampilan bling-bling berlebihan seperti yang dibayangkan banyak orang soal film Korea. Tapi anehnya, begitu saya cerita ke teman-teman laki-laki, reaksinya begini,
“Wah, Korea ya? Plastik dong!” atau “Tontonan cewek tu”.
Waktu itu saya hanya bisa diam. Tapi di dalam hati, saya mikir: kok bisa ya film sebagus itu langsung di-dismiss cuma karena ‘Korea’?
Tidak berhenti di situ. Bulan lalu, saya sedang menonton drakor The Trauma Code: Heroes on Call, drakor medis-komedi dengan plot yang lumayan intens. Tanpa tau jalan ceritanya, Om saya yang lewat di ruang tengah spontan berkomentar,
“Laki kok nontonnya drakor? Tonton film action kek.”
Nada bicaranya santai, tapi tetap mengandung penghakiman yaumul hisab
Lucu juga ya. Tanpa peduli seberapa tegang alur ceritanya, atau seberapa menarik pembangunan karakternya, begitu tahu ini produksi Korea, langsung dicap “kurang laki”. Baru-baru ini saya juga mendapatkan rekomendasi musisi bernama Eaj dari teman dekat saya. Produksi musiknya matang, liriknya dalam, dan sepenuhnya berbahasa Inggris, tanpa terdengar sama sekali aksen bahasa lain. Bahkan saat awal mendengar, saya kira dia bule Amerika, sampai akhirnya dikasih tahu oleh teman saya bahwa dia sebenarnya keturunan Korea-Amerika, dulunya juga member boyband Korea. Saya akui, rekomendasi teman saya memang belum pernah gagal, tapi tetap saja, saya sempat mikir dua kali waktu mau follow akun Instagram Eaj. “Nanti dikira Korea-Koreaan lagi nggak, ya?” Jadi, sebenarnya fenomena apa yang sudah saya alami secara berulang-ulang ini? Atau jangan-jangan di luar sana juga ada mas-mas yang punya pengalaman yang sama dengan saya?
Aturan Tidak Tertulis Kaum Adam
Ternyata setelah sedikit research, masalahnya bukan soal Korea-nya. Bukan juga soal genre film ataupun musik. Yang membuat serba salah justru “aturan tak tertulis” yang sudah menempel di pundak laki-laki sejak kecil. Bahwa laki-laki harus tegas, harus kuat, dan harus suka hal-hal yang “keras”.
R. W. Connell menyebut ini sebagai hegemonic masculinity, versi maskulinitas yang dianggap paling sah, paling dominan dan superior dalam struktur sosial. Versi yang sering kita lihat di iklan rokok ataupun film laga yang berdarah-darah. Kata Connell, tidak semua laki-laki akan berperilaku seperti maskulinitas hegemonik ini, tapi semua laki-laki akan diukur berdasarkan standar itu (Gender and Society, Vol. 19, No. 6, 2005: 832)
Aturan tak tertulis ini bukan cuma dianggap ideal, tapi juga menjadi semacam sensor sosial. Kalau kamu melenceng sedikit saja, misalnya menyukai lagu romansa yang mellow, atau suka menonton film genre romansa, reaksi sosial bisa langsung muncul: dikatain lembek, diledek teman, atau bahkan langsung kehilangan “kejantanan” di mata mereka. Padahal kenyataannya, selera dan maskulinitas bukalah suatu hal yang harus saling meniadakan. Sebenarnya, menonton drama atau mendengar lagu Korea tidak akan membuat seseorang kehilangan identitas sebagai laki-laki kok. Tapi ya itu tadi, sensor sosial akan tetap bereaksi lewat tatapan geli, komentar sinis, atau candaan yang diam-diam banyak hinaan.
Tapi kenapa harus Korea yang sering jadi sasaran? Mungkin karena dalam imajinasi populer, budaya pop Korea sering dikaitkan dengan kelembutan, estetika, dan ekspresi emosional yang kuat. Idol pria berdandan rapi, kulit bersih, rambut dicat terang, dan kadang tampil dengan busana penuh warna. Drakor juga sering menampilkan cerita emosional, tokoh laki- laki yang sensitif dan romantis.
Nah, semua ini dianggap bertabrakan dengan konstruksi maskulinitas ala hegemonic masculinity di banyak budaya, termasuk di Indonesia. Alhasil, tontonan atau musik dari Korea menjadi simbol dari segala hal yang dianggap “kurang jantan”. Yang memperumit, stigma ini justru sering berasal dari dalam lingkungan laki-laki itu sendiri. Kita tumbuh dalam lingkungan sosial di mana laki-laki bertugas sebagai “pengawas kadar maskulinitas” laki-laki lain. Istilahnya, policing masculinity, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh C. J. Pascoe.
Pascoe menjelaskan bahwa laki-laki kerap saling mengawasi dan mengoreksi perilaku satu sama lain untuk memastikan mereka tetap berada dalam batas “maskulin” yang diakui secara sosial. Caranya? Lewat sindiran, ledekan, atau bahkan hinaan yang dibungkus candaan, persis seperti yang saya ceritakan tadi.
Dalam bukunya Dude, You’re a Fag: Masculinity and Sexuality in Highschool (2007: 60), ia mengamati bagaimana remaja laki di sekolah menggunakan ejekan dan lelucon sebagai alat untuk menjaga hierarki maskulinitas. Lewat yang ia sebut fag discourse, mereka saling ledek bukan karena benar-benar menganggap temannya feminim atau homoseksual, tapi karena itu cara tercepat untuk menegaskan siapa yang “paling laki” dalam lingkaran pertemanan mereka.
Ucapan seperti, “Laki kok nontonnya drakor? Tonton film action kek”, bukanlah sekedar opini iseng. Inilah bentuk nyata dari pengawasan sosial. Seolah-olah ada standar tak tertulis yang menentukan tontonan mana yang boleh disukai laki-laki, lagu mana yang cukup “jantan”, dan selera apa yang sah untuk ditampilkan ke publik.
Padahal ini bukan soal Korea semata. Ini soal bagaimana selera (sesuatu yang seharusnya bersifat personal), bisa dijadikan alat ukur tingkat kejantanan seseorang. Aneh bukan? Kita hidup di mana selera bisa menjadi suatu hal yang beresiko secara sosial. Yang paling mengganggu dari semua ini adalah kita jadi belajar menyensor diri sendiri bahkan sebelum orang lain melakukannya. Kita diam, tahan cerita, sembunyikan selera. Bukan karena takut salah, tapi karena resikonya. Agar tetap aman, tetap terlihat maskulin, dan tidak menjadi bahan roasting di tongkrongan.
Mungkin sudah saatnya kita mendefinisikan ulang apa itu maskulinitas. Tidak melulu harus dingin, kaku, keras, dan tangguh. Karena yang lebih susah justru menjadi laki-laki yang jujur soal apa yang dia suka, meskipun itu nonton film romansa, mendengarakan musisi Korea, ataupun hal lain yang dianggap sedikit anti-mainstream. Bukan karena ingin terlihat beda, tapi karena memang bagus. Titik.
Jadi ya, nikmati saja. Selama tidak menyalahi aturan agama, negara, ataupun mengganggu orang lain, biarkan selera tumbuh dan berkembang. Karena dalam banyak kasus, yang membuat seseorang terlihat ‘kurang laki’ bukan soal apa yang dia sukai, tapi seberapa takut dia dihakimi karena kesukaannya. Ingat, semua orang punya selera! Tapi seleranya tidak harus selalu sama, ‘kan?