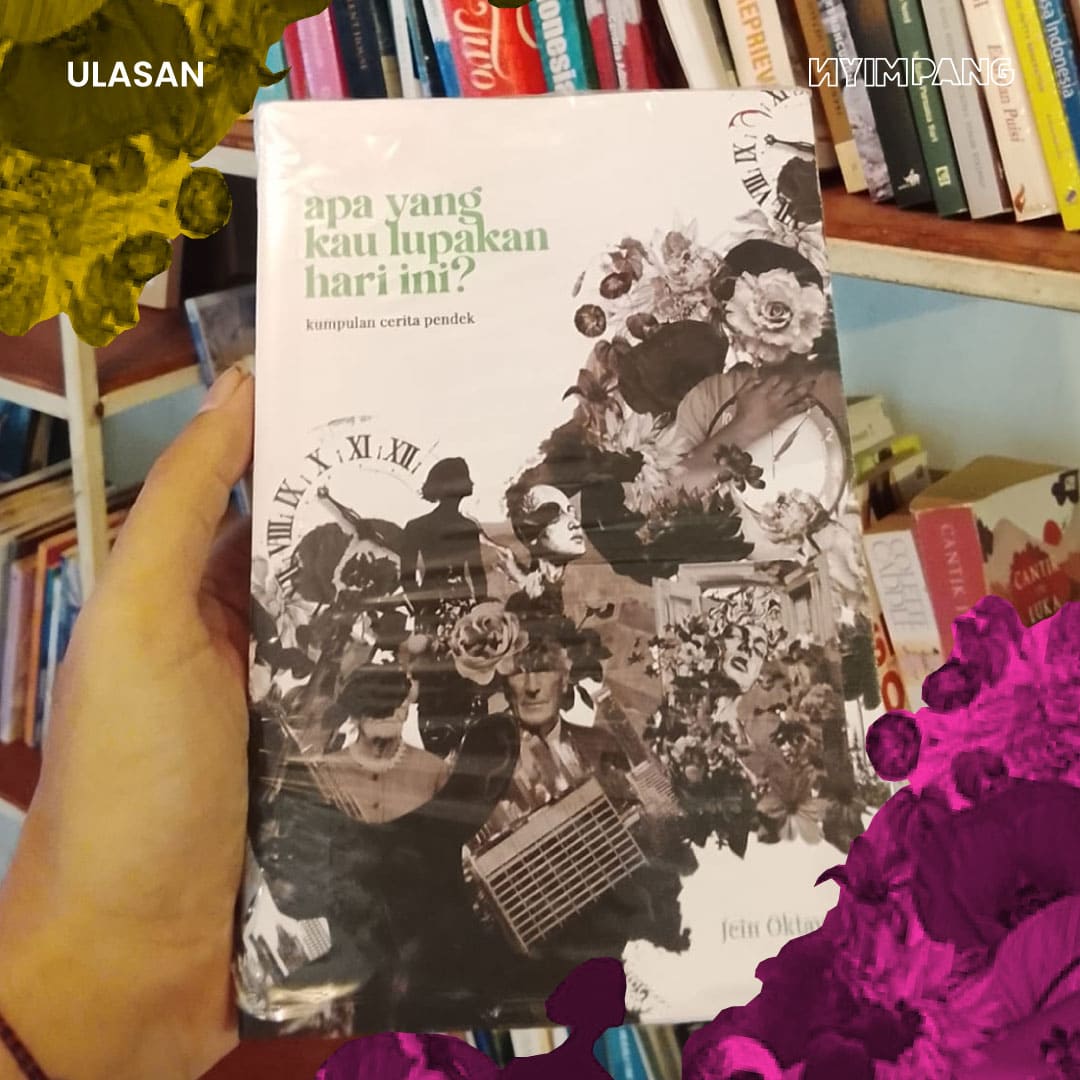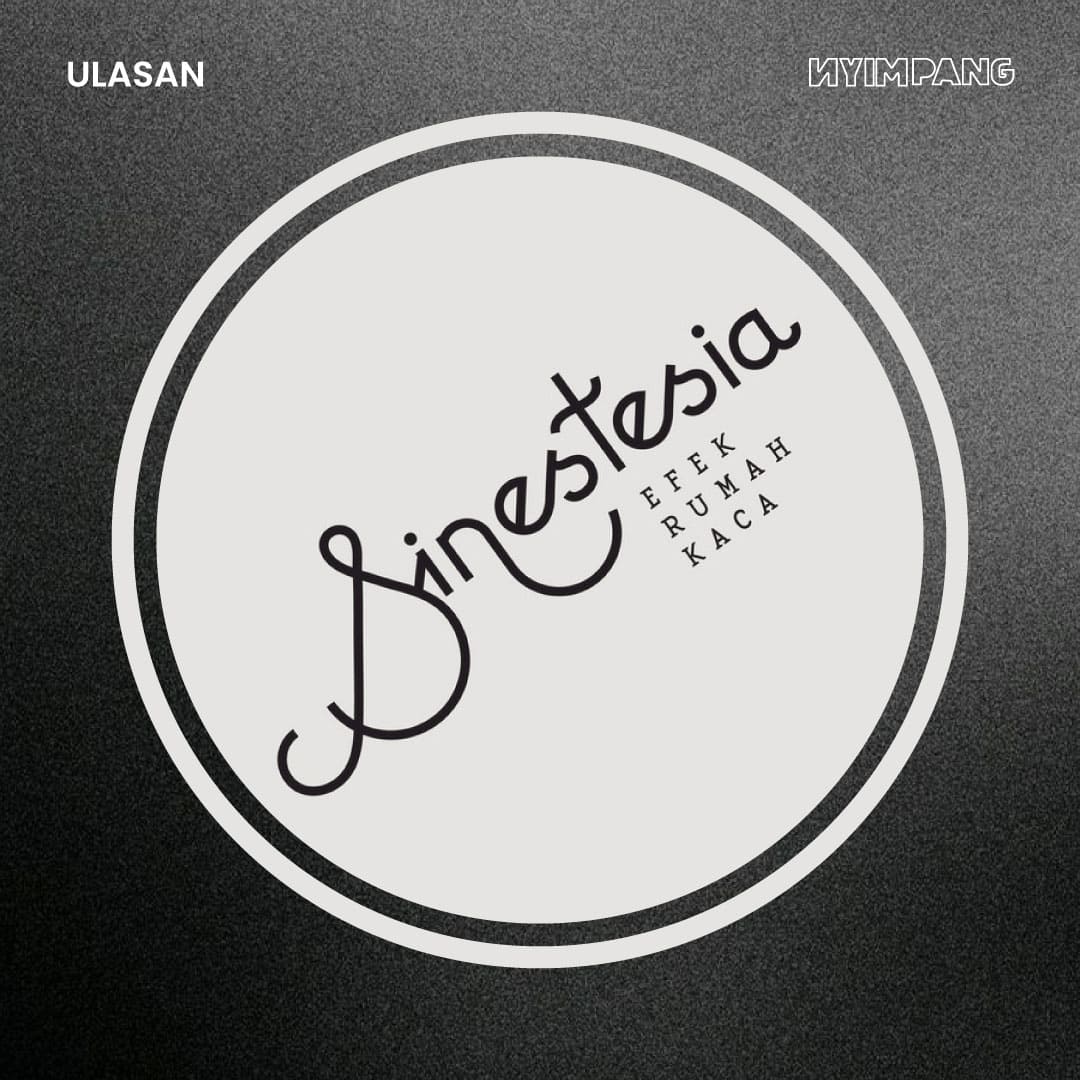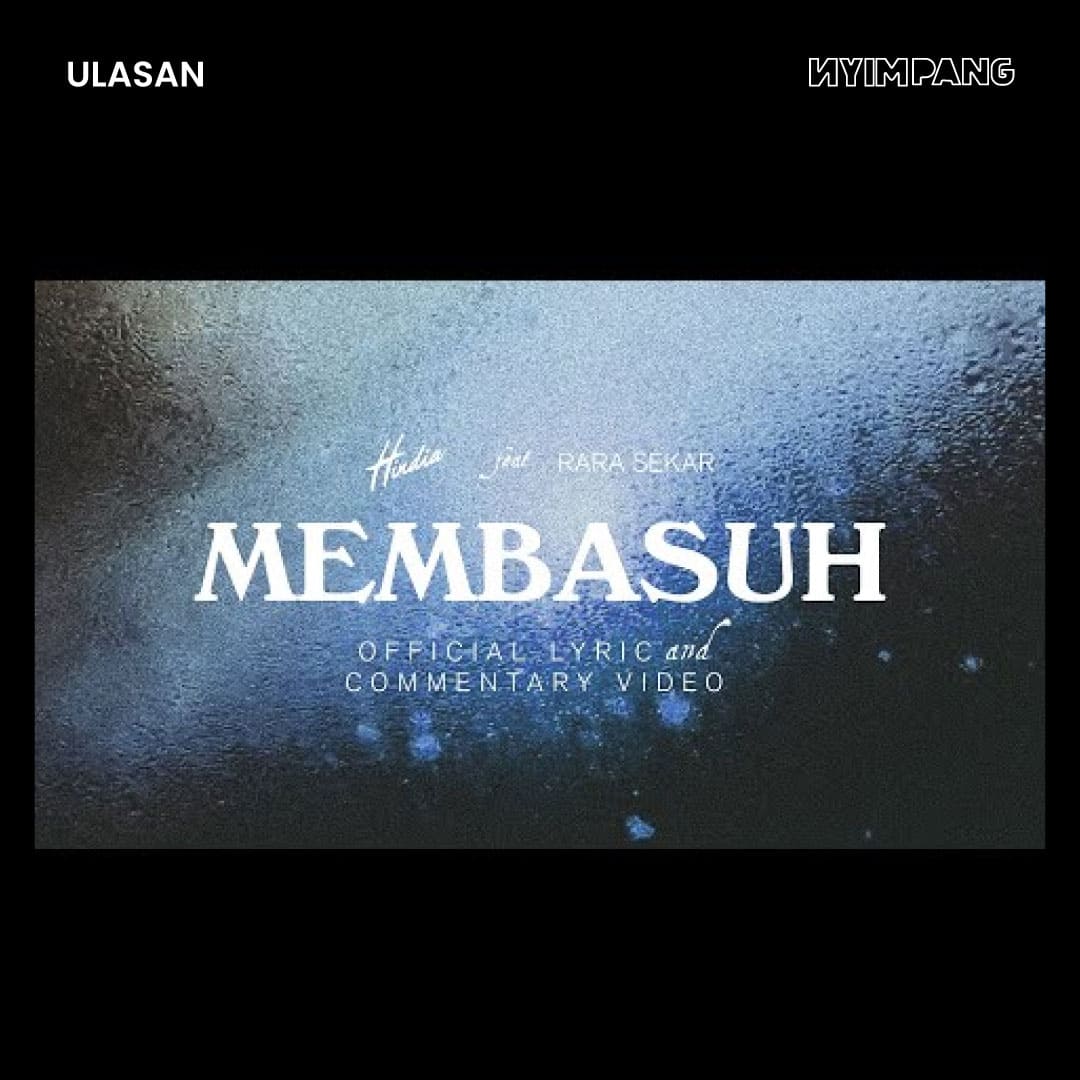
Karhutla, Paraku, dan Trauma Kolektif yang Tak Ditafsir dalam Kabut Berduri (2024)

Kabut Berduri merupakan film garapan Edwin, memiliki judul internasional Borderless Fog. Awalnya, saya kira nama lainnya akan menjadi Thorny Fog atau Spiked Fog, tapi setelah dipikir-pikir lagi, Borderless Fog lebih oke dan lebih representatif juga, kok.
Borderless Fog, yang apabila diterjemahkan adalah kabut tak terbatas, atau sebutlah kabut tanpa batas. Ya, lebih tepat, bukan?
Kabut memang tak perlu cap imigrasi di perbatasan untuk numpang lewat waktu kebakaran hutan dan lahan terjadi. Sebab meminjam kalimat Anies Baswedan di panggung debat Capres 2024,
“Polisi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya.” begitu katanya waktu menjawab Prabowo, sila lihat di sini.
Kabut Berduri rilis di Netflix pada awal Agustus 2024, bersamaan dengan peristiwa kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat. Bahkan pada saat film ini tayang, masyarakat Kalimantan Barat repot betulan karena asap.


Selain isu Karhutla, film ini diiringi oleh berita mangkraknya Ibu Kota Nusantara di timur Kalimantan, juga kepercayaan kepada institusi pemerintah dan circle orang-orang dengan senjata (baca: ABRI) yang terus terdegradasi dengan kasus yang terungkap ke publik melalui media sosial.
Meskipun film ini dibuat jauh sebelum Fadli Zon menggaungkan proyek amnesia nasional melalui penulisan ulang Sejarah Indonesia, tapi saya tak melihat alasan selain isu Paraku hanya dibuat sebagai embel-embel saja dalam premis film ini.
Bukannya menghadirkan refleksi historis yang menggugah, rasanya film ini justru menampilkan Paraku sebagai aksesoris naratif yang kehilangan konteks. Entah, rasanya seperti trauma yang terjadi di Kalimantan hanya cukup ditandai tanpa niat untuk menafsirkan ulang kejadian sesungguhnya. Edwin memang berani memasukkan kalimat yang kontroversial itu meskipun tetap saja, kalimat yang juntrungannya masih belum jelas itu agaknya masih kurang (setidaknya buat saya).
Alih-alih menambah kesadaran penonton dalam upaya memahami
“Apa Paraku/PGRS itu?” atau,
“Memangnya apa yang terjadi di Kalimantan?”
Narasi tempelan semacam premis itu justru terasa menambah runyam daftar panjang masalah penulisan sejarah ini. Meskipun segenap tim Kabut Berduri tentu tak usah merasa bertanggung jawab sebab mereka tak perlu hadir sebagai “film pembawa kebenaran” juga, tapi dengan panjangnya daftar dosa pada tikungan sejarah yang selalu menemui jalan buntu, patutkah premis itu dipertahankan tanpa memberikan alternatif lain membentuk karakter anti-hero penyebab pembunuhan berantai di perbatasan? Saya rasa tidak.
Malahan, film ini terasa seperti kisah Bruyce Wayne mengejar Joker yang hanya dijadikan sumber atau “karakter” gaib yang berada di luar pengetahuan kita, ya seperti belantara yang ditutupi kabut memang.
Premis itu dimunculkan dengan latar hutan Kalimantan: rumah bagi suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Diiringi dengan audio senandung lagu Potong Bebek Angsa, yang menjadi ornamen penambah suasana seram dan menjadi tanda pembuka “potong-memotong”.
Kemudian melaui teknik kamera frog eye, sebuah pohon sawit tua menjulang tinggi dengan akar menjuntai seperti rambut atau tanduk. Besar dan berkuasa atas apa-apa yang ada di hutan yang asing dan tak pernah kita kenali. Membuat penonton berada pada irisan “ketidaktahuan”.
Ketidaktahuan pada akhirnya memunculkan wacana lain berlapis dalam film ini. Ketidaktahuan itu muncul sebagai sosok Ambong, seorang tokoh yang alkisah merupakan komunis, sebuah entitas marjinal pada saat itu, yang kabur ke hutan pada masa pemberontakan. Singkatnya, Ambong bisa kita baca sebagai wujud trauma kolektif masyarakat yang dalam realitas film ini hadir sebagai postmemory.
Peristiwa pemberontakan sampai pasca pemberontakan 1965 yang mengakibatkan cerita Ambong beredar itu memang tidak dijalani secara langsung oleh generasi anak-anak dan remaja perempuan korban perdagangan manusia itu, namun cerita dan perilaku yang diwariskan generasi sebelumnya muncul dalam keyakinan sebagai penjaga masyarakat Kalimantan. Karakter fiktif Ambong, mewakili tragedi yang mungkin lukanya tak kering-kering, dan justru hadir dalam ingatan yang kabur dan bercampur kabut.
“Ambong itu hantu komunis.” Pak Bujang kepada Sanja (9:57)
“Aman, Kak. Ambong melindungi.” Sindai kepada Sanja (21:04)
Pada satu generasi yang diwakili Pak Bujang. Ambong merupakan sosok hantu komunis. Muncul dalam gelapnya sejarah dan membawa kesan yang cenderung menakutkan. Ya, rasanya familiar sekali seperti waktu pemerintah Indonesia melanggengkan ketakutan terhadap komunisme. Namun pada generasi yang lain, Ambong menjelma sebagai pelindung, tak lagi menyeramkan, tapi fakta dan keberadaannya masih tersembunyi. Maka seperti hantu-hantu lainnya, Ambong bukan hanya menakuti saja, tapi menuntut agar kita mengingatnya dalam gelap. Entah sebagai hantu, entah sebagai pelindung. Atau bisa saja keduanya.
Culture Shock ala-ala Thomas dan Sanja
Film lalu dibuka dengan aktivitas pagi hari masyarakat perbatasan di dalam hutan. Orang-orang dengan kegiatannya mengangkut kayu, masyarakat biasa yang hendak berkebun, pergi di sebuah warung kopi yang melakukan transaksi dengan dua mata uang: rupiah dan ringgit.
Seisi warung oldschool yang diduduki masyarakat medioker pun dikejutkan dengan adegan mayat yang jatuh dari balik asbes. Mayat dengan tubuh yang terpisah dan kepala buntung menggelinding.
Adegan kepala buntung ini mengingatkan saya pada scene dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul, atau Si Manis Jembatan Ancol. Namun jika keduanya kelewat jenaka untuk dibandingkan dengan film seserius ini, maka mari saya sebut saja film Hereditary, atau Breaking Dawn 2.
Usut punya usut, mayat yang tubuh dan kepalanya terpisah itu berasal dari tubuh dan kepala orang yang berbeda. Sambungan mayat ini merupakan tubuh dari 2 orang yang hilang sebelumnya: Juwing, aktivis putra daerah yang rajin menyuarakan isu perdagangan manusia dan Thoriq, sang tentara nyambi pembunuh bayaran. Kemudian Sanja (diperankan oleh Putri Marino), tampil sebagai penyidik DKI yang ditugaskan menuntaskan kasus ini.

Secara terstruktur, Pulau Jawa telah lama menjadi pusat, dan arti nama Sanja sendiri dalam Bahasa Jawa berarti “silaturahmi” atau “kunjungan”. Dari Ibu Kota, pusat segala ekonomi dan perputaran uang, berkunjung mampir ke Perbatasan, tempat segalanya tak terlihat dan digelapi kabut.
Sanja, yang datang dengan sikap berlagak selalu mengikuti SOP akhirnya sadar bahwa di lapangan, tidak semua bisa diselesaikan dengan cara “pusat”.
Agaknya Sanja harus memahami betul peribahasa
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”
Sebab barang tentu Sanja mengalami culture shock seperti yang dikatakan Kalervo Oberg melalui (cari tau) bahwa kondisi Sanja menggambarkan kondisi seseorang merasakan sebuah kecemasan yang diakibatkan oleh kehilangan suatu tanda-tanda dan simbol-simbol yang familiar dalam pergaulannya sehari-hari.
Dalam menyelesaikan kasus ini, Sanja berada di bawah komando Panca, kepala kepolisian setempat. Sanja juga didampingi Thomas, putra Dayak yang menjadi olok-olokan dua kubu.
“Aku sampe tutupin tato supaya bisa diterima. Di polisi dibilang dasar orang Dayak, di orang Dayak dibilang dasar polisi. Nasib … nasib.” Thomas kepada Sanja, (65:28)
Thomas, sebagai putra Dayak yang menjalani profesi sebagai polisi justru merasa bahwa dirinya tidak diterima di dua kubu itu. Ia merasa identitasnya saat ini, merupakan hasil kawin ketegangan identitas yang berlapis: antara Dayak dan polisi, masyarakat adat dan otoritas negara, pun pusat dan pinggiran.
Ungkapan Thomas kepada Sanja merupakan ambiguitas identitas yang dikatakan Bhabha sebagai posisi in between, dan sah-sah saja apabila Thomas merasa seperti itu. Tidak sepenuhnya diterima oleh institusi negara karena dianggap kriminal dan/atau primitif, namun juga kehilangan tempat dalam kemunitas asalnya karena dianggap berkhianat. Inilah ruang transisi yang disebut Bhabha sebagai ruang enuansi ketiga, ruang yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh satu kekuatan, tapi justru menghasilkan makna baru dan potensi subversif dari hal itu.
Jelas saja, melalui serangkaian pergolakan yang terjadi, perpecahan ideologi-profesi, Thomas menjadi sasaran empuk bahan ejekan dua kelompok yang beririsan itu.
Adalah Yoga Pratama, pemeran Thomas yang sepertinya melakukan reuni dengan Nicholas Saputra di Kabut Berduri setelah keduanya lulus dari pesantren dalam 3 Doa 3 Cinta (Nurman Hakim, 2008) dan membawanya mendapatkan penghargaan pemeran pendukung pria terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun yang sama.
Dialog Yoga kepada Sanja pun merupakan hasil tak terhindarkan dari serangkaian tragedi di Kalimantan Barat yang berlangsung sejak lama. Seperti yang dikatakan Dr. Xu Yao Feng, Lembaga Peneliti Asia Tenggara
“Kalimantan Barat pada dekade 60-an abad ke-20 merupakan masa pergolakan. Oleh karena bagian provinsi Indonesia ini berbatasan dengan Serawak yang pada masa itu adalah wilayah colonial Inggris, pada tahun 1963 menjadi titik fokus dan daerah utama dalam politik konfrontasi terhadap terbentuknya negara Malaysia.” (Fang, 2022: 13)
Sebab apabila membaca ulang Can the Subaltern Speak oleh Gayatri Spivak, sudah semestinya kita menahan diri dari representasi semu yang berkabut seperti judul filmnya. Spivak secara tajam mengingatkan bahwa subaltern tidak serta-merta dapat berbicara, atau sebut saja tidak dapat didengar sebab memang tidak semudah itu, Ferguso!
Bayang-Bayang Sejarah dan Seksisme Struktural
Jika diamati lebih teliti, tokoh-tokoh perempuan dalam Kabut Berduri selain Sanja yang merupakan tokoh sentral dari awal penciptaannya tidak pernah benar-benar menjadi agen dalam narasi yang terbubuh dalam film ini. Perempuan-perempuan itu bukan pelaku dan penggerak. Mereka adalah subjek yang menerima perlakuan dan digerakkan.
Lihat saja segerombolan anak-anak yang menjadi korban jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan oleh Umi, seorang perempuan yang pada gilirannya hanya berperan sebagai broker dalam sistem hierarki yang lebih besar dan dikepalai oleh Agam, diawasi oleh Panca. Dua figur laki-laki yang menempati posisi strategis dalam negara dan hukum, dan Agam dalam kasus ini menempati posisi tersebut karena punya banyak cuan dari bisnis sampingan untuk menutup tindak-tanduk kriminalnya dengan menyuap Panca.
Dalam logika Spivak yang muncul dalam esainya, Can the Subaltern Speak? (1998), Umi tentu bukan perwakilan perempuan subaltern, Umi adalah ikon perpanjangan tangan dari kekuasaan hegemonik yang sudah ada dan mengakar di tanah yang hampir tak pernah dipedulikan itu.
Bahkan dalam pengungkapan pelaku pembunuh berantai yang baru diungkap di 10 menit terakhir filmnya, narasi dalam cerita ini masih menjadi arena dominasi laki-laki. Sanja, si polisi titipan “Bapak” hanya hadir sebagai representasi perempuan dalam jejak penyelidikan. Sisanya? tetap menjelma tubuh yang marjinal dan tidak terdengar.
Katakanlah Sanja memang bisa berbicara dan sedikitnya berjalan mengungkap kebenaran, tapi tentu saja hal itu dikarenakan ia datang dari Jakarta, “pusat perputaran uang dan peradaban” lengkap dengan lencana yang membuat Sanja bisa masuk ke ruang yang dikunci rapat untuk perempuan lain.
Meskipun begitu, patutlah kita apresiasi Edwin untuk tetap memunculkan kesadaran dan kritik sosialnya terhadap nada-nada seksis sesumbang Panca yang mengatakan,
“Kamu percaya sama kesaksian ABG perempuan yang lagi kebingungan itu?” (8:43)
“Kacamatanya bagus. Cocok buat Borneo Fashion Week.” (3:33)
Dua dialog tadi cukup menjadi alat reflektif dalam memahami bahwa seksisme sudah bekerja secara mikro: menjelma kata, dibungkus sinisme, dan berakhir sebagai penilaian Panca, Inspektur Polisi Dua berjenis kelamin laki-laki.
Panca, dengan segala perasaan dan arogansinya menganggap bahwa perempuan tidak dapat dianggap sebagai saksi yang kredibel. Melalui kalimat meremahkan, Panca tentu saja menihilkan validitas suara perempuan muda, yang seringkali dianggap belum “pantas” untuk berbicara secara sosial.
Kalimat seksis selanjutnya dilontarkan Panca kepada Sanja yang, alih-alih berbicara soal kapasitas individu dalam situasi serius di depan jenazah, Panca malah mengomentari penampilan Sanja.
Mempolitisasi fashion sebagai ranah “perempuan” yang tentu saja menunjukkan secara gamblang stereotip dan peran gender tradisional. Bahwa perempuan tidak sanggup bekerja, dan alih-alih bekerja, perempuan lebih senang berdandan. Bukti yang cukup menunjukkan karakter Panca lahir di masa yang purba, bukan?
Kesimpulan
Isu yang dibawa film ini tidak sedikit, cenderung berjejal begitu saja. Mengangkat karhutla, perampasan ruang hidup, sejarah Paraku, dislokasi identitas, hingga seksisme yang agaknya membuat film ini mudah membuat lelah, terlebih dengan durasi yang cukup panjang.
Semua berjejal dalam satu narasi yang bergerak lambat dan atmosferik. Akibatnya, film ini rentan tergelincir menjadi representasi yang kabur, persis seperti kabut yang ditampilkan. Banyak hal dipaparkan, namun tak semuanya ditafsirkan secara rinci dan mendalam.
Namun justru itu dia: ambiguitas film ini menjadi menarik. Kabut Berduri mungkin tak menawarkan pembacaan sejarah yang utuh atau kebenaran tunggal atas trauma kolektif di perbatasan Kalimantan. Tapi setidaknya, Kabut Berduri berhasil memvisualkan nuansa ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa di banyak tempat di negeri ini, sejarah memang hadir dalam bentuk samar dengan segala gangguan dan kabut-kabut yang memburamkannya.
Mise en scène yang remang, shot yang dalam dan gelap, serta teknik sinematografi yang menekankan ruang-ruang tersembunyi membikin film ini menjadi ruang tafsir yang membuka peluang diskusi yang subur.
Kabut Berduri tetap menjadi film yang patut disoraki “Anjay!” sebagai usaha menghadirkan kekacauan sejarah, trauma ekologis, dan kekerasan struktural dalam satu lapisan kabut yang random dan tak langsung memberi jawaban, tapi setidaknya mengajak kita melihat kembali yang selama ini luput dan tak banyak didengar khalayak.