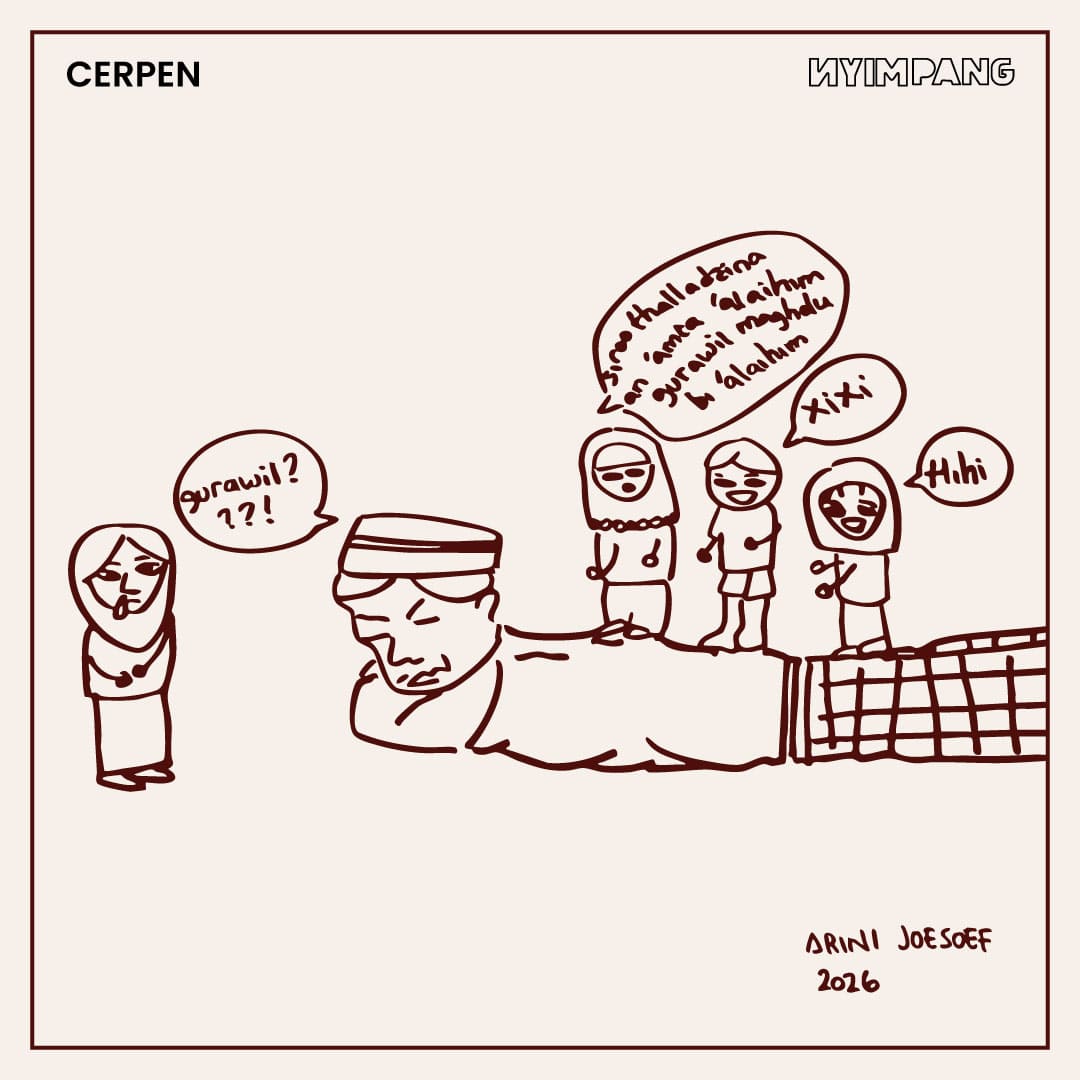
Hikayat Situ Buleud

Barangkali bagi kebayakan orang, Situ Buleud dikenal tak lebih dari sekedar tempat pangguyangan badak. Menurut para sesepuh, riwayatnya jauh lebih kelam daripada cerita yang lazim didengar. Mereka berkata, pondasinya dibuat dari pengorbanan pribumi dan darah kompeni. Asal tahu saja, sebelum kisah ini ramai dituturkan, nama Raden Aditia Aria Gandawaluya (Dalem Pangestu), dikenang sebagai sosok yang dituding menggadaikan harga dirinya ke tangan Walanda, sehingga membuat alam murka membabi buta. Konon, sebuah kutukan dibawa oleh garis darahnya sepanjang hayat. Kutukan yang lebih seperti penebusan rasa bersalah, ketimbang sebuah dendam kesumat.
Asal muasal kisahnya bermula tatkala Karesidenan Walanda di Distrik Wanayasa menerima besluit dari Gubernur Jendral Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Batavia. Berisi titah langsung dari Jan Pieterszoon Coen untuk segera ngababad leweung di Distrik Sindangkasih dan segera memindahkan Karesidenan ke tanah itu. Tujuannya adalah membuka jalur perdagangan baru untuk rempah-rempah yang dibawa dari Batavia menuju ke jantung Priangan.
Namun, janganlah pembaca mengira bilamana ngababad leweung di Distrik Sindangkasih merupakan urusan remeh-temeh. Tempo dulu, wilayah itu dihuni oleh Gerombolan Cina Makao. Kelompok yang kesohor sebagai bajing luncat dan sering melakukan aksi penggarongan di sana. Walanda pun mafhum, mereka tak akan berani melakukan konfrontasi secara terang-terangan. Salah langkah sedikit saja, amarah pribumi bisa langsung tersulut. Lagi pula, perang terbuka hampir selalu bikin mereka nyaris bangkrut. Sebagaimana pernah terjadi di Diponegoro pada tahun-tahun silam.
Pemimpin Gerombolan Cina Makao dikenal dengan panggilan Anton Hao. Kepalanya dipatok imbalan seratus gulden oleh para menak, yang iring-iringan pedati hasil panennya kerap diusik oleh Gerombolan Cina Makao. Sebuah harga yang sebenarnya tergolong menggiurkan pada masa itu. Namun pada hakikatnya, tak pernah benar-benar sebanding dengan resiko yang akan dihadapi jika berurusan dengan manusia seperti Anton Hao.
Pendek cerita, Karesidenan Walanda menempuh perjalanan selama dua kali matahari terbit dari Distrik Wanayasa menuju Distrik Simpereum, untuk menggelar perundingan dengan R.A.A Gandawaluya. Adapun Residen Gustaaf van Riemsdijk punya niat tersembunyi untuk menjadikan nama Gandawaluya sebagai tameng, guna meredam pengaruh Anton Hao di Sindangkasih. Setelah gagal mencapai mufakat dengan ulama besar Distrik Gandasoli, yaitu Kyai Ajengan Arya Dipa, yang tiada sudi membungkuk di hadapan kompeni.
Dalam benak Arya Dipa, bersekutu dengan kaum penjajah bukanlah jalan yang diridhoi oleh sesembahan-Nya. Ia juga tidak ingin menggadaikan keselamatan santrinya hanya untuk cari masalah dengan Gerombolan Cina Makao. Lagipula, Arya Dipa punya rencana lain di Sindangkasih. Ia tengah mengikhtiarkan pendirian tempat ibadah sekaligus pusat persinggahan santrinya yang bermusafir ke wilayah itu. Alhasil, kesepakatan yang ditawarkan oleh Walanda ditolak mentah-mentah tanpa sisa.
Maka tiada mengherankan apabila Riemsdijk akhirnya berpaling muka pada Gandawaluya setelah penolakan dari Arya Dipa. Patutlah kiranya pembaca mengetahui, bahwa nama R.A.A Gandawaluya telah lama masyhur sebagai Wedana Simpereum. Ia disegani bukan semata karena kedudukannya, melainkan karena pengaruhnya sudah menjalar ke urat nadi tanah itu. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Simpereum hidup makmur dan mandiri, nyaris tanpa campur tangan Walanda. Gandawaluya bahkan berhasil membangun sebuah waduk besar yang airnya mengalir melalui tujuh solokan gede menuju sawah-sawah lega yang menjadi sandaran penghidupan rakyatnya.
Jabatan Dalem ditawarkan kepada Gandawaluya sebagai bagian untuk melancarkan kesepakatan. Meski demikian, bukanlah rahasia lagi, bahwa kedudukan Dalem di Karesidenan tak lebih dari formalitas belaka. Memang benar adanya, bahwa Dalem merupakan jabatan tertinggi yang dapat disandang oleh kaum pribumi di tanah Priangan. Namun, kekuasaan sejati tetap berada di bawah kendali Walanda melalui Residen mereka. Alias, Dalem acap kali hanya diposisikan sekedar jadi boneka Walanda saja.
Tapi sungguhlah malang nian, kedatangan Riemsdijk ke Simpereum pun tidak serta-merta berbuah kelancaran. Upaya cuci tangan Walanda dengan mencoba mengadu domba sesama pribumi terancam kandas lagi. Alangkah tercengangnya Riemsdijk saat Gandawaluya mematok harga yang teramat mahal untuk kesediaannya membantu Walanda. Gandawaluya hanya mau membersihkan Distrik Sindangkasih dari cengkeraman Anton Hao, asalkan Distrik Wanayasa dibebaskan dari cultuurstelsel. Suatu permintaan yang terdengar lancang bagi telinga Walanda, dan teramat berani dilontarkan seorang pribumi. Permintaan itu sampai membuat utusan Karesidenan yang ikut berunding memasang raut gusar, karena merasa kehormatan mereka dipermainkan.
“Sederhana saja Meneer, biarlah hak lahan dikembalikan pada para petani Wanayasa.” Gandawaluya meminta dengan tegas.
Riemsdijk terdiam melongo mendengarnya. Lalu, entahlah sebab apa, ia malah tertawa keras. “HA-HA-HA!” Suara tawanya terasa ganjil, apalagi ketika hidungnya tiba-tiba menyemburkan bubuk teh dari cangkir yang baru saja ia seruput. “Kau memang persis seperti yang dielu-elukan rakyatmu, Tuan Gandawaluya.” kata Riemsdijk, penuh kecanggungan.
Perundingan pun berjalan cukup alot. Akibatnya, rombongan Walanda terpaksa menginap beberapa malam di Simpereum, sambil menunggu timbang-tara dari kedua belah pihak. Hingga tiba di batas waktu, Riemsdijk pun mengalah. Ia akhirnya setuju membebaskan Distrik Wanayasa dari belenggu tanam paksa. Bukan semata-mata karena ogah pulang dengan tangan kosong. Tapi, jika mandat dari Gubernur Jendral tertunda lebih lama, maka reputasinya di Priangan-lah yang dipertaruhkan.
Tak berselang lama selepas kesepakatan tercapai, proyek ngababad leweung pun mendapat restu dari Gandawaluya. Sejatinya, tiada seorang pun yang pernah benar-benar melihat bagaimana komplotan Anton Hao diringkus. Akan tetapi, setelah setiap sudut wilayah itu disisir oleh orang-orang Gandawaluya, kabar penggarongan pun mendadak sirna. Pembukaan jalur pun berjalan dengan lancar. Pedati-pedati melintas dengan aman. Dan, Gerombolan Cina Makao tiada terdengar lagi gaungnya di Sindangkasih.
Hingga suatu hari pada mangsa desta, Gandawaluya berhasil membawa Anton Hao di hadapan banyak mata, seorang diri, dan tanpa hiruk-pikuk perlawanan sama sekali. Anton Hao dituntun menuju sebuah lapangan buleud, kedua tangannya terikat, dan matanya ditutup kain hitam. Lapangan yang diniatkan menjadi tempat peletakan batu pertama, bakal tapak berdirinya pondasi Karesidenan baru.
Para menak menyaksikan penangkapan Anton Hao sambil menyunggingkan senyum merekah, senyum yang membuat ujung kumis-kumis tebal mereka mencuat ke atas. Bersoraklah mereka dengan girang, mendesak agar Anton Hao segera diadili. Bagi kalangan bangsawan, peristiwa penangkapan Anton Hao lebih seperti kemerdekaan yang datang terlalu dini. Adapun rakyat kecil hanyalah bisa terdiam di pinggir lapangan dengan wajah tertunduk pilu. Di mata mereka, Gandawaluya tak lebih dari sosok yang rela menggadaikan harga diri, demi bisa duduk manis di Karesidenan.
Riemsdijk berjalan memecah kerumunan, sepatu botnya bergantian menghantam tanah berulang kali. Ia berhenti tepat di hadapan Anton Hao yang bertekuk lutut di tengah lapangan. Perlahan-lahan dibukanya gulungan kertas yang ia bawa. Lalu, dibacakannya hukuman untuk Anton Hao dengan bahasa pribumi yang masih terpatah-patah dan tak sepenuhnya beraturan.
“Kejahatanmu tidak tertolong Tuan Hao. Demi nama rakyat yang menetap maupun sekedar singgah di tanah Priangan, hukuman bagimu adalah digantung hidup-hidup, dan jasadmu akan dihanyutkan ke aliran Sungai Citarum,” Riemsdijk menghentikan kata-katanya sejenak, untuk menaikan kacamatanya yang merosot di pangkal hidungnya. “Namun demikian, sebagai tanda belas kasih, sebelum ajalmu tiba, engkau diperkenankan mengajukan satu permintaan terakhir.”
“Badak, Meneer…” Kata Anton Hao dengan senyum menyeringai hingga memperlihatkan bekas codet di permukaan bibirnya. “Sebelum titah eksekusi itu dijalankan, perkenankanlah hamba bertarung dengan seekor badak dari Ujung Kulon. Biarlah sisa nafas ini dihabiskan dengan layak, daripada leher hamba hanya diserahkan cuma-cuma pada seutas tali.”
Kerumunan pun terdiam sejenak. Riemsdijk terheran bukan kepalang. Ia dapat memastikan sendiri bahwa nyata kiranya Anton Hao memang sinting bin miring akalnya, persis seperti selentingan yang beredar. Bahkan hukuman gantung pun terasa kehilangan marwahnya di hadapan kegilaan manusia yang memilih bertarung dengan badak di sisa hidupnya.
“Biarlah saya sendiri yang mengirimkan surat kepada Panembahan Singaperbangsa II, Meneer,” ujar Gandawaluya menyela dengan sigap, seakan tiada memberi ruang bagi Riemsdijk guna menimbang lebih jauh permintaan Anton Hao. “Beliaulah yang kelak menyampaikan titah itu ke Sultan Agung Banten, agar seekor badak didatangkan ke Sindangkasih.”
Riemsdijk hanya bisa mengangguk. Bibirnya masih kelu, pikirannya tersendat oleh permintaan yang sukar dicerna akal sehat.
“Sampaikan pula kabar ini ke segenap tokoh Walanda di bumi Priangan. Mereka akan senang,” lanjut Gandawaluya dengan senyum seakan ada maksud yang tak terucap. “Patoklah harga tinggi bagi pribumi yang hendak menonton. Biarlah Ini jadi pertunjukan besar untuk Karesidenan, Meener.”
Singkatlah kisah, seekor badak bercula satu dari Sultan Agung Banten pun sampai ke Sindangkasih, melalui perantara Panembahan Singaperbangsa II. Para pejabat tinggi, perwira, dan segala tokoh terkemuka Walanda di tanah Priangan pun berhimpun. Mereka datang oleh rasa penasaran yang terlampau besar. Sebab belum pernah terbayang sebelumnya, apalagi di negeri asal mereka, sebuah pertarungan hidup-mati antara manusia melawan badak.
Aneh tapi nyata adanya, sejauh mata memandang, hari itu tiada seorang pun pribumi tampak di tengah kerumunan. Rakyat pribumi memilih menjauh, tak hanya sekedar karena harus membayar mahal untuk menontonnya, melainkan pula karena tak sampai hati untuk menyaksikan sesama pribumi diadu dengan seekor hewan sebagai bahan tontonan.
Gandawaluya kembali menuntun Anton Hao menuju lapangan, menapaki tanah yang terasa lebih basah daripada hari-hari sebelumnya. Dari kejauhan tampak bahwa Gandawaluya membungkuk sedikit, seakan membisikkan sesuatu ke telinga Anton Hao. Namun Riemsdijk tiadalah menaruh curiga. Dalam sangkanya, barangkali itu hanyalah sumpah-serapah terakhir bagi seorang yang hendak diserahkan kepada maut. Lagi pula, andai kata keajaiban berpihak dan Anton Hao luput dari ajal melawan badak, baginya tetap tiada jalan pulang. Hukuman gantung telah menanti, dan ajal hanya tinggal memilih waktu.
Maka, dilepaskanlah Anton Hao dari segala ikatannya. Demikian halnya dengan sang badak yang dikeluarkan dari kerangkeng besi tempat ia ditahan. Begitu terlepas, badak itu segera berlari tak tentu arah, culanya menghujam tanah, menggusur bumi seakan hendak mengorek sesuatu di dalamnya. Sementara itu Anton Hao tetap berdiri tegak, melangkah menyamping dengan hati-hati, matanya tak lepas mengawasi kemana sang badak akan mengarah.
Badak itu mendadak berbelok, berlarilah ia mendekati Anton Hao dengan dengusan yang memburu. Anton Hao tiada bergeming, meski jarak antara dirinya dan hewan itu tinggal sehasta. Sekejap kemudian, tangan Anton Hao pun disambarnya, bukan untuk mencabik, melainkan menyeretnya, lalu pergi terbirit-birit ke arah kaki Gunung Parang. Sekalian mata masih terbelalak dengan apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, entah sejak kapan, Gandawaluya sudah tak nampak dari tempatnya berdiri. Ia raib begitu saja, tanpa seorang pun menyadarinya.
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah utara. Barang siapa mendengarnya niscaya menyangka hari kiamat telah tiba, sebab bunyinya terdengar seperti langit ditarik turun mendekati tanah. Dari kejauhan, tampaklah samar ombak yang tingginya kira-kira sepuluh depa, datang menggulung semua yang ada di dekatnya.
Tanah lapangan yang semakin basah pun seketika amblas membentuk ceruk buleud yang dalamnya tiada seorang pun bisa menghitung. Orang-orang Walanda yang berada disitu tak sempat menyelamatkan diri dari terjangan ombak dan amblasnya bumi. Mereka terkubur ke dalam ceruk bersamaan dengan lumpur dan air bah yang terus menggenang. Yang mana ceruk berisi air dan segala yang tertinggal di dalamnya itu, kelak kita sebut dengan nama Situ Buleud.
Beberapa hari berselang, barulah diketahui bahwa air bah itu bersumber dari jebolnya tanggul Waduk Simpereum. Namun tiadalah seorang pun mampu menerangkan bagaimana jebolnya terjadi, ataupun sebab-musabab mengapa limpahannya hanya sampai ke Sindangkasih, tanpa menjamah daerah lain di sekitarnya. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Maka, ditariknyalah segala utusan yang masih tersisa dari Karesidenan itu, membiarkan pribumi membereskan kekacauan yang telah mereka buat.
Sejak peristiwa itulah, kuasa Walanda pun lenyap sepenuhnya dari tanah Priangan. Adapun Anton Hao, Gandawaluya, serta badak bercula satu itu turut menghilang bak ditelan bumi. Tiadalah seorang pun mengetahui kemana perginya mereka. Namun demikian, biarlah kepergian mereka tetap menjadi tanda tanya besar, sebab tidak segala yang terjadi di tanah ini diperuntukkan bagi terang cerita.
Supaya pembaca tidak bingung. Sudilah kiranya mendengar kesaksian dari istri Gandawaluya, yakni Purbasari. Sejak kejadian itu, Purbasari meyakini bahwa Gandawaluya masihlah bernyawa. Dalam pandangannya, segala yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan telah dirancang dengan seksama oleh suaminya. Perkara pribumi yang tak datang ke tempat kejadian, barang mungkin merupakan akal-akalan Gandawaluya pula. Namun, tiada yang bisa mengkonfirmasi perihal itu. Menurutnya, Gandawaluya sedari awal memang berniat melenyapkan pengaruh Walanda di Priangan, meski harus mempertaruhkan nama baiknya. Tiada maksud menjadi pengkhianat sebagaimana yang kemudian dipercayai masyarakat.
Keyakinan Purbasari itu didasari suatu alasan. Sebab jauh-jauh hari sebelum kejadian, para ahli nujum kerap datang ke Pendopo Simpereum untuk bertemu Gandawaluya. Bahkan, lebih sering dari biasanya. Purbasari percaya bahwa pengorbanan suaminya bukanlah sebuah kehancuran, tapi permulaan baru dari sebuah rencana yang paripurna dijalankan.
Sedangkan perihal kutukan, tersiar kabar simpang siur di kalangan rakyat Simpereum. Konon, lantaran tiada satu pun saksi dari pihak pribumi yang mengetahui kejadian sesungguhnya, Gandawaluya merasa perlu membersihkan namanya dari salah tafsir di masa depan. Agar kelak keturunan Anton Hao tidak memikul prasangka atas perbuatannya di masa silam, ia pun menjatuhkan kutukan kepada garis keturunannya sendiri yang berbunyi:
“Dari darahku, kelak akan lahir orang-orang yang terus menuliskan kisah yang sebenarnya, dari zaman ke zaman. Dan, entah dengan jalan apa, tulisan itu hanya akan dibaca oleh keturunan Anton Hao dengan hati yang lapang.”





