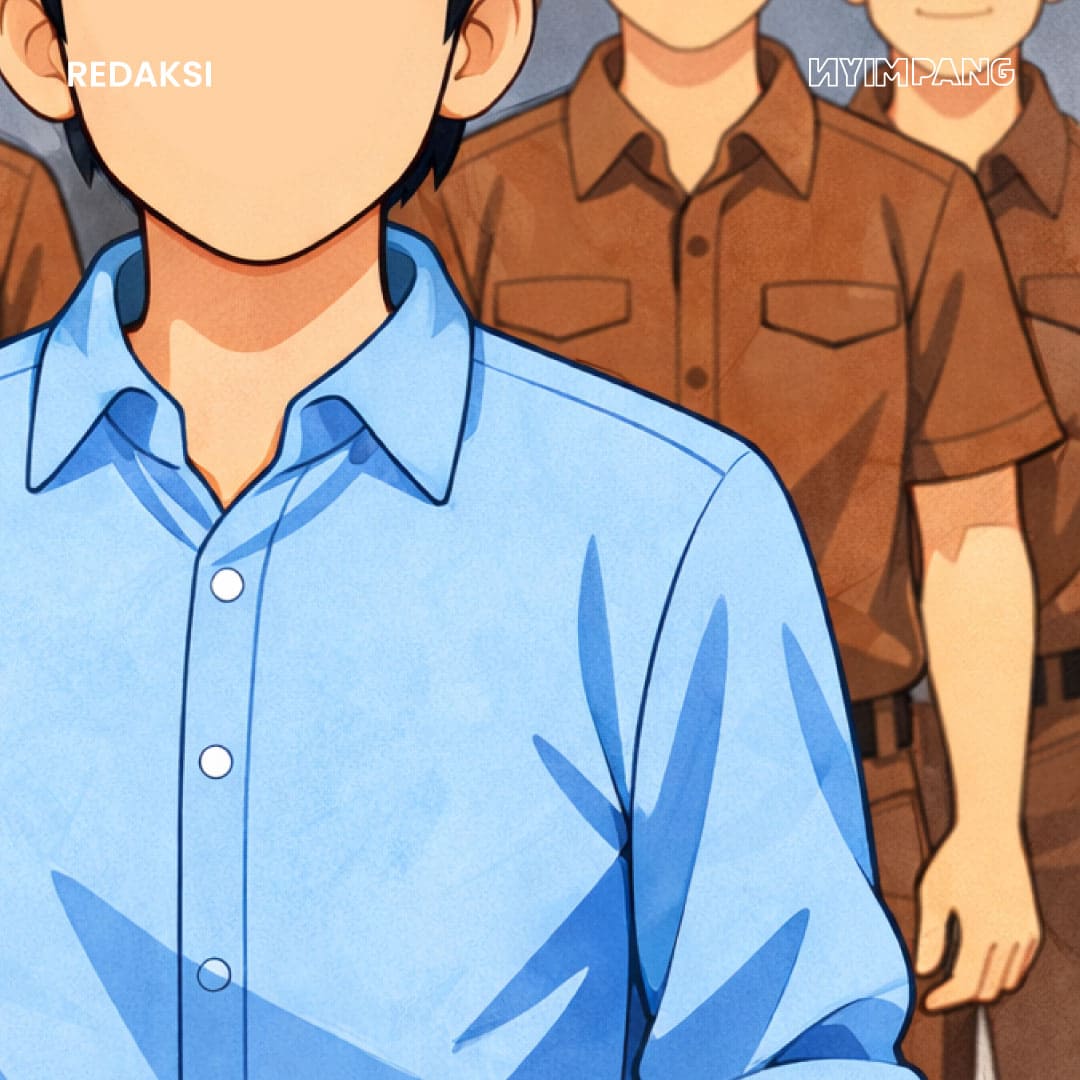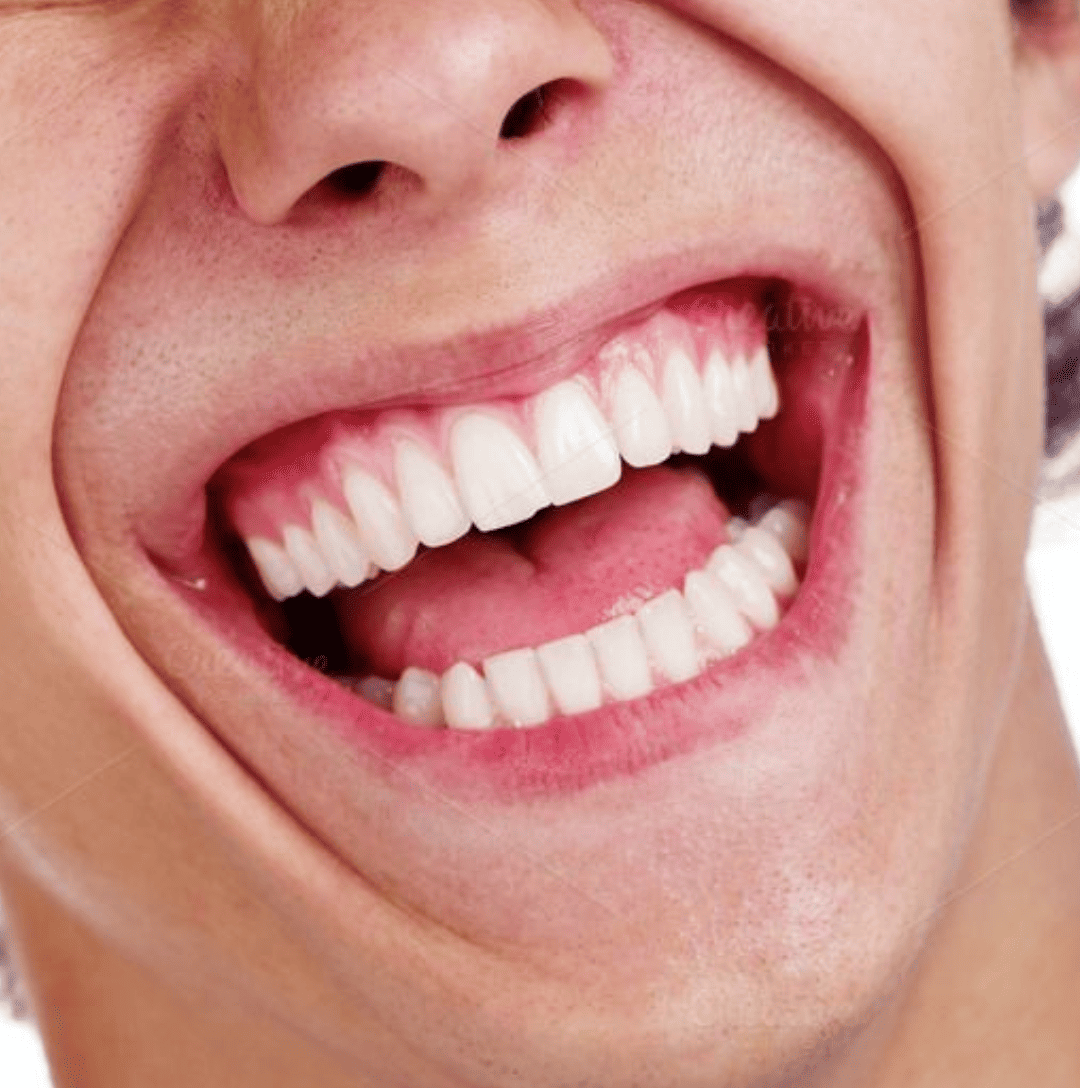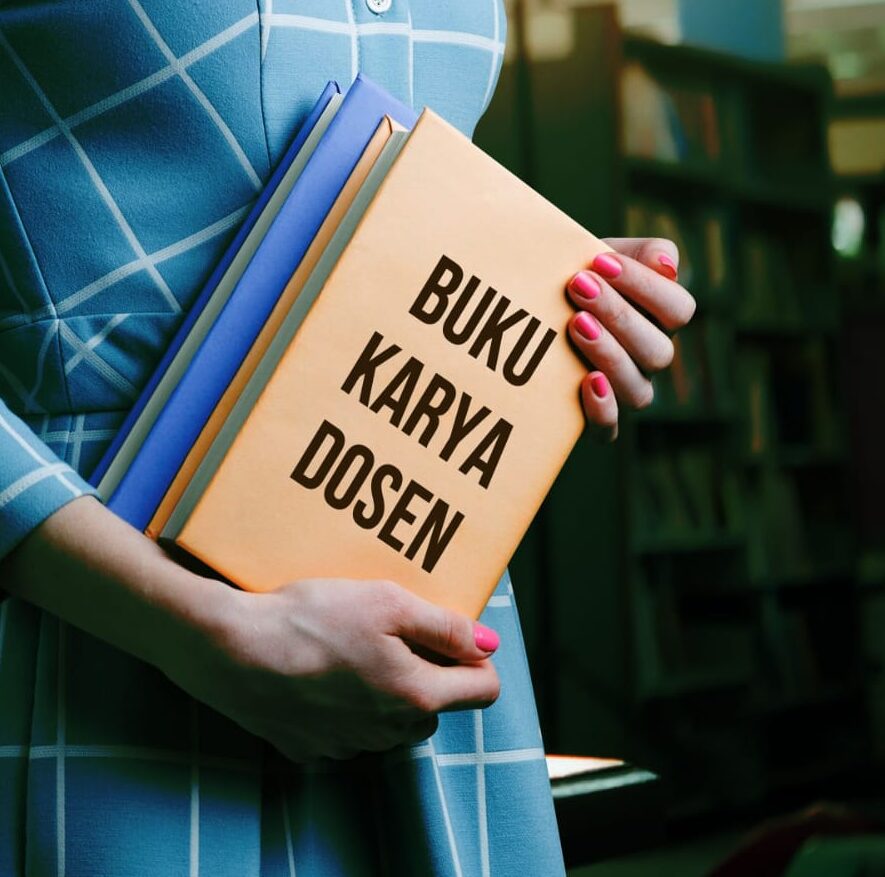
Gedebak-gedebuk Kerja Ordal Pemerintah
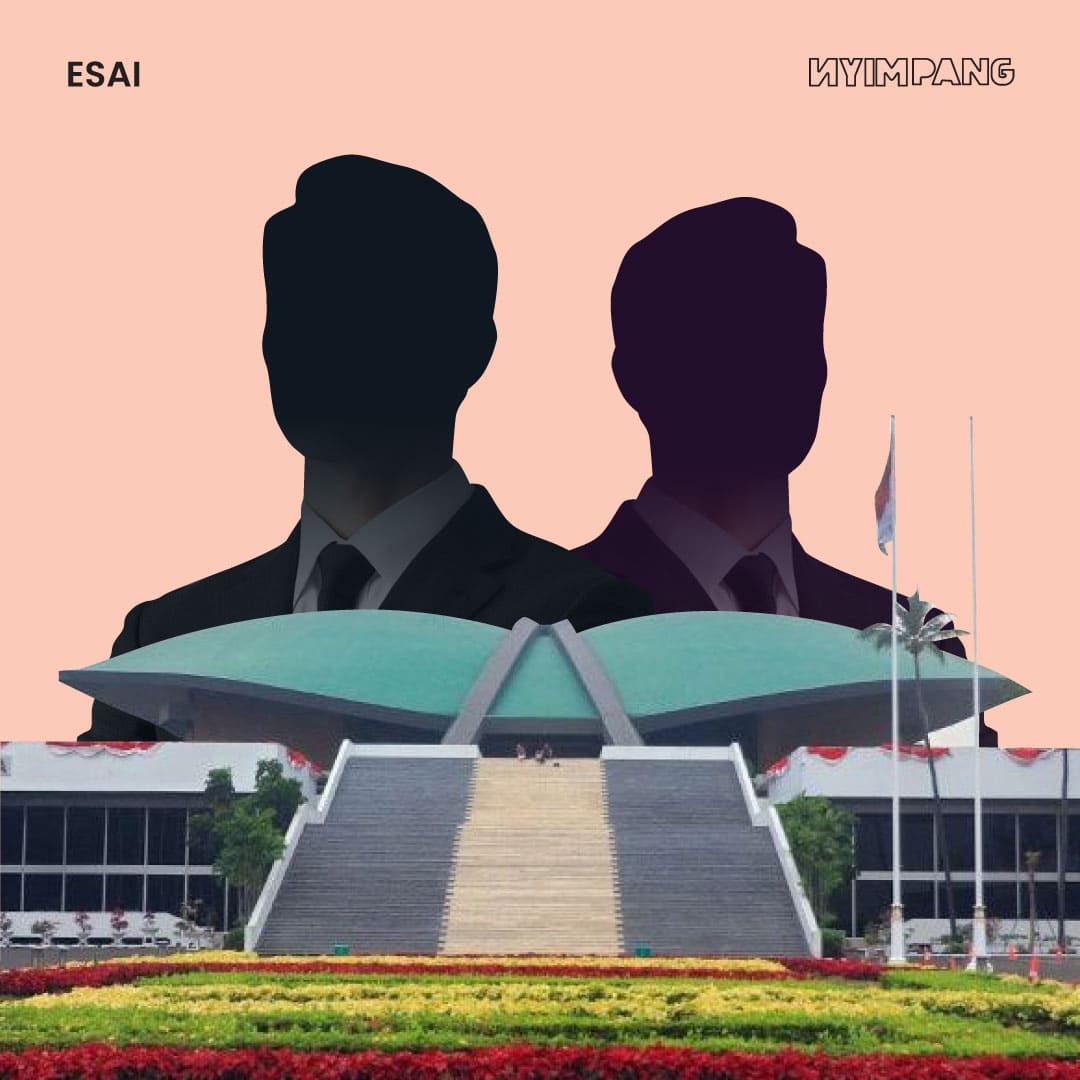
Saya bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang, seperti sudah dimaklumi banyak orang, banyak sekali birokrasinya. Saya ingin bercerita soal betapa lekatnya pekerjaan saya dengan istilah birokrasi, bahkan sudah menjadi ritual wajib yang mustahil dihindari. Buat yang belum paham apa itu birokrasi, birokrasi itu kaya kue lapis yang banyak layernya. Bedanya kue lapis itu bikin kenyang kalo dimakan, sementara birokrasi itu bikin pusing kalau dilalui. Satu waktu saya pernah menjelaskan definisi birokrasi ke anak kecil dengan perumpamaan anak sekolah yang ingin pulang cepet. Ia gak bisa seenaknya keluar kelas dan pulang, tapi harus izin gurunya dulu, telepon mamanya dulu, bilang satpam sekolah dulu, baru boleh pulang. Perumpamaan itu cukup berhasil untuk menyederhanakan realitas birokrasi yang nyatanya gak semudah penjelasan untuk anak-anak. Sebab ada kalanya anak sekolah yang ingin pulang cepet itu gak perlu izin gurunya dulu, gak perlu izin mamahnya dulu, gak perlu bilang satpam dulu, karena ternyata bapaknya adalah kepala sekolah. Ketika semua prosedur bisa dilompati dan diakali, di situlah kompleksitas birokrasi sering dimulai.
Dalam keseharian saya mengelola media sosial instansi, salah satu contoh birokrasi yang erat saya alami adalah ketika saya hendak mengunggah foto kegiatan kantor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta persetujuan isi kontennya ke bos divisi, lalu bos saya akan minta persetujuan ke bos di atasnya. Kalau bosnya bos saya masih punya bos, ia akan minta persetujuannya juga. Lapisan-lapisan persetujuan ini akan terus naik ke atas, tergantung seberapa penting acara atau kegiatan yang dilaksanakan. Mengunggah satu foto aja kadang kayak perjalanan naik tangga yang panjang, berliku, dan kadang kita nggak tahu tangga itu sebenarnya menuju lantai berapa. Lebih ribet lagi kalau foto kegiatannya melibatkan kantor dan instansi yang berbeda-beda. Bisa jadi acaranya hari ini, posting foto kegiatannya baru bisa minggu depan karena proses persetujuan dari semua pihak tidak selalu berjalan mulus. Makanya gak heran kalau berita resmi dari pemerintah akan selalu kalah cepat dari berita wartawan atau netizen, karena proses birokrasi yang panjang dan berliku.
Pernah satu waktu ada proyek besar yang melibatkan puluhan lembaga dan korporasi, dan saya harus membuat grafis untuk flyer dan konten media sosial. Logo dari semua lembaga itu harus ada di grafis yang saya buat, dan bisa dibayangkan betapa panjangnya perjalanan yang harus saya lalui untuk menunggu persetujuan dari semua pihak. Proses untuk menentukan logo mana yang harus berada di pojok atas kanan flyer, siapa yang harus di atas kiri, logo mana yang ukurannya lebih besar, siapa yang paling kecil, adalah proses yang panjang dan tidak selesai dalam hitungan minggu. Birokrasi yang panjang dan berliku ini benar-benar membuat desainer grafis pusing dan mual karena revisi.
Tapi dalam beberapa hal lain, saya mengalami proses birokrasi yang relatif singkat. Misalnya ketika saya mau posting konten ucapan “Selamat Hari Batik”, “Selamat Hari Buruh”, atau “Pengumuman Kantor Tutup”, biasanya cukup bos saya aja yang menyetujui, lalu saya bisa posting. Tapi kalau peringatan Hari Batik, Hari Buruh, atau hari apalah itu yang diwujudkan dalam bentuk acara resmi, di mana ada sambutan-sambutannya, ada pejabat lintas lembaga, ada rakyat jelitanya, tentu prosesnya akan lebih panjang. Apalagi kalau di acara itu ada foto pimpinan yang kebetulan matanya lagi ngedip, atau rambutnya kurang presisi, atau botak belakang kepalanya terlalu kelihatan, maka hal-hal itu harus dipoles dulu sebelum akhirnya diunggah.
Dalam kesempatan yang lain, kantor saya ngadain acara pertunjukan budaya, dan Big Boss kita memberikan sambutan kira-kira berdurasi 10 menit di acara tersebut. Untuk konten video yang hanya berdurasi 3 menit, serta caption yang cuma satu sampai dua paragraf, kita perlu mendiskusikan bagian mana dari pidato sepuluh menit itu yang akan disoroti seperti,
1. Apakah bagian ketika Pak Bos bilang urgensi pertunjukan budayanya?
2. Apakah bagian soal program pemerintah yang pro acara kebudayaan?
3. Apakah soal lelucon yang dilempar ke audiens, atau mungkin tidak mengutip pidatonya sama sekali?
Proses diskusi dan dinamika birokrasi dalam memilih foto, mengedit video, dan membuat caption ini seringkali jadi arena debat akademik kecil-kecilan.
Salah satu pekerjaan saya di kantor ini memang banyak berkaitan dengan media sosial. Menariknya, saya gak pernah kepikiran sebelumnya betapa perkara membuat caption aja merupakan suatu hal yang penting, seolah-olah ini adalah pekerjaan heroik para pahlawan bangsa di abad sekarang. Karena dalam birokrasi, yang diperdebatkan ternyata bukan hanya konten foto atau videonya, tapi juga caption-nya.
Minggu lalu menjelang kegiatan Upacara 17 Agustus, saya dan tim harus membuat rencana bagaimana kegiatan tahunan ini akan dipublikasikan ke publik. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana caption untuk konten Agustusan nanti. Apakah caption-nya harus bahasa Indonesia atau bahasa asing (kebetulan kantor saya berada di luar negeri), apakah diksinya sudah pas, apakah narasinya sudah sesuai dengan visi misi pemerintah, apakah sudut pandangnya sudah pas, termasuk dalam caption tersebut adakah nama yang perlu di-mention, di-tag, di-collab, atau bahkan tidak dihadirkan sama sekali.
Dalam proses menulis caption Agustusan itu, saya bingung apakah padanan kata untuk “Penaikan Bendera” itu “Flag Raising” atau “Flag Hoisting”? Apa jadinya jika bos saya setuju dengan “Flag Hoisting”, sementara bosnya bos saya lebih suka “Flag Raising”? Apakah di caption perlu menyebut siapa pejabat yang hadir di upacara itu? Apakah perlu menuliskan kalimat yang menggambarkan kegigihan anggota Paskibra yang sudah latihan berminggu-minggu? Atau haruskah menyebut siapa Inspektur upacaranya dan ngapain aja di upacara itu? Apakah perlu juga menyoroti antusias warga yang mengikuti upacara? Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi bagian dari dinamika birokrasi caption di lembaga pemerintah.
Ini baru urusan contoh perihal posting foto di media sosial. Lain cerita dengan hal-hal yang lebih besar seperti isu tarif Amerika Serikat, 19 juta lapangan kerja, kenaikan PBB, Makan Bergizi Gratis, dan isu lainnya yang punya birokrasinya sendiri. Makin besar permasalahannya, makin kompleks isunya, makin rumit birokrasinya.
Pada akhirnya, saya jadi paham bahwa birokrasi itu kadang bikin ribet, tapi tanpa itu sistem nggak bisa jalan. Dan di balik ribetnya birokrasi, ada satu hal yang diam-diam mengikat: semangat memastikan semuanya tertib, sesuai aturan, dan nggak asal-asalan. Kadang saya berpikir, kalau saja birokrasi ini punya genre, mungkin dia masuk “drama komedi absurd.” Karena serius iya, penting iya, tapi di baliknya selalu ada momen yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dan saya, sebagai pemain kecil di panggung besar birokrasi, cuma bisa berusaha bilang “Siap!”, “Oke, noted.”, “Aman!”, atau “Gak apa-apa” tanpa harus ketauan betapa isi kepala dan hati saya teriak-teriak karena udah kebanyakan revisi untuk minor yang kayanya gak penting-penting amat untuk direvisi.