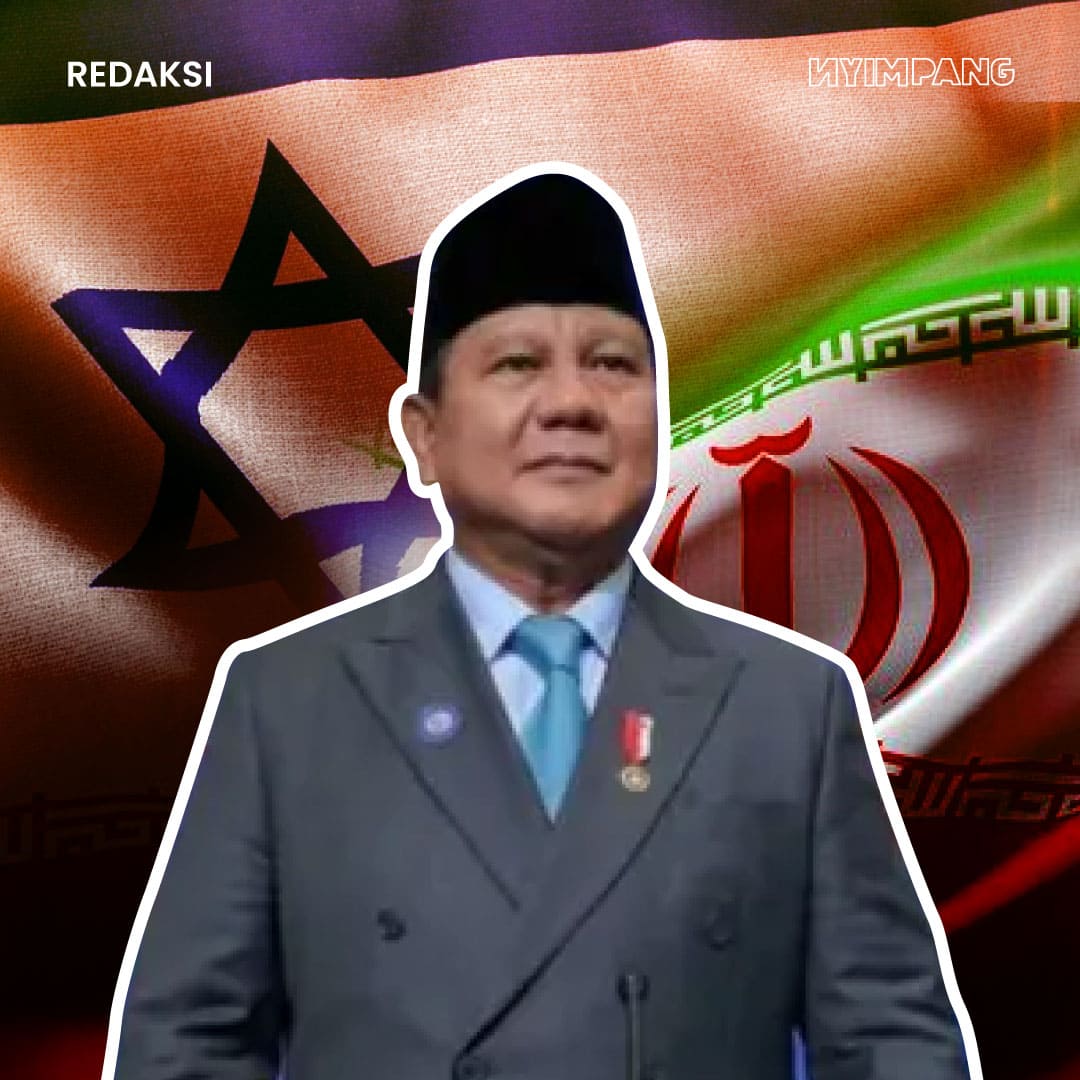
Fenomena Wajib Beli Buku Dosen biar Lulus Matkul

Kampus sering membanggakan diri sebagai ruang paling rasional di muka bumi. Kampus, sebagai ruang mengasah nalar, memuja logika dan mitos dikuliti. Tapi anehnya, di ruang yang katanya logis banget itu, praktik jual-beli (yang dipaksakan) masih hidup subur. Bedanya ya ini di kelas saja: yang jual dosen, yang beli mahasiswa. Barangnya: buku. Syaratnya: wajib.
Kalau cuma jual buku, mungkin tidak masalah ya, toh buku identik dengan ilmu. Tapi jual-beli bukan sembarang jual-beli memang ini.
Jual-beli yang ini dibungkus silabus, dipoles RPS, lalu disegel dengan ancaman paling halus sekaligus paling efektif di dunia akademik: nilai.
“Buku ini wajib dibeli karena jadi pegangan utama mata kuliah ini ya.”
Mantap sekali, bukan?
Dampaknya? Mahasiswa langsung buka E-Wallet, bukan buka pikiran. Di kepala kami atau saya (sebagai mahasiswa), kalimat itu ya terdengar seperti begini:
“Kalau nggak beli, siap-siap ngulang.”
Sebagai mahasiswa, ada lah kesal-kesalnya. Mahasiswa kan jadi bukan konsumen merdeka. Kita datang ke kelas bukan dengan semangat diskusi dan kebebasan memilih, tapi dengan ke-riweuhan- KRS, absen, dan rasa cemas finansial ketika dosen mewajibkan bukunya sendiri.
“Lah ini mah transaksi kuasa.”
Lucunya, praktik ini sering dibela atas nama ilmu. Seolah dengan membeli buku, pengetahuan otomatis pindah dari buku ke otak. Padahal belum tentu.
Saya rasa, yang perlu ditegaskan: menulis buku itu kerja mulia. Dosen menulis buku itu sah-sah saja, bahkan terpuji. Eta mah teu aya masalah. Masalahnya muncul ketika buku dijadikan syarat kelulusan matkul. Mau lulus? Lewat sini. Mau aman? Beli dulu. Paket bundling pokoknya!
Kalau mau jujur, praktik ini mirip MLM. Tidak ada “Bismillah! Saya siap menjadi kaisar!”-nya aja.
Tapi ada bonus nilai C+ yang bisa disulap jadi B kalau nurut. Angkatan ini beli. Angkatan depan beli lagi. Isinya mah sama. Contohnya masih tahun 2009. Dunia sudah ganti algoritma, tapi materi kuliah tetap setia pada satu sudut pandang yang kebetulan punya NIDN.
Biasanya dosen bilang, “Tenang saja, bukunya murah.”
Murah menurut dosen yang gajinya tetap. Mahal menurut mahasiswa yang uang makannya dicicil seperti saya.
Tapi lagi-lagi, yang paling mahal bukan harga bukunya. Yang paling mahal adalah kebebasan mahasiswa yang hilang untuk menentukan pilihan. Diganti senyum palsu dan anggukan iya-iya.
Coba bayangkan satu kelas berani bilang, “Pak, kami mau pakai referensi lain.”
Dalam konteks pendidikan, itu namanya critical thinking. Dalam praktik sehari-hari, itu bisa berubah jadi dicuekin satu semester. Maka mahasiswa cepat belajar: selamatkan IPK dulu, idealisme bisa nanti kalau masih sempat.
Tanpa sadar, kampus sedang mengajarkan bahwa kekuasaan boleh dipakai dengan memaksa, asal dikasih label akademik. Hari ini buku. Besok modul eksklusif. Lusa seminar wajib berbayar. Semuanya gak masalah “demi kelulusan” dan “sistemnya sudah begitu.”
Padahal ilmu yang baik tidak pernah memaksa. Dosen yang yakin dengan gagasannya tidak perlu menjadikan nilai sebagai senjata. Kalau pemikirannya kuat, mahasiswa juga bakal dengan senang hati masuk kelas dan beli buku tanpa terpaksa.
Dosen kan bukan sales. Mahasiswa bukan customer. Kampus bukan marketplace. Ketika ketiganya diperlakukan sebaliknya, jangan heran kalau yang lahir bukan sarjana kritis, tapi lulusan patuh yang jago bertahan hidup di dunia yang isinya kerja-kerja-kerja.
Kalau sebuah buku hanya bisa laku karena diwajibkan, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan mahasiswanya, tapi kualitas dialog yang gagal dibangun.
Sebab saat buku berubah jadi tiket lulus mata kuliah, kita pantas curiga: jangan-jangan kita tidak sedang belajar apa-apa dan kita cuma sedang bayar jalan pintas aja. Menurutmu gimana?





