
Duka Amara

Kelopak mataku berkedut sebelah kanan, tapi aku punya kebiasaan untuk memercayai hal-hal baik akan datang saat salah satu anggota tubuhku berkedut seperti sinyal. Air mengalir dari sudut gayung biru bergambar Winnie the Pooh, namun matanya hilang karena terkikis dan lembab.
Pertama, kubiarkan air itu mengaliri pundak kananku terlebih dahulu, sebab rasanya lebih nyeri dibanding anggota tubuhku yang lain. Lalu pundak kiri, dan dadaku yang menyembul kemerahan akibat luka lebam. Aku meringis menahan perih.
Kumatikan keran, membiarkan sisa air menetes ke lantai kamar mandi yang mulai kusam. Aku menunduk, melihat kakiku yang mulai memucat dan jari-jari yang kaku oleh air dingin. Sudah berapa lama aku mandi? Aku menoleh jam tangan yang menggantung di dinding.
Entahlah, yang kuingat jam itu baru saja kubeli tiga hari yang lalu.
Aku menyentuh jam tangan itu, jarum jamnya berdetak, pelan tapi pasti. Satu-satunya benda yang terasa hidup di antara segala yang membisu.
“Mara!”
Aku menghela napas pelan. Kali ini apalagi? Aku sudah berusaha bersembunyi di kamar mandi, berharap suara itu tak mengikutiku ke sini.
“Mara! Kamu gila, ya?” Suara itu terdengar lagi, kini lebih keras dari sebelumnya.
Tangan besar itu menarikku tiba-tiba, lalu menyentuh kepalaku dengan cepat.
“Sudah berapa lama kamu mandi?”
Aku menatapnya, pandanganku menjadi agak samar seperti melihat seseorang asing.
“Apa?” kujawab, mataku semakin menyipit berusaha mencerna pertanyaan itu. Dengan sigap dia membalutku dengan selimut lalu memelukku sambil menangis.
Di dunia ini, tak ada satu pun yang ingin berduka. Ia hadir menjadi perasaan pedih seperti peniti yang tertinggal di ulu hati. Wayan memberitahu kalau aku tidak keluar dari kamar mandi sejak petang, dan kini sudah lewat dari shubuh. Matahari mulai menembus kaca jendela sedikit demi sedikit. Baru kusadar ternyata aku baru berduka enam jam, bukan tiga jam.
Aku duduk di kursi dekat meja, menatap jarum jam yang bergerak perlahan, sementara aku meraba pundakku yang terasa sakit. Lebam itu semakin terlihat jelas—warna ungu kehitaman yang mencuat, seakan menandakan sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku ingat betul, beberapa hari yang lalu, aku merasa sesak dan ingin lari dari semuanya. Aku menekan dadaku, berharap bisa menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan.
“Rasanya jomplang banget, Wan… Masa aku cuma dapat lebamnya doang tapi Arka yang meninggal?”
Aku ingat ada sesuatu di pundakku yang terasa berat. Sebelum aku pingsan—atau lebih tepatnya, sebelum aku merasa seperti hilang dari tubuhku—aku merasa sebuah sentuhan, kasar dan tajam, seperti cengkeraman yang memaksa tubuhku tetap ada.
Mobil yang kutumpangi dengan Arka mendadak rem blong. Kami sempat panik, dan Arka yang duduk di belakang kemudi berteriak menyuruhku membuka sabuk pengaman dan loncat jika bisa. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Mobil menghantam pembatas jalan, dan tubuh kami terpental. Aku tak ingat bagaimana aku bisa terseret ke luar dan hanya terhantam sisi kanan, sementara Arka… dia tak pernah keluar dari dalam mobil itu.
Wayan tidak banyak bicara setelah itu, hanya membalut pundakku dengan kain dingin dan memberiku obat. Tapi setiap kali aku melihat lebam itu, aku teringat perasaan terjepit, perasaan bahwa ada yang salah, tapi aku tak bisa lari dari rasa itu. Seolah dunia ini memberikan pelajaran keras tentang ketidakmampuanku untuk bergerak maju, bukan hanya secara emosional, tetapi fisik.
Aku mulai berpikir, apakah lebam ini hanya luka luar? Atau, apakah ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, dari luka yang terus bertumbuh di dalam hati dan pikiranku? Aku menatap Wayan yang berdiri di pintu, masih menunggu.
“Wan, aku kenapa, ya?” tanyaku, suara serak.
Wayan menggeleng, ekspresinya hampa. “Yang lebih tahu kan dirimu sendiri, Mar. Coba cek CCTV kamarmu, biar ketahuan selama enam jam itu kamu ngapain aja. “
“Arka tadi bareng sama kamu, kan?” Aku memeriksa perban yang dibalut oleh Wayan—jago juga dia, pikirku.
“Mulai deh. .” Wayan menghela napas.
Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Rasa berat di dadaku semakin memadat, seakan dunia ini mulai mengecil, menekan semua napasku.
“CCTV kamar?” Aku tertawa pelan, hampir tak terdengar. “Nggak deh, kayaknya aku udah gila, ya.” Suaraku masih serak, seperti ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokan. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang salah dengan kata-kata Wayan. Sesuatu yang janggal. Seperti ada lubang besar dalam percakapan kami, yang semakin membesar.
Wayan melangkah masuk, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. “Kamu udah nggak sadar, Mara,” katanya. “Bukan cuma tentang Arka, ini tentang kamu sendiri. Kenapa semua jadi serba kabur kayak gini?”
Aku menggigit bibir, tidak tahu apa yang harus kukatakan. “Aku cuma… merasa hilang, Wan. Aku nggak bisa lagi bedain mana yang nyata, mana yang cuma aku bayangkan.” Aku menggenggam pundak yang terasa semakin nyeri, mencoba menahan tubuhku dari runtuh. “Arka ada di sini, kan?”
Wayan tidak menjawab langsung. Dia berdiri beberapa langkah di depanku, seolah berpikir keras. “Mar…” Ucapannya terhenti, seolah takut melanjutkan. Akhirnya, dia menghela napas dan mendekat. “Kamu harus ke psikolog, Mar. Aku nggak bisa bantu kamu kalau begini terus.”
Aku menggeleng, mataku tertuju pada lebam di pundak yang semakin jelas.
“Bingung. Rasanya seperti mimpi. Nggak tahu kenapa aku merasa dia masih ada di sini.”
“Wan, aku takut,” aku berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. “Takut kalau aku nggak bisa keluar dari sini.”
Wayan menatapku lebih dalam, dan kali ini ada sesuatu yang berubah di matanya, rasa khawatir yang lebih dari sebelumnya. Dia menarik napas panjang, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan.
“Kamu udah lama banget terjebak di perasaan ini, Mar. Nggak cuma kehilangan Arka, tapi kamu juga kehilangan diri kamu sendiri. Kamu butuh bantuan. Aku nggak bisa ngeliat kamu kayak gini lagi.”
Aku menunduk, perasaan hampa semakin menyelimutiku. “Kenapa jadi gini, sih?” ucapku, suara bergetar.
“All is well, Mara…” Wayan akhirnya berkata, keteguhan mulai muncul di wajahnya. “Kamu nggak sendiri, Mar. Jangan mikir kamu harus jalan sendirian.”
Aku menatapnya, terasa seperti ada dua dunia yang bertabrakan di dalam kepala. Aku tahu Wayan benar. Aku tahu aku butuh sesuatu untuk mengubah keadaan ini. Tapi sejujurnya, aku tak yakin bisa melepaskan semuanya begitu saja.
Akhirnya, aku berdiri, menatap cermin kecil di meja. Aku memandang diri sendiri dengan rasa tak mengenal. “Mandi seharian bikin perut keroncongan ternyata.”
Wayan mengangguk, sedikit tersenyum. “Yuk, mau makan apa?”



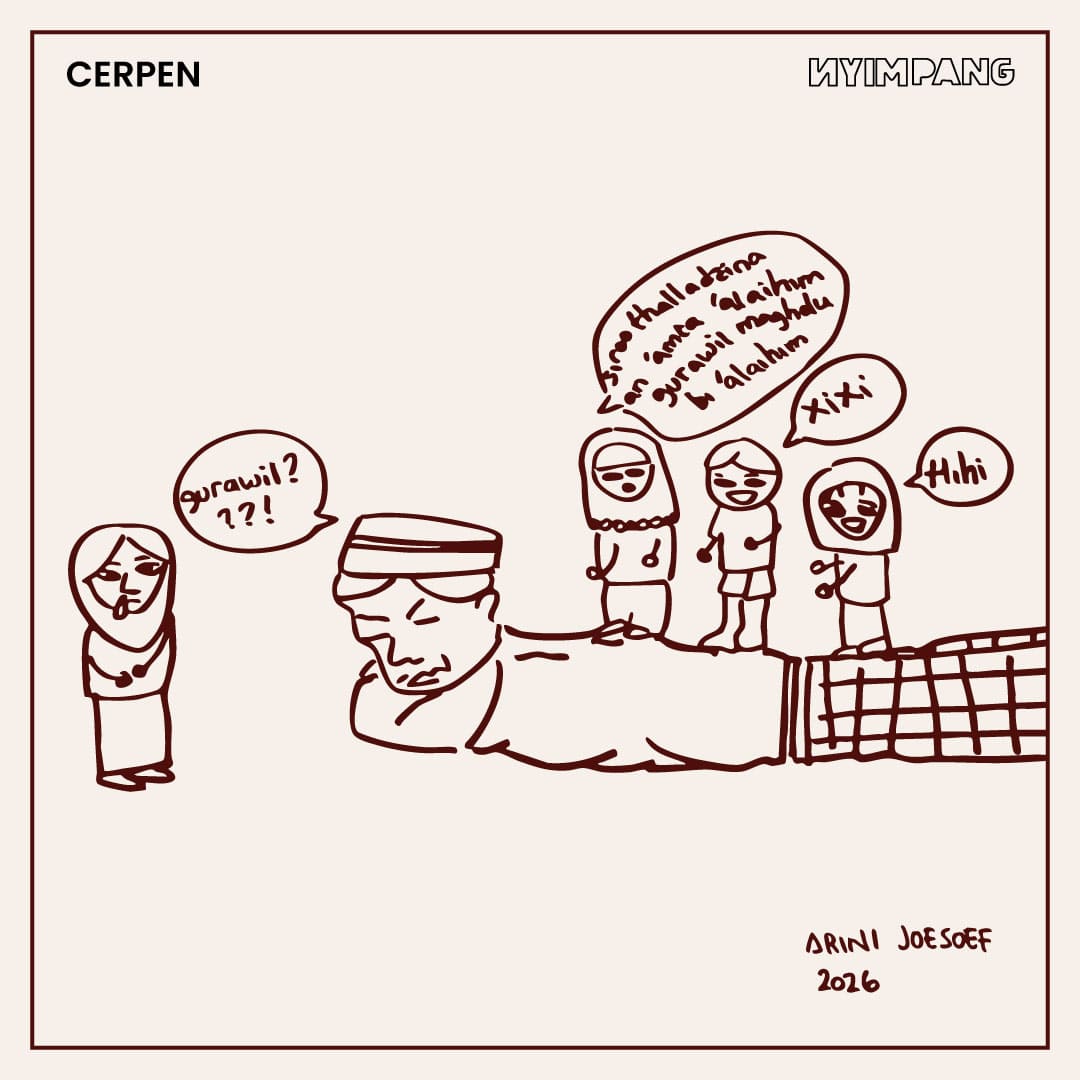


“menjelaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan” ternyata kehilangan seseorang yang sangat begitu berarti malah membuat kita kehilangan diri sendiri, kita hanya butuh ikhlas untuk merelakan dia yang sudah pergi…