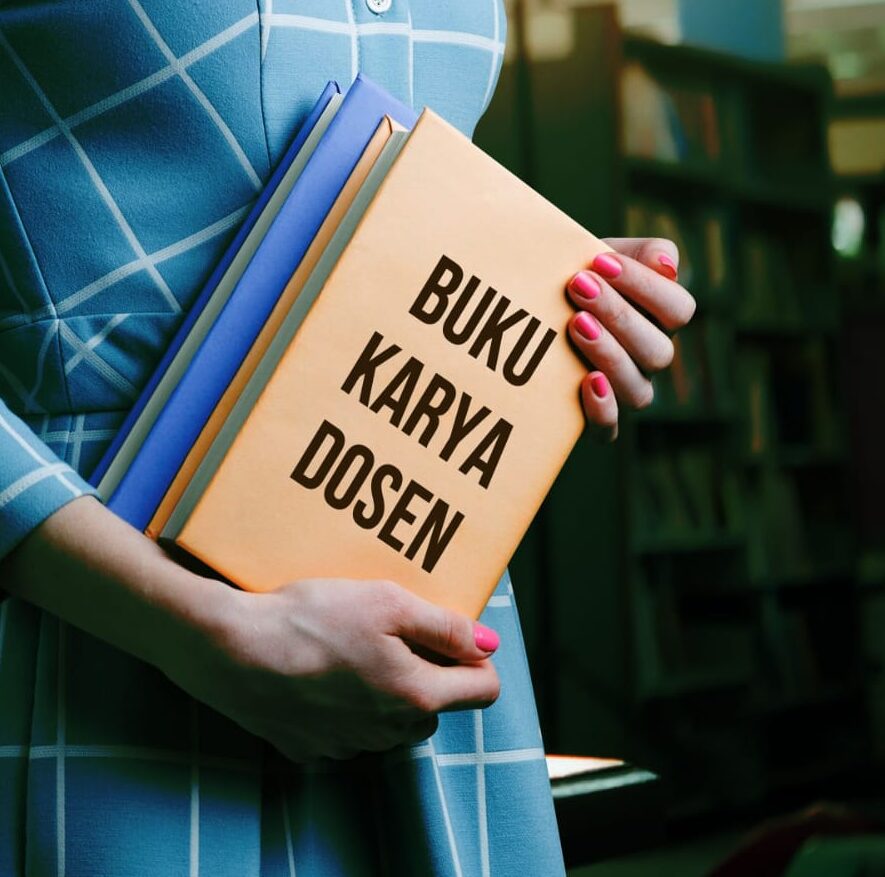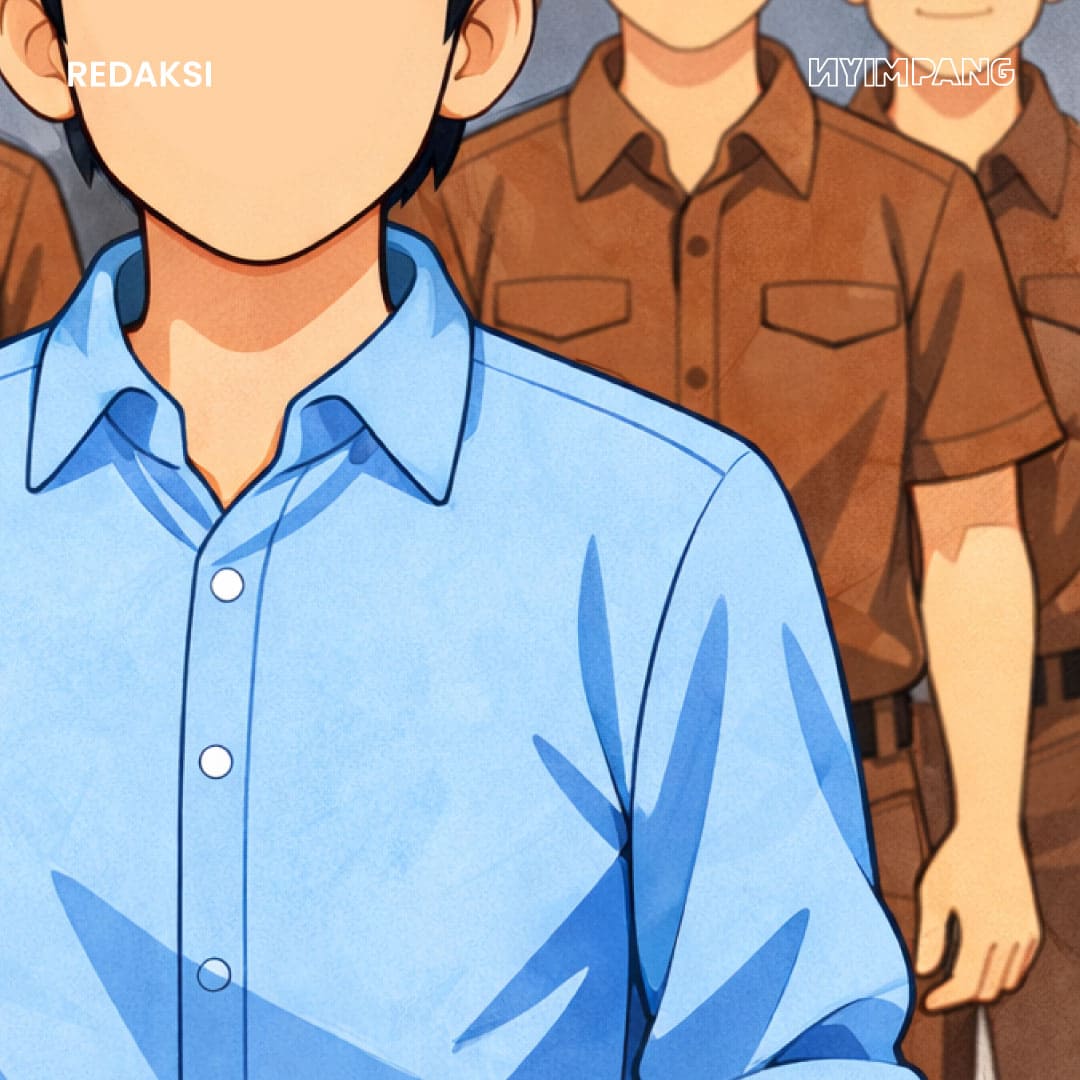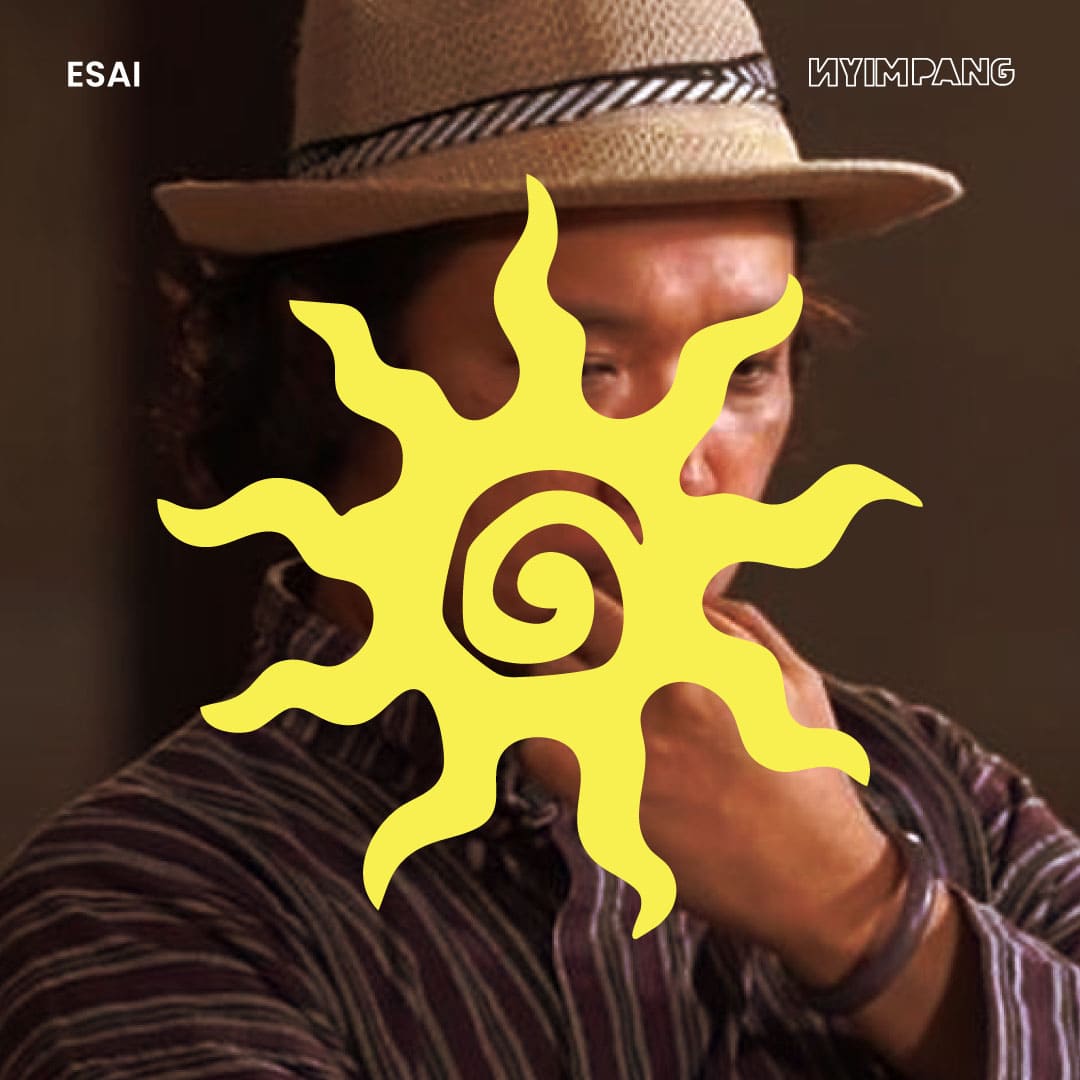
Dosa Paling Tidak Kalcer Abad Ini

Kita terlalu penakut akan kebenaran. Kita terlalu penakut jika ternyata pasangan kita tidak benar-benar mencintai kita, jika pasangan kita secara diam-diam ternyata juga berkencan dengan laki-laki atau perempuan lain. Kita terlalu takut jika faktanya di tempat tinggal kita masih banyak ketidakadilan dibiarkan begitu saja. Kita takut tahu jika ternyata pejabat kita korup, wakil rakyat tidak membela rakyatnya, hukum bengkok, industri tidak berpihak pada pekerja, dan lain-lain.
Kita terlalu malas pergi ke dokter ketika kita tahu bahwa tubuh kita ada yang bermasalah. Kita takut jika orang lain mengetahui kenyataan bahwa kita memiliki borok, kita pemalas, tapi mendamba kekayaan. Kita takut bilang bahwa kita punya banyak masalah dan kita sangat rapuh.
“Kadang-kadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur.” – Friedrich Nietzsche
Kebenaran yang tidak kita inginkan, fenomena ini kerap berkaitan dengan ungkapan lama, “Ignorance is a bliss”, yang artinya “ketidaktahuan adalah sebuah kebahagiaan.” Istilah ini berasal dari puisi “Ode on a Distant Prospect of Eton College” karya Thomas Gray pada abad ke-18. Frasa ini menyiratkan bahwa dalam banyak situasi, ketika seseorang tidak menyadari bahaya, konflik, atau ketidakadilan yang ada di sekitarnya, ia tidak akan mengalami keresahan emosional yang muncul akibat kesadaran tersebut.
Dalam konteks ini, ketidaktahuan memberikan perlindungan psikologis dan memungkinkan seseorang hidup dengan pikiran yang lebih ringan. Namun, meskipun ketidaktahuan bisa membawa kedamaian sementara, pandangan ini juga bersifat paradoks dan problematik. Dalam jangka panjang, mengabaikan kebenaran atau memilih untuk tetap tidak tahu bisa memperparah masalah, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya, seseorang yang mengabaikan tanda-tanda penyakit serius karena tidak ingin tahu diagnosisnya mungkin akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk. Begitu pula dalam masyarakat, ketidaktahuan terhadap isu-isu sosial, politik, atau lingkungan dapat membuat orang pasif, tidak kritis, dan mudah dimanipulasi.
Kisah Socrates, filsuf besar Yunani kuno, adalah contoh nyata dan historis dari pepatah “Orang yang berkata benar akan kesepian.” Sepanjang hidupnya, Socrates dikenal karena keberaniannya mempertanyakan norma, nilai, dan keyakinan masyarakat Athena melalui metode dialektik yang sekarang dikenal sebagai Socratic Method. Ia tidak segan menantang para politisi, penyair, dan ahli retorika, serta mengajak orang untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka anggap sebagai “kebenaran.” Dalam upayanya mencari dan menyampaikan kebenaran, Socrates justru menjadi sosok yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh banyak orang berkuasa.
Puncak dari kesepiannya sebagai pencari kebenaran adalah saat ia diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh negara kota Athena pada tahun 399 SM. Tuduhan terhadapnya adalah merusak pikiran anak muda dan tidak menghormati dewa-dewa negara. Namun, inti dari tuduhan tersebut sebenarnya adalah karena keberaniannya mengungkap kebodohan tersembunyi dalam otoritas yang mapan. Saat menghadapi hukuman mati, Socrates tetap teguh pada pendiriannya, menolak untuk mundur dari pencarian kebenaran meski tahu bahwa itu akan membuatnya kehilangan nyawa. Ia memilih integritas intelektual dibanding keselamatan pribadi — dan dengan itu, ia menanggung kesepian eksistensial sebagai seseorang yang memilih untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam penerimaan sosial.
Ilustrasi Gua Plato
“Kebenaran bisa menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan.” – Plato. Ungkapan “orang yang berkata benar akan kesepian” tercermin jelas dalam kisah hidup Socrates, filsuf Yunani yang memilih untuk hidup dalam kebenaran meskipun harus menghadapi penolakan dan kematian. Melalui dialog-dialognya, Socrates berani mempertanyakan keyakinan, nilai, dan otoritas yang diterima begitu saja oleh masyarakat Athena. Namun, keberanian intelektualnya justru membuatnya dibenci, dianggap mengganggu ketertiban, dan akhirnya dihukum mati. Ia lebih memilih mati daripada hidup dalam kebohongan atau membiarkan masyarakat tetap terjebak dalam ketidaktahuan.
Kisah Socrates ini sejalan dengan ilustrasi gua Plato, di mana seseorang yang keluar dari gua dan melihat kebenaran justru ditolak ketika mencoba membagikannya kepada mereka yang masih terikat pada bayangan semu. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam ilusi sering kali menolak realitas yang mengguncang kenyamanan mereka. Maka, orang yang membawa kebenaran kerap dianggap ancaman, dijauhi, bahkan dimusuhi. Kesepian pun menjadi konsekuensi bagi mereka yang memilih jalan kebenaran dalam masyarakat yang belum siap untuk menerimanya.
Melawan Rasa Takut
Dilema semacam ini kian bertambah dahsyat lalu bertumbuh subur seiring ketakutan dibiarkan begitu saja. Apa pengetahuan kebenaran sebegitu menyakitkan? Lalu apa yang harus kita lakukan?
Saya yakin, secara historis ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran meskipun dalam ruangan hanya tersisa satu lilin kecil. Saya yakin, cita-cita ilmu pengetahuan supaya individu terbebas dari seluruh bentuk kekangan, meski itu dalam kerangkeng berpikir. Dengan kata lain, ada yang salah dengan cara berpikir kita kendati tidak ingin mengetahui kebenaran-kebenaran yang terjadi di sekitar kita.
Manusia memiliki rasa takut sejak lahir. Bayi menangis sebab ketakutan kehilangan ASI dari ibunya. Seorang anak perempuan lari terbirit-birit ketakutan tatkala melintas depan kuburan jam 12 malam. Tapi, apakah seorang bayi tadi akan selalu bergantung pada ASI dari ibunya?
Dalam psikologi belajar, individu menangkap informasi dari apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia sentuh, yang kemudian direduksi oleh otak dengan pengalaman sebelumnya sehingga membentuk suatu persepsi. Apa yang dipersepsikan seseorang memengaruhi apa yang dirasakannya. Secara teori, persepsi melibatkan sistem saraf pusat, terutama area sensorik di korteks serebral, amigdala, dan hipokampus. Amigdala memainkan peran penting dalam memproses emosi, termasuk rasa takut, dengan mendeteksi potensi ancaman dan mengaktifkan respons stres melalui sistem limbik.
Seseorang pernah bilang, rasa takut tidak abadi. Ia bisa dihancurkan dengan cara dilawan. Saya tertawa mendengarnya. Kalimat itu sederhana, namun sangat berat dalam praktik. Bagaimana kita melawan rasa takut kalau perlawanan itu juga memerlukan keberanian? Mungkin, kita akan berhenti ketakutan ketika kita melakukannya bersama-sama. Anak perempuan tadi sangat ketakutan saat melintas depan kuburan jam 12 malam karena dia sendirian. Pengalaman pertama, kita boleh takut, dalam hal apa pun, tapi saya yakin, pengalaman berikutnya rasa takut itu akan hilang, setidaknya berkurang, sebab alam bawah sadar sudah mengenal dan secara mekanistik diri kita akan menyesuaikan.
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, no. 49)
Rujukan
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2020). Neuroscience: Exploring the brain (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Gray, T. (1747). Ode on a Distant Prospect of Eton College (Stanza 10). Dalam Poems (Edisi 1768). London: J. Dodsley.
- Nietzsche, F. (n.d.). Kadang-kadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur [Kutipan populer]. Diakses dari Kompasiana dan Facebook.
- Plato. (n.d.). Allegory of the Cave (Republik, 514a–520a). Dalam Wikipedia. Diakses pada 10 Juni 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_Cave
- Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Trial of Socrates. (n.d.). Dalam Wikipedia. Diakses pada 10 Juni 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Socrates