
Di Tangan Pemerintah Apapun Jadi Ribet, Termasuk Musik
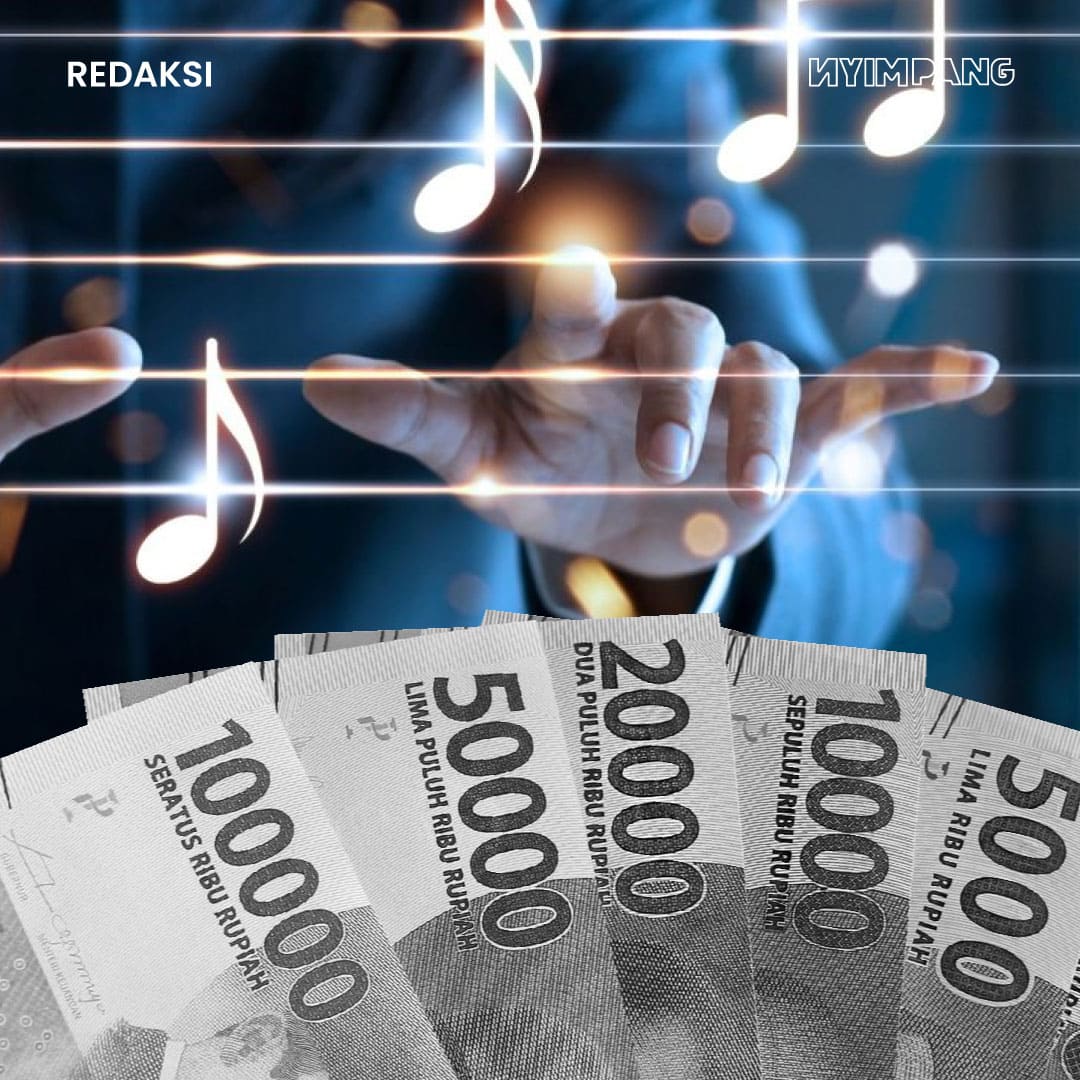
Bagi masyarakat Indonesia musik dan lagu amat dekat dengan keseharian. Dari bayi kita sudah dinyanyikan lagu pengantar tidur seperti “Nina Bobo”, saat tumbuh balita kita dinyanyikan “Pok Ame-Ame Belalang Kupu-Kupu”, kita punya banyak lagu anak-anak mulai dari “Anak Gembala” sampai “Diobok-obok”, begitupun masa remaja, dewasa hingga tua musik terus menemani kita seumur hidup.
Musik harusnya jadi penghiburan yang menyatukan tiap orang. Sebuah lagu bisa bikin kita tersenyum, menangis, ataupun menemani masa galau. Tapi di Indonesia, belakangan ini musik jadi drama layaknya berita artis cerai. Bukan karena liriknya yang berisi kata-kata jorok atau umpatan, bukan juga karena melodinya yang mirip dengan lagu lain, tapi karena urusan yang terdengar sederhana namun malah jadi rumit: royalti.
Misalnya pada Februari 2025, Penyanyi Agnez Mo pernah berurusan dengan tuntutan dari Ari Bias perkara royalti. Ari Bias menuduh Agnez Mo melakukan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu ciptaannya yang berjudul ‘bilang saja’ di berbagai acara tanpa izin darinya. Hasil akhirnya adalah Agnez Mo dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjatuhkan denda sebesar Rp 1’5 milliar yang harus ia bayarkan kepada Ari Bias.
Contoh kasus yang terbaru adalah kisruh antara PT Mitra Bali Sukses pengelola Mie Gacoan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK SELMI) tentang pemutaran lagu tanpa izin di gerai-gerai Mie Gacoan. Kasus itu mulai bergulir sejak Agustus 2024 dan baru berakhir setahun kemudian. PT Mitra Bali Sukses (MBS) menyelesaikan perkara itu melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT Mitra Bali Sukses (MBS) membayar royalti kepada LMK SELMI sebesar 2,2 Milliar. Hitungannya dimulai sejak tahun 2022 hingga akhir Desember 2025. Itupun hanya menghitung 65 gerai Mie Gacoan yang berada di bawah naungan PT Mitra Bali Sukses (MBS). Sebab ratusan gerai Mie Gacoan lainnya berada di bawah naungan PT Pesta Pora Abadi (PPA).
Bukannya memperelok suasana industri musik , dua kejadian di atas justru bikin banyak penyanyi mulai mikir dua kali sebelum bawain lagu orang. Pemilik tempat usaha seperti kafe juga bakal mempertimbangkan matang-matang sebelum menyetel musik di tempatnya. Takut ditagih royalti, padahal kafe-nya aja belum tentu rame.
Semua kerumitan ini bila ditelusuri akan bermuara pada dua kata: sistem royalti.
Di atas kertas, sistem ini dibuat untuk melindungi pencipta lagu agar karyanya dihargai. Pemerintah lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengatur semua pembayaran dan pembagian royalti.
Masalahnya, seperti umum terjadi di pemerintahan kita tercinta, pelaksanaannya kacau balau. Pengguna lagu (misalnya kafe, EO, stasiun TV) sering bingung bayar ke mana dan berapa. Hitungannya kurang Transparan. Pencipta lagu nggak selalu tahu persis lagu mereka diputar di mana, berapa kali, dan berapa royalti yang harusnya mereka terima.
Belum lagi soal data yang tumpang tindih. Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia itu ada 16 dan semuanya punya data sendiri-sendiri, kadang tidak sinkron.
Kisruh ini bikin musisi terbagi jadi dua kubu. Ada Kubu Pencipta Lagu (contohnya AKSI) ingin aturan ketat demi melindungi karya dan Kubu Performer (contohnya VISI) ingin aturan yang lebih fleksibel agar kreativitas di panggung tidak mati gara-gara izin yang ribet.
Perbedaan pandangan ini bikin ruang diskusi kadang terasa seperti debat antar kader partai, bukan obrolan santai antar seniman.
Niat awal pemerintah jelas ingin melindungi hak cipta. Tapi realitanya, regulasi yang ada malah memunculkan rasa takut di kalangan pelaku musik. Alih-alih mempermudah, aturan terasa seperti jerat.
Apalagi, nominal royalti yang sampai ke pencipta kadang bikin geleng-geleng kepala. Piyu (PADI) misalnya hanya menerima Rp. 125.000 royalti dari LMK/LMKN dalam kurun waktu satu tahun.
Bagi musisi, musik adalah jiwa. Mereka nggak cuma mau dibayar adil, tapi juga ingin karya mereka bisa dinikmati tanpa rasa takut. Sayangnya, ketika birokrasi terlalu dominan, yang indah bisa jadi rumit, dan yang rumit sering kali mematikan kreativitas.
Semua pihak—pencipta lagu, penyanyi, promotor, pemerintah—sebenarnya punya tujuan yang sama yaitu ingin industri musik yang adil dan berkelanjutan.
Musik seharusnya sederhana: diciptakan, dimainkan, dinikmati. Tapi ketika terlalu banyak tangan mengatur, keindahan itu bisa tertutup tumpukan kertas dan tanda tangan.
Kalau pemerintah mau benar-benar melindungi musik, jangan sampai sistemnya justru membuat seniman takut berkarya. Karena musik yang indah, kalau jadi rumit, kehilangan separuh nyawanya.





