
Cirebon, 2003

Kala itu, bayangan Ibu menggema di seisi ruangan. Ia ada di mana-mana, terlihat kabur. Namun, ada satu bayangan yang tampak jelas—ia sedang membuat camilan kesukaanku. Sebenarnya, aku lebih menyukai bumbunya dibanding lauknya. Bumbu spesial yang dibuat dengan sukacita dan cinta, dipadukan dengan tangan lembutnya. Sepintas, meski bumbunya sempurna, jika lauknya busuk, tetap saja tak terasa spesial dan senada.
Di meja dapur yang kusam—tak semenarik liuk-liuk tangannya yang lembut—Ibu menghaluskan daging ikan tenggiri. Semerbak bau amis menyelinap ke kepalaku dengan halus. Tangan lainnya cekatan memasukkan bawang, gula pasir, bubuk penyedap rasa, dan tepung secara bergantian. Tanpa menggunakan timbangan, hanya mengandalkan instingnya, seolah ia tahu isi jiwa darah dagingnya sendiri.
Tepungnya dituangkan dengan penuh nafsu hingga berterbangan ke mana-mana, membuat mataku kabur seperti tertutup kabut. Namun, yang kusadari, kabut itu menjelma menjadi air mata yang menggenang.
Tak luput bahan jagoanku—kesukaanku—daun jeruk limau yang ia masukkan ke dalam adonan. Tangannya terus berpindah dengan cekatan. Aroma minyak bertemu adonan, menjenguk sukmaku. Ia tak menyentuhnya dengan sudip, tak mengacak-acaknya, hanya berkata:
“Kadang, membuat makanan sama seperti membesarkan anak.”
Suara itu nyata, begitu nyata hingga menghadirkan luka rindu.
Setelah selesai, ia membawa camilan itu—batagor yang diguyur dengan bumbu spesial—disajikan di piring seadanya. Sendok silver tipis berukir naga dan ayam menemaninya, sederhana. Di meja makan, atau lebih tepatnya ruang tamu yang disulap, ada aku yang masih kecil, menunggu dengan khidmat.
“Ini, Dek. Batagor kesukaanmu,” ucap Ibu.
Mereka duduk bersama, bercerita dengan khusyuk, atau lebih tepatnya, Ibu yang lebih sering mendengar daripada berbicara. Aku berjalan, lalu duduk di samping aku yang masih kecil, tepat di hadapan Ibu. Mereka berhenti berbicara, lalu berbarengan menatapku, dengan senyum seteduh sinar mentari pagi—sinar yang menyelinap di sela-sela dedaunan yang rimbun dan hangat—seolah mengisyaratkan:
“Ayo, kali ini giliranmu bercerita.”
Aku tersenyum senang dan berkata:
“Sudah berapa tahun, ya, aku meninggalkan kalian, Ibu? Setelah melewati medan perang di wilayah yang tak kukenal, aku hampir bisa beradaptasi. Ditemani Hawa yang kukira obat, ia justru berubah menjadi bangkai parasit.
“Sudah bangkai, lalu parasit—separah itu memang. Setelah ia hilang, saripatiku telah dihisap olehnya. Ragaku terkena kudis, dan aku tertular tingkah lakunya pula. Walau sudah sadar dan luka-luka ini terlihat jelas, aku terus terbayang. Terbiasa terinfeksi, terbiasa dihisap. Aku seperti pecandu narkoba jika berada di dekatnya—aneh dan ketagihan diperlakukan seperti itu.”
Aku melihat mereka masih dengan tenang mendengarkan. Tak ada celaan, tak ada petuah. Di depanku, batagor dengan piring kecil sudah terhidang, menunggu untuk disantap. Namun, aku menghiraukannya meski lebih menggiurkan dibanding sungai susu. Aku melanjutkan ceritaku:
“Aku hidup sambil menenteng nerakaku sendiri, dengan caraku sendiri. Tapi, anehnya, banyak yang bilang tubuhku subur dan membesar. Aneh, kan?
“Apa aku memang harus bersahabat dengan cambuk setiap hari atau menanggung beratnya kehidupan seperti Atlas? ‘Mati perlahan-lahan kalau begini terus.’ Pikiran itu terus berputar di kepalaku, Bu. Akhirnya, neraka tingkat pertama bisa kulewati.
“Mungkin berkat doamu atau Tuhan yang sedang berbelas kasih. Aku mulai mengenal lebih banyak teman, hasrat datang dari berbagai sisi, menyemangatiku untuk bertahan.
“Namun, naasnya, di neraka tingkat kedua, cobaan kian berat. Masukan yang membangun dan menjatuhkan dari teman-teman yang merasa tertinggal olehku tak lagi bisa kubedakan. Rasanya kepalaku seperti kepala orang lain. Ada wejangan darimu yang keliru, Bu: ‘Terbentur, terbentur, lalu terbentuk.’ Tapi bagiku, ‘Terbentur, terbentur, terbentur, lalu hancur.’
“Belum habis sampai di sana, lahir lagi masalah dari sumur yang kelam. Kini, permasalahan bumi dan langit serta surga yang berbeda menghantui garis hidupku. Aku hidup di selokan neraka, berseberangan dengan jurang kematian.
“Lengah sedetik saja, aku bisa hilang ditelan kegelapan. Melelahkan, Bu. Saking melelahkannya, suaraku kadang tak terdengar oleh kupingku sendiri. Bahkan, jika aku sedang marah, suaraku bisa membelah bulan.
“Namun, aku tak ingin Ibu—surgaku—terganggu pikirannya. Dan untuk aku yang masih kecil, maafkan aku yang belum bisa membahagiakan surga dan semesta kita berdua.”
Ibu mendekatiku. Telapak tangannya mengusap derita yang jatuh tetes demi tetes. Telapak tangan yang tegas, tetapi selembut sutra—hangat sekali, hingga menembus relung jiwa.
Telapak tangan mungil dari aku yang masih kecil turut mengusap punggungku. Lembut, pelan. Tubuhnya yang kurus dan mungil terlihat jelas karena ia harus berdiri agar tingginya setara dengan punggungku yang sedang duduk. Air mataku semakin deras seperti hujan. Pilu bercampur dengan kekecewaan terus menggerayangi dadaku.
Aku mengucapkan terima kasih. Aku akan mengusahakannya sendiri. Perlahan, senyum teduh mereka kembali merekah. Semakin lama, semakin kabur. Hingga akhirnya, mereka menghilang tanpa sisa.
Namun, aku tahu, mereka hanya bentuk dari imajinasiku sendiri. Tapi rasa hangat dan senyum teduh itu—benar-benar nyata.
Dari sela-sela jendela, cahaya kekuningan mulai masuk ke dalam ruangan. Angin sejuk musim semi berhembus, harum dan manis. Ia menyentuh rambutku, seakan membawa pesan:
“Aku akan selalu mendoakanmu.”


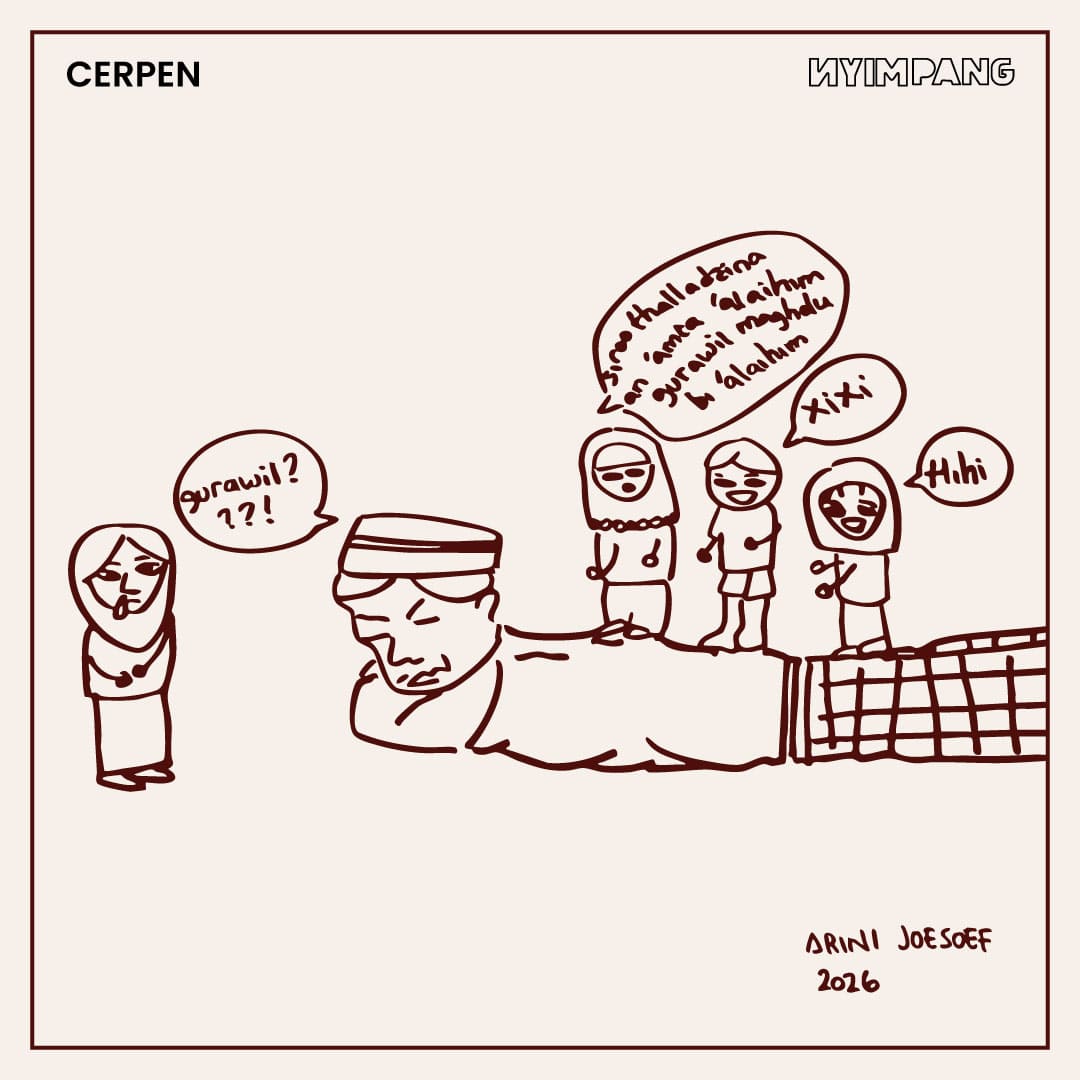



Suka sekali dengan tulisan ini.
Deep ngab