
Buku Jelek, Bubur Diaduk, dan Drama Diskusi Sastra
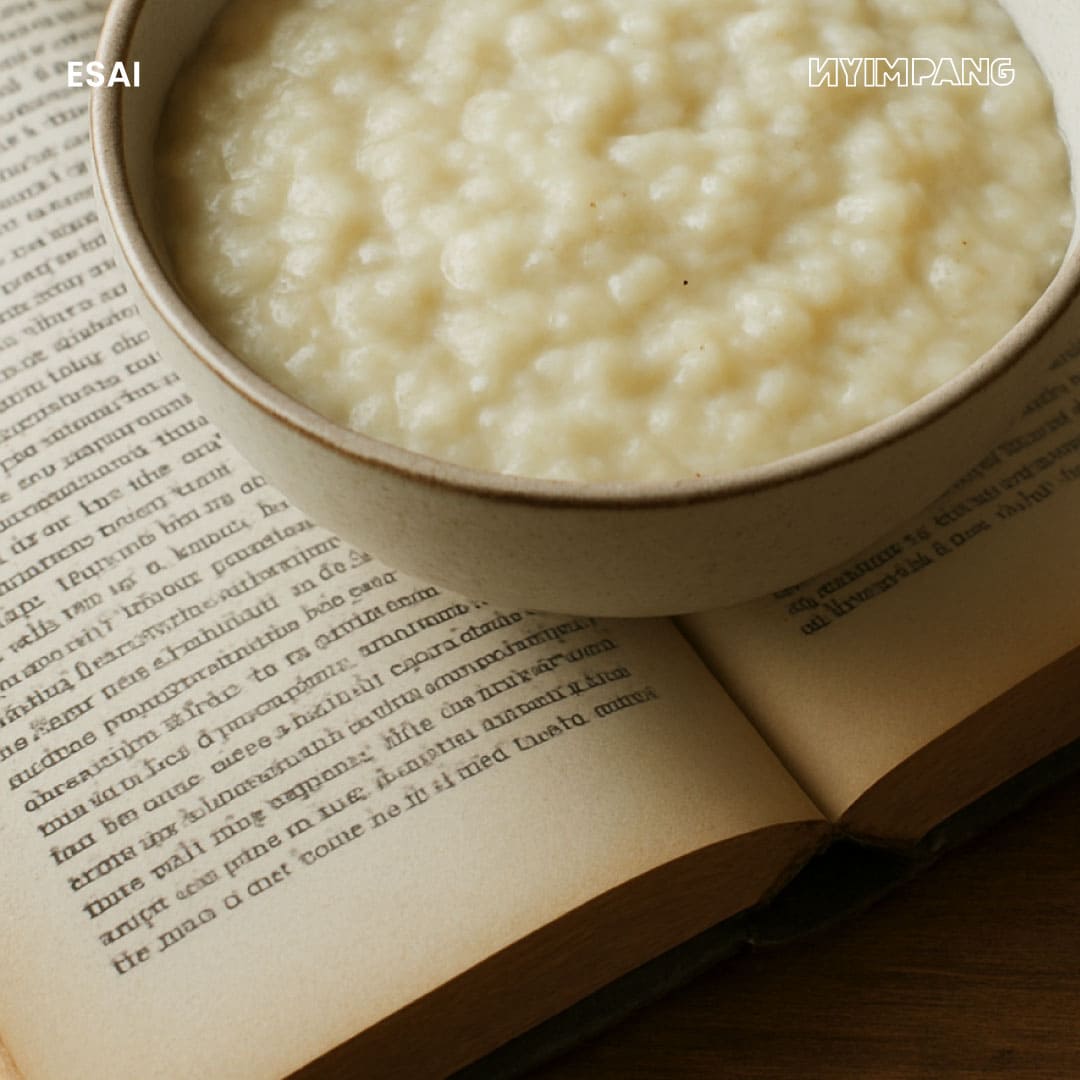
Ketimbang memperdebatkan sastra atau tidaknya sebuah buku, mending kita bicarakan bagaimana menyelesaikan perdebatan bubur diaduk atau tidak diaduk.
Aku sebenarnya malas ketika diajak untuk menghadiri sebuah diskusi buku. Lagian kenapa harus didiskusikan ya? Bikin pusing aja. Apalagi kalau buku yang didiskusikan itu jelek, kita cuma akan disuguhkan dengan misuh-misuh si pembicara saja, dan yang paling aku herankan juga adalah hampir separuh dari yang hadir, pasti belum membaca buku yang tengah didiskusikan. Aneh kan? Ya begitulah, biar kelihatan peduli saja dengan sastra Indonesia ini.
Kebetulan dua hari yang lalu aku diajak untuk menghadiri sebuah diskusi buku. Kali ini aku tidak dapat menolak ajakan itu karena yang mengajakku adalah seniorku di dunia kepenulisan, yaitu Johan Arda. Apalagi beliau adalah seorang promotor sastra, ah betapa segannya diriku. Kebetulan beliau menjadi pembahas pada diskusi buku tersebut. Di diskusi ini dia tidak sendirian, ia ditemani oleh seorang pengamat sastra yaitu Bunga Suci Pertiwi. Entah sastra mana yang diamatinya, entahlah. Haha. Aish, sungguh aku merasa tidak apa-apanya di hadapan mereka.
Saat diskusi berlangsung, aku hanya duduk di pojokan, mendengar mereka berdua bergantian memberikan pendapatnya terhadap buku yang tengah didiskusikan. Johan Arda tampak seperti bapak yang menasehati anaknya yang ketahuan mencuri mangga tetangga, sedangkan Bunga seperti ibu tiri yang memecut anaknya yang ketahuan selingkuh. Aku hanya bisa mendengarkan mereka dan berharap diskusi ini cepat selesai, kemudian aku kembali ke kosanku dan menelpon kekasih hatiku.
Sampai akhirnya peserta diskusi diberi kesempatan untuk berbicara. Kawan-kawan, ini adalah bagian yang paling tidak kusuka karena aku takut tiba-tiba aku disodorkan pengeras suara. Hihi, jujur aku malu. Syukurnya prasangaku tidak terjadi, haha. Mereka satu-satu memberikan pertanyaan dan ada satu orang yang menanggapi pernyataan pembicara perihal buku sastra. Baginya tidak ada buku sastra dan bukan sastra. Ah, diskusi ini seperti dua orang memperdebatkan bubur diaduk atau tidak diaduk saja. Perihal ini, aku berikan pendapatku. Semoga kamu berkenan membacanya.
Membaca ibarat makan
Bagiku, kita perlu selalu lapar saat membaca. Jika kita membaca sebuah buku, alangkah baiknya kita lahap saja. Lezat atau tidaknya itu belakangan. Ketika di tengah-tengah membaca kalian muntah, segeralah berhenti. Ini adalah langkah yang sebaiknya dilakukan.
Sejauh ini, inilah yang aku lakukan terhadap sebuah buku, semua buku kucoba baca; berbagai genre kulahap, walau nantinya bakalan terhenti di tengah jalan. Satu lagi, selayaknya makanan, pastinya kita akan melihat bentuknya dulu, jika tampilannya kurang menjanjikan, jujur aku segan untuk mencobanya, begitu pula buku, jika sampulnya jelek aku akan berpikir dua kali untuk membacanya. Tapi ya akhirnya dibaca dulu aja.
Kalian jangan lupa makan, ya!
Buku adalah buku.
Selayaknya kita, manusia tetaplah manusia walau sifatnya berbeda-beda. Begitu pula buku, ia tetaplah buku walau isinya berbeda. Dengan begini, harus kita pahami ketika sebuah buku mengandung isi yang tidak jelas maka kita maklumi saja, seperti ke manusia; kita perlu ngobrol supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tetapi jika sudah keras kepala, pukul saja kepalanya! Untuk apa kita buang-buang waktu ngobrol dengan orang yang kerasnya seperti karang gigi: keras dan menjijikkan! Nah, begitu juga dengan buku; jika penulisnya ngotot, biarkan saja. Hehe.
Kalau bubur tak diaduk apakah tidak enak
Jika memang buku yang kita baca bukan sastra; lantas kenapa? Bukannya bubur jika tidak diaduk tetap enak-enak saja? Perihal ini, yang perlu dibicarakan bukan wujudnya tetapi rasanya dan otomatis menyangkut siapa yang membuat. Ya, kalau yang buat hanya sekedar memasukan bumbu-bumbu saja tanpa tahu takaran sebenarnya, aku jamin tidak akan enak di mulut. Ah, aku jadi ingin bubur. Aku tipe yang pake kacang, kalau kalian gimana? Nah, kalau orang-orang yang gak pake kacang; sama saja seperti orang yang milih-milih bacaan. Haha. Bercandaa ges.
Akhirnya diskusi berakhir sia-sia. Aku masih duduk di kursiku, menunggu Johan Arda menghampiriku dan memulai sebuah gunjingan; benar ya, Sastra Indonesia ternyata ngeyel! Orang-orang di dalamnya seakan ingin menjewer telinganya hingga merah. Tetapi aku tidak ikut-ikutan kok, sebab aku bersamanya hingga kini. Ia nakal tapi aku tetap menyayanginya. Jika dia diasumsikan bukan dirinya oleh orang lain, aku tidak peduli. Perihal menyelesaikan perdebatan bubur diaduk atau tidak diaduk, sepertinya kita tidak dapat menyelesaikannya. Biarkanlah! Namanya juga selera.
Padang, 6 November 2025





