Barangkali Soal Seni dan Purwakarta, Barangkali Nonsense Belaka
Apa yang dilakukan seni (khususnya sastra) dalam masyarakat yang memilih menghibur diri sekaligus menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan apa pun yang bukan produk kesenian?
Saat masih dua puluh tahunan, saya menanyakan itu pada seseorang dan ia menjawab: untuk menghargai yang kecil, yang remeh, yang dilewatkan.
Sejak SMP saya ingin menjadi penulis. Seorang seniman. Karena semua penulis yang saya baca dan ayah saya yang pelukis adalah orang yang sangat menyenangkan di usia-usia itu. Semua ini mengarahkan saya pada masa-masa SMA dan awal kuliah yang paling menggairahkan. Terutama saat membaca buku; mengkliping puisi dan cerpen dari koran Minggu; mengerjakan mading dan membikin selebaran mini berisi puisi dan menyebarkannya di tengah-tengah kota; dengan perasaan seolah kami bisa “menguasai” Purwakarta, kota kecil yang lagi puber-pubernya dengan gelaran acara kesenian setiap akhir pekan dan hari-hari besar.
Saat itu rasanya masa depan bukan apa-apa bagi saya, karena orang-orang dan karya-karya yang saya kagumi telah menunjukkan banyak hal. Mereka telah menggambar peta hidup untuk saya. Tugas saya tinggal telusuri saja jalannya.
Oh, Tuhan. Betul-betul bocah yang manis, bukan?
Kini saya tahu sedikit tak enaknya “berkesenian”. Setelah banyak hal terjadi, obrolan bergeser ke mana-mana, dan proses berkarya makin banyak dramanya, maka pertanyaan bocah SMA tadi bergeser jadi begini:
Oke, kenapa kita mau-maunya (atau harus) menghargai yang kecil, remeh, dan kerap dilewatkan di kota ini?
Tugas Seniman (Penulis) yang Tersisa
Carlos Fuentes kira-kira menulis seperti ini…
Tanggung jawab riil seorang penulis (secara umum seniman) terhadap masyarakat adalah meletakkan kekuatan imajinasi dan kemampuan komunikasi bahasanya, untuk melawan sikap rendahan politisi yang menggunakan kata-kata demi mendistorsi informasi penting dengan hiruk pikuk, sehingga menjadikan informasi yang ada bukan sebagai pengetahuan.
Lanjutnya, terlalu banyak kerugian bahasa yang ditimbulkan oleh media (tak punya integritas) dan tulisan-tulisan (para buzzer) di bidang politik. Untuk inilah penulis harus membersihkan kembali deretan kata-kata, tegasnya.
Sungguh ucapan yang mengharukan, tapi itu belum semuanya. Karena ada hal lain, yang kecil dan sepele itu, bukan lagi romantisme atas daun-daun keperakan diterpa bias rembulan, melainkan mindset orang biasa seperti kita yang secara naif masih mengira title seniman punya arti lebih dari usahawan umkm, sehingga negara harus memperlakukan mereka sebagaimana raja-raja mataram menjamin seniman mereka dengan insentif, para budak, dan tunjangan-tunjangan.
Jika kita mau sedikit saja menggunakan kacamata Fuentes yang bla-bla-bla itu, setidaknya kita akan setuju bahwa Negara dalam berbagai bentuknya, entah itu UU Kebudayaan, Anggaran Kebudayaan, bahkan Dinas Kebudayaan Daerah, hanya bisa bekerja sekadar mengisi absen dan laporan. Jadi apa yang mau diharapkan dari budaya kerja “asal beres administratif” semacam ini?
Meski begitu saya bersyukur dan berterima kasih pada dua periode pemerintahan Dedi Mulyadi dan legasinya atas kerja-kerja kesenian (jika boleh disebut demikian) di kota ini, setidaknya karena tiga hal berikut.
Pertama ia memperlihatkan bagian paling kocak dari komunikasi politik bermodal narasi usang kebudayaan. Missalnya patung-patung jelek di pusat kota, dan taman-taman air mancur yang norak seperti tiruan ancur-ancuran dari air mancur Bellagio Fountains, di Las Vegas.
Menurut saya ini bukanlah salah dia, tapi karena masa yang berusaha menghancurkan patung beberapa tahun lalu itu, berdalih dengan alasan agama. Padahal kalau mereka hancurkan patung itu karena murni bentuk patungnya yang mengundang tawa, ceritanya pasti akan lain.
Kedua ia menjadikan para seniman dan even kesenian yang saya idolakan tampak seperti lawakan. Saat ia mendatangkan banyak orang yang saya kagumi ke Purwakarta, seperti Godi Suwarna, Zawawi Imron, Kang Acep Zam-zam Noor, ia berhasil membuat saya memandang diri dan karya mereka secara berbeda. Seniman-seniman itu nampaknya tidak pernah peduli pada penerus dan audiens mereka di kota ini. Pasalnya saya selalu mengira, orang-orang itu akan bergaul dengan kami-kami yang muda dan ada di bawah. Melihat orang-orang biasa di tempat kami menulis puisi dan membacakannya. Silakan sebut saya naif.
Ketiga, dan ini yang paling penting, ia menunjukkan bahwa siapapun yang memimpin kota ini cuma punya dua tipe: youtuber dan bintang gosip lokal.
Ketiga hal ini membuktikan bahwa orang-orang seni di mana pun tak peduli dengan orang-orang seni di tempat lain, dan politisi selalu menggunakan versi paling kapiran dari kerja-kerja kebudayaan.
Apa yang akhirnya tersisa dari sepuluh tahun sejak “kesenian dan kebudayaan” jadi kata hits di kota kita?
Masih sama saja. Kita tidak saling menyimak karya-karya di sekitar kita, tidak saling mensupport dan mempromosikan, tidak mendokumentasikan karya dengan baik, dan lebih banyak berlarut-larut dalam gosip daripada perbincangan karya yang sungguh-sungguh.
Kita memang tidak bisa bilang Purwakarta adalah tanah perjanjian yang penuh harapan, tapi mengatakan kota ini seperti ladang mandul juga tak adil. Airnya sudah ada sejak lama, hanya karena pompa airnya bobrok, bukan berarti kita tak bisa mengairi tanah.
Bukankah kita mengerti bahwa menjadi seniman berarti membuat pilihan sadar untuk menjadi yang liyan. Persoalannya hal ini bisa menimbulkan mental korban. Jika tidak waspada kita akan berperangai sama ngawurnya seperti orang bermental korban pada umumnya: selalu menyalahkan pihak lain untuk setiap kemalangan mereka.
Kota ini tak ramah penulis? Bisa jadi. Tak menghargai seniman? Mungkin sekali. Tapi apa kita sudah ramah dan menghargai sesama kita lebih dulu? Apa kita sudah layak mendapat ‘perhatian’ warga kota ini?
Sebagai yang liyan, jangan-jangan problem kita adalah tak menyadari kelebihan dari keliyanan kita. Misalkan, bukankah orang-orang liyan selalu punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang sama liyannya?
Di Purwakarta, kota yang anyep ini sulit menemukan orang-orang yang betulan bahagia. Seniman atau bukan seniman, orang-orang hanya bertahan hidup. Mereka marah, ragu, takut, dan saling curiga. Menyakitkan rasanya melihat itu semua, tapi di saat yang sama betapa menakjubkannya melihat semuanya tampak baik-baik saja.
Pada akhirnya apa yang saya bicarakan saat ini, bisa jadi bukan soal kesenian, seniman, bahkan bukan soal Purwakarta. Dengan segala hormat, ini mungkin hanyalah gumaman anak 30 tahun yang mengira dirinya berhak menggunakan kekuatan kata-kata dan imajinasinya, untuk melamunkan kota ini lebih dari yang telah ia lihat dan dengar. Bukan untuk melawan politisi atau media, tapi mencoba mengurai kejumudan kita sendiri.
Ahmad Farid
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Al-Quran & Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bagian dari Gusdurian Purwakarta dan Swara Saudari Purwakarta.
- Trending
- Comments
- Latest
A Happy Notes
Memantau Pola Cinta
Darwish Membahasakan Kekerasan
Baiat Pegiat Literasi Purwakarta
Dialog-Dialog Plato
Dukung Penulis Favoritmu
-
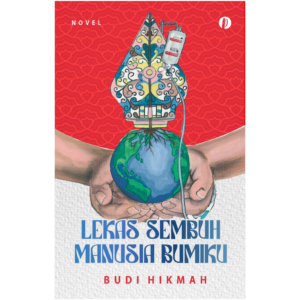 Lekas Sembuh Manusia Bumiku
Rp69.000
Lekas Sembuh Manusia Bumiku
Rp69.000
-
 Unboxing
Rp65.000
Unboxing
Rp65.000
-
 Mendengar Radio Sendirian
Rp69.000
Mendengar Radio Sendirian
Rp69.000
-
 Klothek'an
Rp75.000
Klothek'an
Rp75.000
-
 Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya
Rp75.000
Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya
Rp75.000
-
 Yang Absen dari Pendidikan Kita
Rp75.000
Yang Absen dari Pendidikan Kita
Rp75.000
-
 Menjadi Perempuan Setiap Hari
Rp75.000
Menjadi Perempuan Setiap Hari
Rp75.000
© 2018 Nyimpang Coop - Part of CV Pustakaki Press .














