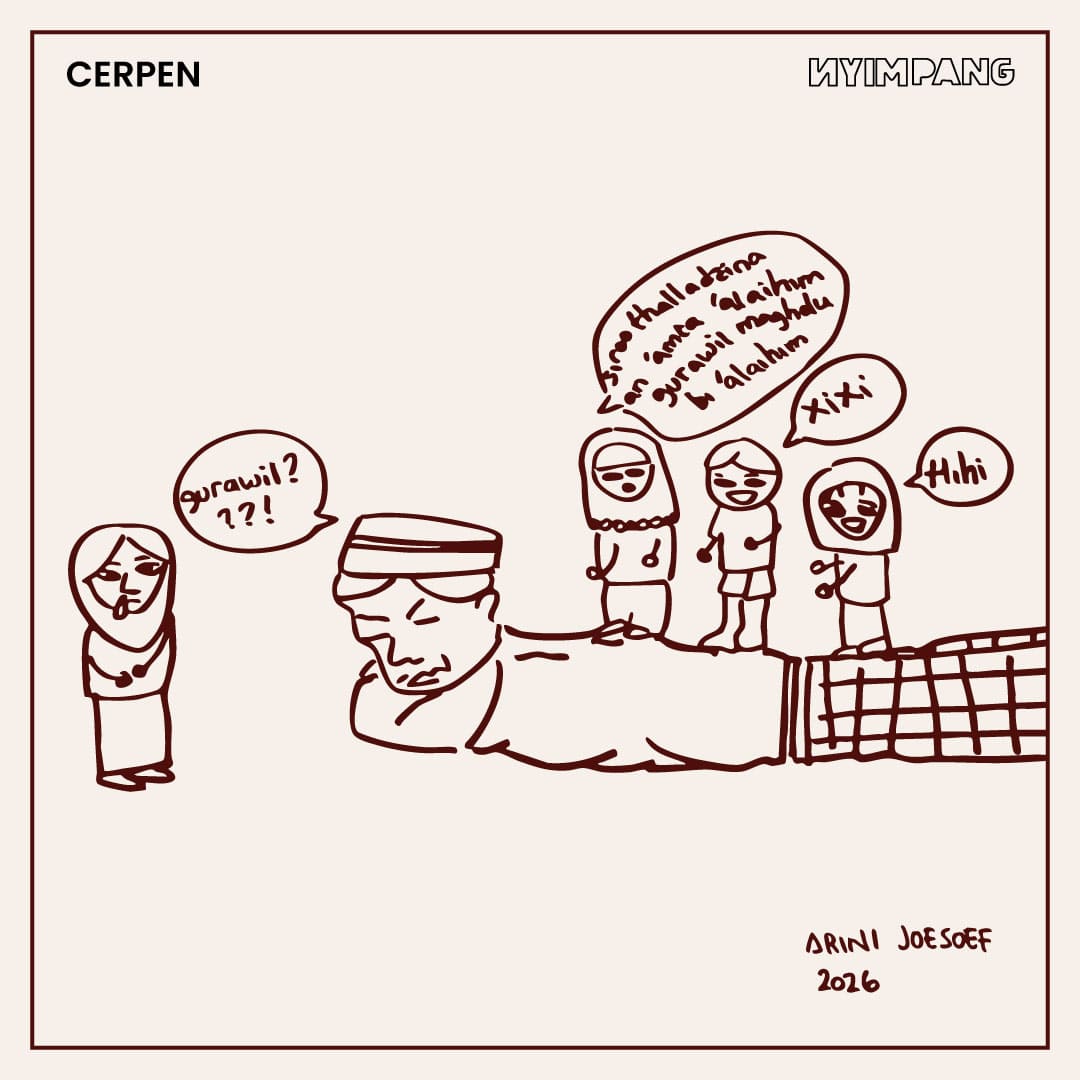Dari Bilik Toilet Fancy di Kota Ini

Aku sudah bekerja 9 bulan di sini, dan kalau saja aku hamil, maka seharusnya aku melahirkan sekarang, tapi alih-alih melahirkan atau beradaptasi, aku malah semakin payah di hadapan AC gedung mewah di Jakarta.
Aku bekerja di lantai 40, di sebuah gedung fancy yang bahkan naik liftnya saja seperti sedang naik elf ke Sumedang. Kau tahu, kan? Supir elf terkenal dengan gaya nyetir khas drift, hanya saja rutenya Cadas Pangeran. Mirip-mirip Kelok Sembilan atau Jalan Pangandaran.
Bahkan di minggu-minggu pertama aku memulai perjalanan karir baruku sebagai personal assistant di gedung ini, aku harus selalu ke kamar mandi dan kalau sedang beruntung, aku hanya tinggal merogoh-rogoh tenggorokanku biar muntah. Tapi kalau itu hari sialku, tentu semua sarapanku akan langsung ke luar dari mulut. Huek.
Kalau ada yang bilang aku norak, aku sama sekali tidak marah karena memang begitu kenyataanya.
Aku lahir dan tinggal lama di kabupaten industri di pinggiran. Siangnya selalu panas, berdebu, dan udaranya bercampur bau-bau pelet ayam atau sesekali amoniak.
Meskipun di rumahku ada AC, tapi sekeluarga kompak enggan menyalakannya. Selain menghemat biaya listrik, kami semua tidak terbiasa saja dan lebih memilih kipas angin atau blower untuk mengatasi hawa panas.
Di kota asalku, kalau kita ke luar rumah di tengah hari dan kita menaruh panci, saya rasa suhunya sudah bisa dipakai untuk membuat daging kurban empuk.
Banyak hal yang kubenci dari Jakarta Selatan. Orang-orang yang selalu memenuhi kereta dengan parfum-parfum yang dibeli dengan gaji UMR nanggung, garang-gusuh pejalan kaki, mobil-mobil mewah yang enggan tertib. tetot-tetot, lift yang bikin muntah, dan AC kantor yang dinginnya kelewatan.
Eh! Mati aku! Hari ini aku lupa membawa jaket. Orang-orang selalu bilang begini,
“Ah enggak kok, aku biasa aja. Kamunya aja kali,”
atau “Kok AC-nya gak dingin, ya?” waktu aku menaikkan suhu AC di ruangan itu.
Ya ya ya. Gimana orang kota aja, lah. Kadang aku membalas kalimat-kalimat sok itu dengan julidan yang tak kalah sok juga di dalam hati.
Hari ini, aku menggunakan kemeja tipis yang kubeli dari thrifting di Senen. Dingin ini bagiku bukan dingin yang bisa ditoleransi.
Aku pernah disentri karena suhu dingin, berakku jadi air, dan itu semua gara-gara aku kedinginan tidur di lantai. Lantai kabupaten pinggiran itu. Ya, bisa dibayangkan kalau tidur di lantai yang dingin tak berkarpet saja berakku jadi cair, apalagi AC kutub begini.
Mungkin itu sebabnya aku tak cocok jadi orang kaya yang hidup enak, tapi tolong! Perutku sakit sekali!
Aku mendekatkan diri ke kaca dan mencoba menghangatkan diri, tapi kaca itu tebal dan cukup menahan panas matahari, sehingga hasilnya gak begitu kentara. Aku tetap saja kedinginan, perutku sakit, dan aku mau berak!
Argh! Aku benci berak di toilet fancy di sini! Selama 9 bulan, kalau aku kebelet, aku selalu menahannya sampai di kosan.
Kau tahu? toilet di gedung mewah ini terlampau canggih buatku. Toilet di gedung ini, entah itu di lantai dasar atau di lantai ini sama saja membuatku jengah!
Lantainya marmer krem, mengkilap sekali seperti wajah-wajah krim merkuri. Biliknya pun mewah. Ada yang kaca, ada yang kayu mahal, atau apa lah itu. Selalu ada pengharum ruangan yang menyemprot otomatis di setiap sudut dindingnya, dan sunyi sekali! Setiap embusan napas bisa terdengar di sini. Apalagi kucuran kencing atau tahi yang jatuh ke air, lalu kalau tahi itu tidak ke luar berbarengan dengan semprotan pewangi ruangan, maka Argh!
Semuanya serba bagus, bersih, dan aku jadi sadar bahwa ruangan seindah itu terlalu mahal untuk hal-hal manusiawi seperti buang air.
Setiap bilik hanya berukuran setengah. Dari luar, kita bisa melihat kaki orang yang di dalam, kadang dari sekat yang setipis rambut di pintu bilik itu, kita juga bisa sih lihat orang lain masuk, tapi ya ngapain juga?
Ini tak bisa ditahan, aku segera beranjak sambil berupaya elegan. Terasa hawa-hawa ingin kentut, tapi aku gak mau tiba-tiba kentutku berbonus, jadi ya sudah aku tahan juga kentutnya seperti orang-orang saleh yang berupaya menjaga wudunya.
Toilet itu kosong melongpong. Sudah tak kuhiraukan lagi lah perkara setan-setanan!
Aku lalu langsung masuk ke bilik tengah, karena ya jujur aku masih takut kalau di pojok, dan kalau bilik itu penuh dan semuanya sedang di dalam bilik, maka setidaknya aroma busuk perutku gak terlalu kentara waktu baunya menyebar.
Yang paling kanan bisa dicurigai, yang paling kiri bisa dicurigai, dan aku akan ke luar dari bilik toilet sambil berlagak bilang, “Ih bau banget” sambil pura-pura mau muntah padahal aku yang bau. Ehe.
Ya, begitu lah aku.
“Astaga! WC duduk lagi! Ah bodo amat”
Aku tak terbiasa menggunakan WC duduk, dan hasilnya aku pun berjongkok di toilet duduk itu. Konyol, tapi kalau gak gitu aku harus menahan rasa sakit itu karena tahiku susah ke luar.
Aku berusaha sekeras mungkin untuk menyamarkan suara, satu diantaranya dengan menyalakan bidet terus-terusan, dan aku bukan orang yang suka mengumpulkan tahi. Meskipun aku berupaya keras menghemat air dengan mandi 2 gayung setiap waktu, tapi untuk urusan WC, nanti dulu! Aku selalu membanjur sampah-sampah perutku sepersekian detik begitu mereka muncul (supaya gak bau juga, sih) dan ahhh! Lega sekali.
Aku mematikan bidet, dan sekali lagi aku flush toilet itu. Tapi aku masih belum ingin beranjak. Aku masih jongkok di sana sambil melihat stiker larangan jongkok di toilet duduk. Pokoknya kalau sampai toilet ini rusak kujongkoki, salah sendiri! Memangnya dipikir semua orang bisa berak di toilet duduk apa?!
Aku masih jongkok, siapa tahu masih ada yang mau lewat.
Lalu, masuk langkah sepatu. Bukan sepatu biasa sih dari suaranya. Sepertinya hak tinggi dan runcing. Bunyinya tik-tok, tik-tok.
Aku diam, menahan. Tahi yang tadi sudah siap keluar, tertarik kembali ke perut. Begitulah nasib orang kampung yang tak terbiasa punya privasi. Sekali ada orang masuk, mekanisme pertahanan dirinya langsung aktif begitu saja.
Suara sepatu itu berhenti di bilik sebelahku, bilik yang paling ujung dan dekat tembok. Ada bunyi tas diletakkan di gantungan, lalu suara tangan merogoh isi tasnya. Ada suara krenceng-krenceng seperti lonceng atau kunci, kemudian suara plastik dibuka perlahan.
Aku tidak berniat menguping tentu saja, tapi seperti yang sudah kubilang sebelumnya, suara-suara di toilet ini terlalu nyaring! Kau bisa dengar semua hal: tarikan napas, gesekan tisu, bahkan detik-detik seseorang sedang mengetik chatting sekaligus.
Aku lantas mendengar suara kencing. Tak lama, kudengar suara napas tercekat. Setelah itu tangis kecil. Tangis perempuan. Aduh! Kuntilanak tak mungkin pakai sepatu hak!
Aku mulai gelisah. Perutku masih sakit, tapi suasana berubah jadi bingung. Aku gak tahu yang dialami perempuan di bilik sebelah. Kadang juga aku suka tiba-tiba nangis saja kalau sedang melamun, tapi brug dengan bunyi yang kecil sekali. Aku mengintip sedikit dari bilikku dan celah bawah itu menunjukkan test pack. Dua garis.
Aku tertegun. Sebelum sempat menata ekspresiku, terdengar suara dari ponselnya. Nada deringnya membuatku kaget dan hampir jatuh. Aku bahkan baru ingat kalau ia tak mungkin tahu aku di sini karena kakiku gak menyentuh lantai sama sekali.
Telepon itu ia jawab dengan suara yang pelan, dan suaranya berbalapan ria dengan air mata dan seguk-seguk khas orang menangis,
“Pak, saya hamil…”
“Iya, Pak. Saya udah pastiin, barusan. Bapak janji kan mau ceraikan istri Bapak? Bapak janji kan mau nikahin saya? Bapak gak ninggalin saya, kan?”
Si perempuan itu kembali berbicara
“Tolong, Pak… saya nggak tahu harus gimana.”
Aku menggigit bibir. Aku bahkan lupa kalau masih ingin berak. Ada rasa asing antara iba dan jengkel. Iba karena aku tahu hal-hal seperti ini akan merugikan si perempuan, jengkel karena bisa-bisanya orang yang bekerja dan mencari uang masih juga mau dihamili suami orang! Padahal kan ada teknologi canggih yang namanya kondom! Argh!
Aku lalu mencoba mendengar tajam-tajam suara perempuan itu,
“Apakah dia orang dari kantorku? Atau dia orang dari kantor sebelah? Kalau iya kantor sebelah, kantor yang mana? Anak perusahaan yang mana?”
Sebab aku tentu tahu, 1 lantai seluas ini hanya disewa oleh perusahaanku dan anak-anak perusahaannya. Jadi, aku pastilah harus bisa menebak suara perempuan ini. Bukan, bukan! Aku tidak bergosip dan tidak membocorkan suatu rahasia, apalagi sepenting ini. Aku hanya ingin membantu saja.
Semakin kudengar tangis perempuan itu, semakin aku tak merasa kenal dengannya. Lagipula, anak perusahaan itu banyak sekali dan tidak semua karyawannya ku kenali!
Suara di seberang telepon terdengar samar, tapi nadanya bisa kutebak. Laki-laki yang terbiasa memberi perintah.
“Tenang saja, saya atur. Kita ketemu di depan lift jam 3. Kita pergi bersama ke obgyn kenalan saya.”
Kalimat-kalimatnya membuat saya merinding. Beberapa menit kemudian, kudengar flush, lalu suara tas diseret keluar bilik.
Aku tetap diam di dalam. Aku menunggu, meski perutku mulai berontak lagi. Setelah aku pastikan perempuan misterius itu sudah ke luar, aku lalu melanjutkan urusanku. Aku cukup lama menghabiskan waktu di toilet. Lalu, kakiku sedikit kesemutan, dan aku buru-buru menghadap bosku, karena 30 menit lagi ia harus meeting dengan BOD di lantai 42, dan sebagai personal assistant, aku harus memastikan kebutuhan presentasinya terpenuhi.
Aku kemudian menuju ke mejaku, yang berada tepat di depan ruangannya. Aku lalu masuk dan mengetuk pintunya. Aku memperhatikannya terburu-buru memasukkan laptopnya ke dalam tas.
“Aduh! Dia pasti sudah mau ke atas!” ucapku dalam hati karena takut ia akan memarahiku sebab terlalu lama pergi
“Eh, sorry. Kali ini lu aja yang presentasi, ya. Gue ada urusan mendadak dulu. Gue udah bilang sama direksi untuk lu yang present ke mereka. Sorry banget gue buru-buru, istri gue mau ke rumah sakit.”
Aku terkejut. Meskipun aku tahu aku pintar dan mampu, tapi mempresentasikan revenue anak-anak perusahaan tentu saja bukan tugasku!
Bosku kemudian pergi, dan aku duduk dengan lega di kursi. Aku melihat jam di meja.
Waduh. Jam 3.